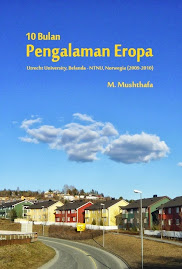Bila orang pada umumnya menyatakan bahwa pengetahuan itu memberi terang, saya kini punya pikiran lain. Ada kalanya pengetahuan tertentu justru menggelisahkan. Setidaknya, itulah yang saya alami pagi tadi.
Bersilaturahmi di hari lebaran, di rumah seorang famili, tadi pagi saya disuguhi air minum dalam kemasan. Merknya Aqua. Saya tak punya masalah kesehatan dengan air minum dalam kemasan. Namun saya bermasalah dengan merk Aqua—gara-gara pengetahuan saya. Apalagi, air minum yang isi bersihnya 240 ml itu tepat dikeluarkan dari pabrik Aqua kedua di Pandaan yang telah beroperasi sejak 1984. Saat saya melirik ke labelnya, tampak jelas tertulis: “Mata Air Pandaan, Gunung Arjuno”.
Kegelisahan saya itu terjadi karena pengetahuan saya. Saat di Trondheim, Norwegia, bulan April lalu, saya sempat membaca sebuah berita di laman Media Indonesia Online (yang sekarang sudah tak bisa diakses, tapi masih terdokumentasi di laman Walhi) tentang aktivitas perusahaan Aqua yang mengancam debit air tanah di Gunung Arjuno. Dilaporkan bahwa PT Tirta Investama (Danone Aqua) setiap hari mengeksploitasi 1,5 juta liter air tanah di lereng Gunung Arjuno. Akibatnya, warga Pasuruan banyak yang mengeluh karena sumber mata air mereka banyak yang mati.
Saya mencoba membayangkan angka 1,5 juta liter itu, dan saya lalu teringat pada air botol Aqua kemasan 1,5 liter. Jika air yang dieksploitasi setiap hari itu dikemas dengan botol ukuran 1,5 liter, maka itu akan sama dengan sejuta botol kemasan 1,5 liter! Imajinasi visual tentang sejuta botol yang berderet tiap hari, siap diangkut, didistribusikan, dan dijual itu, terasa mengganggu pikiran saya. Ke manakah mereka itu semua akan berakhir?
Satu setengah juta liter! Jika setiap orang rata-rata memakai air bersih sebanyak 150 liter per hari, maka air yang dieksploitasi Aqua setiap hari di Pasuruan itu cukup untuk jatah sepuluh ribu orang yang tinggal di Pasuruan!
Ini adalah sejenis pengetahuan yang menggelisahkan. Atau, dalam istilah Michael Moore, the awful truth. Dan pengetahuan ini kemudian menemukan momentumnya untuk menggelisahkan saya tadi pagi.
Sebenarnya, masalah terbesar yang saya hadapi dalam kasus ini bukan terletak pada aspek teoretis atau konseptual. Masalahnya ada pada tindakan, yakni bagaimana saya menyikapi dan merespons pengetahuan saya itu. Pengetahuan itu telah merepotkan saya, memaksa saya untuk berpikir kembali untuk menjulurkan tangan saya meraih satu-satunya pilihan air minum yang tersedia di tempat itu pagi tadi.
Saya lalu teringat pembahasan Franz Magnis-Suseno tentang kebebasan, yang kemudian menyadarkan saya bahwa pada saat semacam tadi pagi itulah saya sebenarnya dapat menegaskan bahwa saya memiliki kebebasan. Saya punya kebebasan karena saya memiliki pilihan—dengan berbagai konsekuensinya.
Dan saya pun tahu, pilihan apa yang sebaiknya saya ambil pagi tadi. Ya, setidaknya pagi tadi—entah lain kali.
Rabu, 17 November 2010
Ironi Pengetahuan
Label: Daily Life, Environmental Issues
Selasa, 16 November 2010
Bagikan Pengalamanmu, Bagikan Kisah-Kisahmu

Kini yang tersisa adalah penyesalan. Waktu jelas tak bisa terulang. Sekarang saya hanya bisa meratap mengapa dahulu saya tak rajin menuliskan semuanya—pengalaman penuh warna yang sebelumnya bahkan tak terbayangkan akan dapat saya lewati.
Hari Kamis dua pekan yang lalu, di kelas Jurnalistik, setelah beberapa pekan awal memberi bekal wawasan pengetahuan dan pengantar umum tentang jurnalisme, saya mencoba menanamkan semangat kepenulisan kepada murid-murid setingkat SLTA di siang itu. Saya memperkenalkan gagasan tentang jurnalisme warga (citizen journalism) kepada mereka dengan sebuah kerangka yang “agak politis”. Saya katakan bahwa media arus utama tak selalu sudi berbagi ruang untuk menuturkan hal-hal penting yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, kita sebagai warga masyarakat mestinya juga terlatih dan memiliki kemampuan untuk menuliskan hal-hal penting di sekitar kita. Bahkan hal yang personal pun terkadang dapat memiliki nilai penting yang lebih luas, yakni dapat menjangkau pada kepentingan masyarakat luas.
Saat berdiskusi tentang jurnalisme warga itu, pikiran saya sebenarnya tengah mendua. Jika yang keluar dari mulut saya adalah semacam upaya menyulut semangat murid-murid untuk menulis, benak saya saat itu dipenuhi dengan penyesalan. Pikiran saya melayang ke Belanda, tepat setahun yang lalu, saat saya mencoba mencatat kisah daun-daun yang berjatuhan di musim gugur, lalu juga perjalanan kereta di suatu senja dari Leiden ke Utrecht.
Rasa sesal yang menyelimuti pikiran saya muncul saat saya menyadari betapa banyak pengalaman-pengalaman menarik lainnya yang tak sempat saya catat. Pengalaman di hari-hari pertama saat baru tiba di Belanda di tengah menjalankan ibadah puasa, misalnya, hanya sempat saya catat dengan cara yang terlalu kaku dan “kering”.
Setiba di Utrecht awal September tahun lalu, saya memang langsung disambut dengan berbagai kesibukan, mulai dari perkuliahan dengan tugas-tugas yang langsung berjibun, urusan administrasi dengan Kantor Registrasi Kota dan kampus, termasuk juga pengenalan lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tambahan lagi, itu semua harus dilakukan bersama penyesuaian cuaca baru dan antisipasi yang kurang matang.
Tapi kalau dipikir-pikir, mestinya semua situasi itu tak bisa menjadi alasan atas kelalaian saya melewatkan momen-momen yang tak tercatat itu. Justru sebaliknya: mestinya itu semua menjadi dorongan sehingga momen yang penuh warna itu dapat terekam dalam sebuah komposisi yang dapat dibaca di kemudian hari.
Namun saya patut juga bersyukur bahwa selama di Utrecht dalam waktu lima bulan, lebih sepuluh tulisan telah saya tulis. Mengingat kembali masa-masa itu setahun yang lalu, saya berpikir bahwa salah satu faktor yang membantu saya menjaga semangat kepenulisan saya waktu itu adalah Blog Pengalamanku yang dikelola oleh Radio Nederland Wereldomroep (RNW) yang memberi ruang bagi orang-orang Indonesia di Belanda untuk membagikan cerita dan pengalaman mereka. Bahkan saya berhasil mendapatkan tiga sovenir dari Blog Pengalamanku untuk tulisan-tulisan yang saya kirimkan—yakni iPod Nano yang kemudian menemani hari-hari saya bersepeda dan menikmati Belanda dan Eropa, hardisk eksternal 1 terra yang lalu dibuat untuk menyimpan file-file penting yang saya dapatkan di Eropa, dan E-Book Reader yang sungguh bermanfaat buat saya.
Setelah sekitar lima bulan kembali beraktivitas di kampung halaman, saya terkadang geregetan saat membaca tulisan-tulisan pengalaman teman-teman saya di Eropa, baik yang ditulis di blog pribadi maupun Blog Pengalamanku RNW. Sekali lagi, saya kini hanya bisa menyesal. Lebih dari itu, bahkan kesibukan-kesibukan di kampung halaman pun belakangan telah melumpuhkan semangat saya untuk terus menulis.
Memang benar, waktu tak dapat dibeli. Momen dan kesempatan hanya datang satu kali. Karena itulah, selagi Anda sedang berada dalam sebuah ruang pengalaman yang unik, semisal pengalaman bertajuk “pengalaman-Eropa”, maka kesempatan semacam itu jangan disia-siakan. Tuliskan, bagikan!
Label: Literacy
Senin, 30 Agustus 2010
Problem Etis dalam Pembiayaan Pendidikan
Pemiskinan Negara, Kepentingan Publik, dan Otonomi Pendidikan Masyarakat
Dalam berbagai level kehidupan, pendidikan memainkan peran yang sangat strategis. Pendidikan memberi banyak peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan. Dengan pendidikan yang baik, potensi kemanusiaan yang begitu kaya pada diri seseorang dapat terus dikembangkan. Pada tingkat sosial, pendidikan dapat mengantarkan seseorang pada pencapaian dan strata sosial yang lebih baik. Secara akumulatif, pendidikan dapat membuat suatu masyarakat lebih beradab. Dengan demikian, pendidikan, dalam pengertian yang luas, berperan sangat penting dalam proses transformasi individu dan masyarakat.
Dengan menyadari nilai strategis pendidikan tersebut, dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, muncul pertanyaan awal: siapakah yang memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan? Negara, masyarakat, atau kedua-duanya?
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan ayat (3) menyebutkan bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Pasal ini dapat dilihat sebagai landasan normatif yang mewajibkan negara untuk memenuhi hak setiap warga negara agar bisa mendapatkan pendidikan.
Kewajiban negara untuk menyediakan dan memenuhi hak warga negara atas pendidikan dibangun di atas asumsi yang terkait erat dengan bagaimana kehidupan bermasyarakat terbentuk. Dalam teori kontrak sosial, dijelaskan bahwa masyarakat politis terbentuk berkat adanya kontrak atau konsensus nasional. Ada kesepakatan bersama tentang nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat dan tujuan yang dihendak diraih. Kesepakatan ini juga terkait dengan sarana, proses, dan prosuder pelaksanaannya (Sugiharto & Rachmat W., 2000: 46-47). Dalam konteks Indonesia, hal ini tergambar dalam Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945.
Jadi, untuk memenuhi amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang kemudian diturunkan ke dalam pasal 31 UUD 1945, negara, di antaranya, berkewajiban untuk membiayai pendidikan. Perlu dicatat di sini bahwa pembiayaan adalah salah satu bagian dari pengelolaan. Artinya, terkait pendidikan, negara secara umum berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan pendidikan (termasuk dalam hal pembiayaan) untuk dapat memenuhi hak setiap warga negara. Ini adalah premis pertama yang dapat dirumuskan dalam diskusi kita ini.
Sampai di sini, jika disepakati bahwa pada tingkat tertentu negara memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan, muncul pertanyaan lainnya: bagaimana dan di manakah posisi masyarakat? Apakah masyarakat juga punya kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan? Pertanyaan ini juga mengimplikasikan pertanyaan lain: jika kewajiban negara untuk membiayai pendidikan tidak bersifat penuh, mengapa pada tingkat tertentu partisipasi publik dalam pembiayaan pendidikan itu tetap harus ada dan diperlukan?
Di balik uraian dan pertanyaan terakhir ini, problem etis yang mungkin muncul dapat ditelusuri dengan mempertanyakan: adakah dampak/problem etis yang dapat muncul ketika negara dalam batas tertentu memiliki kewajiban dan wewenang untuk membiayai dan mengelola pendidikan? Adakah dampak/problem etis ketika publik tidak berpartisipasi pada pembiayaan pendidikan?
Problem etis ini pada dasarnya adalah persoalan lanjutan dari diskusi soal legitimasi etis penggunaan dan batas wewenang kekuasaan negara. Apakah “negara memiliki hak untuk mencampuri segala urusan masyarakat, untuk menentukan segala-galanya?” (Magnis-Suseno, 1994: 177).
Aspek normatif dan problem etis yang muncul dari masalah pembiayaan pendidikan ini akan berusaha didiskusikan dalam tulisan ini. Diskusi akan juga banyak terfokus pada problem umum pendidikan di Indonesia, yang baik secara langsung atau tidak dipandang terkait erat dengan asumsi kewajiban dan wewenang negara untuk mengelola pendidikan.
Kewajiban Negara
Anies Baswedan, rektor Universitas Paramadina dan ketua Gerakan Indonesia Mengajar menyatakan bahwa dalam hal pemberantasan buta huruf, Indonesia memiliki prestasi yang cukup membanggakan. Saat republik ini berdiri, angka buta huruf mencapai 95 persen (di sumber yang lain Anies menyebut 80 persen). Dan sekarang, angka itu turun menjadi 8 persen (Baswedan, 2010). Bahkan, menurut Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional, Hamid Muhammad, total jumlah warga buta aksara 9,7 juta atau 5,97 persen dari jumlah penduduk Indonesia (Kompas, 28/04/2009).
Namun dari banyak segi yang lain, dunia pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi banyak masalah. Di antara yang utama adalah soal akses. Menurut data Depdiknas, pada tahun pelajaran 2007/2008, 2,2 juta anak usia wajib belajar (7-15 tahun) tak menikmati pendidikan dasar sembilan tahun terutama karena faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran orangtua. Untuk anak usia 16-18 tahun, ada 5,5 juta yang tak bersekolah. Sedangkan usia 19-24 tahun, 20,7 juta tak mengenyam bangku kuliah (Kompas, 11/12/2009).
Akses yang sulit ini menjadi semakin problematis ketika kesenjangan akses pendidikan ini dalam kasus tertentu didukung oleh kebijakan negara. Darmaningtyas, misalnya, menyorot kebijakan pengembangan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI) yang justru mendorong terbentuknya kastanisasi sekolah. Keberadaan sekolah yang sebelumnya berlabel “unggulan” ini dilegitimasi dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003. Pasal 50 Ayat 3: ”Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan jadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Masalahnya adalah: sekolah jenis ini mendapat gelontoran dana yang cukup besar dari pemerintah, dan pada saat yang sama diberi kebebasan untuk memungut dana tambahan dari murid. Pendidikan menjadi elitis, dan akses masyarakat miskin untuk jenis pendidikan semacam ini seperti menjadi mustahil (Darmaningtyas, 2010).
Jika menurut UUD 1945 negara berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan warga negaranya, bagaimana kita menilai pemenuhan kewajiban tersebut? Apakah negara sudah dapat dikatakan berhasil menunaikan kewajibannya? Dalam buku Utang dan Korupsi Racun Pendidikan (2008), Darmaningtyas menyatakan bahwa negara belum dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Tyas menyebut tiga faktor penyebabnya, yakni utang luar negeri, korupsi, dan inefisiensi.
Warisan utang luar negeri yang menggunung telah berakibat pada berbagai sektor kepentingan publik. Pada tahun 2003, total utang Indonesia mencapai US$ 150 miliar. Jumlah ini melampaui produk domestik bruto (GDP) yang dihasilkan Indonesia. Pada 2004, total pembayaran bunga pinjaman memakan 92,67% total penerimaan negara, yakni sebesar US$ 7,9 miliar. Karena beban pembayaran utang begitu tinggi, maka dampak yang paling terasa oleh masyarakat saat ini adalah pengurangan subsidi untuk berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian, dan sebagainya.
Korupsi terjadi di mana-mana, mulai dari lembaga pemerintah, BUMN, lembaga legislatif, bahkan juga dalam dunia pendidikan. Tyas menguraikan bahwa dana pinjaman untuk beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) untuk membantu sektor pendidikan pada saat krisis ternyata juga banyak mengalami kebocoran dan salah sasaran. Temuan Tim Pengendali Program JPS yang diketuai Mar’ie Muhammad memaparkan bahwa salah sasaran program beasiswa SD-SMTA mencapai 60%. Pada saat yang sama pemerintah justru mengucurkan dana BLBI yang mencapai 144 triliun rupiah untuk para pengusaha yang hingga kini penyelesaiannya masih gelap.
Sementara itu, inefisiensi terjadi baik terkait dana pendidikan, dana negara, atau dana masyarakat. Karena tak efisien, dana yang memang terbatas itu jauh dari sasaran, bocor ke mana-mana, atau diterima oleh orang yang tidak tepat. Di antara contoh yang dikemukakan adalah pemborosan dana dalam pelaksanaan pilkada atau pemilu. Contoh lainnya yang cukup dekat dengan kita adalah kasus pembangunan gedung SMPN 2 Pasongsongan, Sumenep. Bangunan sekolah tersebut memiliki sembilan ruang kelas, satu ruang guru, satu ruang perpustakaan, dan satu ruang laboratorium. Padahal, ketika Tyas berkunjung ke sana tahun 2002, sekolah itu hanya memiliki 63 murid—artinya, hanya membutuhkan 3 ruang kelas. Di Madiun dibangun gedung senilai Rp 43 miliar untuk rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang akhirnya mangkrak dan tak digunakan, karena pejabatnya belum siap menjalankan program tersebut. Di sekolah, inefisiensi juga banyak ditemukan, mulai dari program study tour, penyediaan seragam, buku LKS, dan sebagainya.
Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa pemenuhan kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan bagi warga negara sejauh ini tampak problematis, di sisi yang lain kita juga melihat bahwa semenjak era reformasi dan era otonomi daerah peluang masyarakat dan lembaga pendidikan untuk memperoleh bantuan dana (pembiayaan) pendidikan dari pemerintah menjadi semakin lebar. Isu reformasi, demokratisasi, dan transparansi memaksa pemerintah untuk lebih terbuka mengelola dana yang dimilikinya, termasuk dana pendidikan. Berbagai jenis bantuan dan tunjangan untuk pendidikan semakin banyak. Hal ini terjadi juga karena didorong oleh amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Hal yang cukup menarik untuk direnungkan adalah: apakah setelah negara, pada tingkat tertentu, memberi perhatian yang lebih pada sisi pembiayaan, hal itu kemudian diiringi dengan peningkatan mutu pendidikan?
Selain itu, penting juga dicatat bahwa hingga kini pun, masalah korupsi dan inefisiensi masih terus membelit dunia pendidikan kita. Tambahan lagi, meski faktanya berbagai jenis bantuan dana tampak semakin banyak diturunkan ke sekolah-sekolah, negara juga diam-diam mulai melepas tanggung jawabnya dari kewajiban untuk membiayai pendidikan. Ini di antaranya tampak dalam UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan—yang beberapa bulan lalu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (lebih jauh, baca dua tulisan Darmaningtyas di Kompas, 7 April 2010 dan 3 Mei 2010 tentang masalah ini, termasuk tentang ancamannya meski UU tersebut sudah dibatalkan MK).
Peran Serta Masyarakat
Jika negara tampak gagal dan bahkan mulai menghindar memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pendidikan bagi warga negara, lalu bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pendidikan?
Menteri Agama, Suryadharma Ali, pernah menyatakan bahwa dari 41 ribu madrasah yang ada di Indonesia, 92 persen di antaranya dibangun pihak swasta—hanya 8 persen yang dibangun oleh pemerintah. Di beberapa daerah, mayoritas madrasah didirikan oleh kiai dengan tujuan mengabdi untuk kepentingan masyarakat (Kompas, 15/5/2010).
Keterlibatan kiai atau pesantren dalam proses pendidikan di Indonesia sebenarnya memiliki akar historis yang panjang. Kita tahu bahwa cukup banyak pesantren di Indonesia yang berdiri sejak paruh kedua abad ke-19 yang lalu dan punya andil yang besar dalam proses pendidikan di masyarakat. Menurut Gus Dur, pesantren mula-mula berfungsi sebagai instrumen islamisasi, tapi kemudian beralih ke fungsi kemasyarakatan yang lebih luas, yakni dengan terlibat dalam proses transformasi kultural yang bersifat total. Ini tergambar dari kisah para kiai yang dengan sengaja mendirikan pesantren dengan sengaja di daerah-daerah “hitam” pinggiran kota (Wahid, 2001: 93).
Sebagai unit kultural, pesantren sering pula digambarkan berperan sebagai subkultur. Pesantren memiliki kelengkapan nilai, bangunan sosial, dan tujuan-tujuannya sendiri. Gus Dur menyebut tiga nilai utama di pesantren, yakni (1) cara memandang kehidupan secara keseluruhan sebagai ibadah; (2) kecintaan pada ilmu-ilmu agama yang tertanam begitu kuat; dan (3) ketulusan bekerja untuk tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan, posisi pesantren sebagai subkultur pada tingkat tertentu menunjukkan adanya watak mandiri (otonomi) pesantren, baik menyangkut sistem dan struktur pendidikan (Wahid, 2001: 97-103).
Interaksi pesantren sebagai subkultur dengan institusi lain di luarnya, termasuk negara, sangat menarik untuk diamati. Saat ini, cukup banyak pesantren telah melakukan sejumlah kompromi utamanya dengan negara terkait dengan pengelolaan pendidikan. Masuknya sistem pendidikan formal ala negara, dengan berbagai konsekuensinya, pada satu sisi memperlihatkan lenturnya watak mandiri (atau otonomi) pesantren dalam mendefinisikan dan mengelola sistem pendidikan yang dimilikinya.
Jika hal semacam ini digambarkan sebagai bentuk akomodasi pesantren atas aspirasi masyarakat agar pendidikan yang diikutinya di pesantren juga masuk dalam pengakuan formal negara, maka ini mungkin dapat dilihat sebagai—apa yang oleh Gus Dur disebut—contoh keterbatasan watak subkultur pesantren. Mungkin situasi ini dapat pula digambarkan sebagai keadaan ketika sebuah pesantren tak mampu melaksanakan tugas transformasi kulturalnya secara total, sehingga ia justru akan ditransformasikan oleh keadaan atau institusi lain di luarnya (Wahid, 2001: 102).
Terkait dengan pembiayaan pendidikan, saat ini sangat banyak lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (swasta), termasuk juga pesantren, yang menikmati gelontoran dana dari pemerintah. Pertanyaan reflektif yang dapat diajukan adalah: seberapa jauh hal tersebut memengaruhi watak dan terutama nilai-nilai utama pendidikan yang sebelumnya menjadi pedoman lembaga tertentu yang dimiliki oleh masyarakat (seperti pesantren)?
Pada titik inilah soal partisipasi masyarakat menemukan poin pentingnya untuk didiskusikan lebih mendalam. Negara memang punya kewajiban untuk membiayai pendidikan (atau, secara umum, menyediakan pendidikan bagi setiap warga negara). Akan tetapi, kewajiban dan wewenang negara ini haruslah diberi batasan dan kerangka yang jelas.
Secara umum, perlu ditegaskan bahwa fungsi negara pada dasarnya bersifat subsider. Negara bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri. Ia dibuat untuk mendukung upaya masyarakat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Negara harus memberi ruang kepada masyarakat (dan anggota-anggotanya) untuk mengurus dirinya sendiri, termasuk dalam hal menentukan apa yang mereka butuhkan. Jika wewenang negara tidak dibatasi dan meliputi semua segi kehidupan masyarakat, maka itu disebut negara totaliter. Negara totaliter menyangkal asumsi bahwa ia hanya pelengkap usaha masyarakat dan bahwa masyarakat memiliki hak moral untuk mengurus dirinya masing-masing (Magnis-Suseno, 1994: 178-179).
Negara memang harus memenuhi kewajibannya membiayai pendidikan. Tapi masyarakat harus diberi otonomi dalam mendefinisikan pendidikan macam apa yang mereka butuhkan. Jika negara membiayai pendidikan, dan pada saat yang sama menggerogoti partisipasi masyarakat, dan kemudian mengharuskan pengelolaan pendidikan sepenuhnya berada dalam kewenangannya, maka kepentingan publik bisa saja terancam.
Ancaman atas kepentingan publik ini menjadi semakin kuat jika kita menempatkan posisi negara yang dalam konteks globalisasi cenderung tunduk pada kepentingan lain, entah itu korporasi atau pemegang kapital, atau institusi lainnya yang pada tingkat tertentu mengisyaratkan lemahnya kedaulatan suatu negara. Dalam situasi seperti inilah, pendidikan bisa saja berbalik arah dan justru mendukung proses pemiskinan.
Pendidikan dan Pemiskinan
Bagaimana mungkin pendidikan dapat berkontribusi pada proses pemiskinan? Bukankah jika demikian yang terjadi berarti pendidikan telah jelas-jelas bertentangan dengan tujuan awalnya, yakni untuk meningkatkan martabat manusia?
Istilah pemiskinan merujuk pada adanya upaya aktif yang berakibat terjadinya keadaan atau status miskin pada individu atau kelompok masyarakat tertentu. Adapun kemiskinan itu sendiri pada dasarnya dapat dilihat sebagai pencederaan atas konsep keadilan sosial yang sejatinya juga menjadi bagian dari cita-cita atau tujuan berdirinya negara.
Namun demikian, dalam situasi tertentu, bisa saja negara mendukung bagi terlembaganya proses pemiskinan di masyarakat, termasuk melalui pendidikan.
Sejauh mengenai institusi pendidikan, kritik Ivan Illich (2000) dalam bukunya yang sudah menjadi klasik, Deschooling Society, amatlah relevan untuk dikemukakan di sini. Illich menegaskan adanya konspirasi antara kapitalisme dan sekolah yang didukung oleh kekuasaan hegemonik negara. Sekolah, seperti juga halnya negara, hanya menjadi pelayan para pemilik modal. Sekolah dalam lingkungan kapitalis sama sekali tidak mengembangkan kegiatan belajar atau mengajarkan keadilan, sebab sekolah lebih menekankan pengajaran menurut kurikulum yang telah dipaket demi memperoleh sertifikat. Sertifikat ini nantinya akan digunakan sebagai alat legitimasi bagi individu untuk memainkan perannya dalam pasar kerja yang tersedia.
Senada dengan Illich, Vandana Shiva juga menegaskan bagaimana institusi pendidikan mempromosikan pendekatan reduksionis yang menjadi paradigma sains modern. Reduksionisme, yang menjadi basis epistemologis paradigma pembangunan (developmentalisme), menampik berbagai pengetahuan lokal masyarakat sebagai suatu mode pengetahuan (Shiva, 1989: 14-26).
Paradigma semacam inilah yang kemudian menjadi landasan kebijakan dan cara kerja banyak lembaga pendidikan di negeri ini, yang pada tingkat tertentu, tanpa terasa, telah juga merasuk ke lembaga pendidikan yang sebelumnya secara mandiri dikelola oleh masyarakat. Dengan iming-iming bantuan dana (pembiayaan) oleh negara, perlahan paradigma semacam ini semakin menguat dan menyingkirkan nilai-nilai lokal yang dimiliki lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat.
Dari sinilah proses pemiskinan melalui pendidikan terjadi. Lebih parah lagi, pemiskinan melalui pendidikan bergerak mulai dari level kesadaran, yakni semenjak dalam pikiran, melalui bagaimana masyarakat memandang apa itu yang disebut miskin. Bersamaan dengan paradigma pembangunan yang dianut negara, kemiskinan kemudian didefinisikan terkait dengan kepentingan kapitalisme. Orang-orang yang telah mencukupi kebutuhan dasarnya secara mandiri dipandang miskin, karena mereka tidak turut serta dalam ekonomi pasar, yakni tidak mengkonsumsi komoditi yang diproduk dan didistribusikan oleh pasar (Shiva, 1989: 10-12).
Jadi, tanpa disadari, masyarakat digiring untuk berpikir dalam kerangka komodifikasi. Kita dapat mengamati bagaimana produk-produk kebudayaan modern perlahan menyingkirkan berbagai khazanah lokal, mulai dari sektor pangan, sandang, dan papan. Padahal, produk kapitalisme yang bersifat monokultur sangat besar berkontribusi bagi pengurasan sumber daya alam dan mengancam keanekaragaman hayati (Aditjondro, 2003: 330-346).
Nah, eksploitasi yang berlebihan yang sudah menubuh dengan semangat kapitalisme ini dan kemudian menimbulkan krisis ekologi saat ini tak mampu untuk dimunculkan dalam kesadaran masyarakat melalui pendidikan karena memang sekolah tidak didorong untuk kritis terhadap aktivitas ekonomi macam ini.
Lebih jauh, kita menyaksikan bagaimana berbagai disiplin ilmu yang diajarkan di sekolah banyak yang tidak lagi berupaya untuk merawat berbagai khazanah pengetahuan lokal yang ada di masyarakat. Ia justru membawa jenis pengetahuan “baru” (yang secara paradigmatik masuk dalam kategori sains reduksionis) yang senapas dengan kepentingan kapitalisme. Pada titik inilah kemandirian masyarakat terganggu, sehingga pada waktu yang sama proses pemiskinan pun berlangsung.
Ancaman pemiskinan ini menjadi cukup serius saat belakangan kita menyaksikan fenomena infiltrasi kekuasaan negara untuk masuk ke berbagai bentuk sistem pendidikan otonom yang dimiliki masyarakat. Misalnya, negara mulai masuk untuk ikut membiayai madrasah diniyah yang ada di pesantren. Yang patut dikhawatirkan, selain tergesernya salah satu nilai utama pesantren yakni nilai pengabdian, adalah tuntutan pengarahan dan penyeragaman dari negara sebagai kompensasi dari pembiayaan tersebut.
Kata Akhir
Idealnya, masyarakat mestinya memiliki daya tawar untuk mempertahankan model pendidikan yang selama ini dimilikinya. Mestinya model pendidikan yang ada harus dapat mendukung bagi pelestarian beragam pengetahuan lokal yang dimiliki setiap masyarakat (yang dalam konteks Indonesia sangatlah kaya dan plural). Tentu juga kita tak dapat melupakan kewajiban dasar negara untuk menyediakan pendidikan bagi setiap warga negara, termasuk memberi dukungan pembiayaan. Namun, sekali lagi, penting dicatat bahwa kewajiban negara ini bukan kemudian berarti bahwa negara dapat sewenang-wenang merampas hak otonomi masyarakat dalam mendefinisikan kebutuhan mereka akan pendidikan.
Di sini kita berhadapan dengan dua fakta yang cukup pahit. Pertama, negara seringkali tak punya kedaulatan yang cukup untuk menjaga kewajiban moralnya melindungi kepentingan masyarakat dan justru sering tunduk pada kepentingan eksternal (pemilik modal, aktor global). Kedua, masyarakat sendiri seperti tampak dapat ditundukkan oleh negara yang telah ditunggangi kepentingan eksternal tersebut dan gagal untuk mempertahankan suaranya sendiri.
Kurang lebih, situasi semacam inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama yang menunggu untuk diselesaikan.
Daftar Bacaan
Aditjondro, George Junus, 2003, Korban-Korban Pembangunan: Tilikan terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Baswedan, Anies, 2010, "Guru sebagai Garda Depan Indonesia", Jawa Pos, 26 Juli 2010.
Darmaningtyas, 2008, Utang dan Korupsi Racun Pendidikan, Pustaka Yashiba.
Darmaningtyas, 2010, "Kasta dan ISO di Sekolah", Kompas, 2 Juni 2010.
Illich, Ivan, 2000, Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah, terj. A. Sonny Keraf, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Magnis-Suseno, Franz, 1994, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Cetakan IV, Jakarta: Gramedia.
Shiva, Vandana, 1989, Staying Alive: Women, Ecology and Development, London: Zed Books.
Sugiharto, I. Bambang, dan Rachmat W., Agus, 2000, Wajah Baru Etika dan Agama, Yogyakarta: Kanisius.
Wahid, Abdurrahman, 2001, Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren, Yogyakarta: LKiS.
Kompas, 28 April 2009, "64 Persen Perempuan Buta Huruf".
Kompas, 11 Desember 2009, "2,2 Juta Anak Tak Sekolah".
Kompas, 15 Mei 2010, “92 Persen Madrasah Dibangun Swasta”.
Tulisan ini dibuat untuk bahan pengantar Seminar Pemiskinan dan Pendidikan, Dimensi Etis Pembiayaan Pendidikan: Antara Kewajiban Negara dan Partisipasi Publik, salah satu sesi dalam rangkaian kegiatan Sekolah Pengabdian Masyarakat (Angkatan Kelima) yang diselenggarakan oleh Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, 15-29 Agustus 2010. Seminar diadakan pada hari Ahad, 29 Agustus 2010.
Label: Education, Ethics, Social-Politics
Rabu, 21 Juli 2010
Dunia Tak Akan Lagi Sama
Sekarang kau sudah tahu semuanya. Tak ada lagi misteri. Tak ada lagi tirai yang menutupi jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu. Kebisuan, kabar angin yang bertebaran, sangkaan yang mengecewakan, kiriman buku kecil di hari ulang tahun, surat-surat yang hanya berbalas kata-kata singkat, kunjungan terakhir di awal tahun, semua telah dibicarakan.
Namun begitu, kupikir, mungkin saja kau masih menyimpan pertanyaan tentang momentum titik penyingkapan ini: mengapa harus sekarang kau mendapatkan penjelasannya, setelah sekian lama kau terperangkap dalam ketidakmengertian?
Kau sendiri tak terlalu banyak menjelaskan apa yang terjadi pada dirimu dalam rentang belasan tahun itu—setidaknya sejauh yang terkait dengan diriku. Aku sendiri tak mencoba mempertanyakannya. Aku tahu, jika memang ada hal penting, kau mungkin akan menyampaikannya padaku; kau akan mengurai satu persatu hal-hal yang mungkin saja masih kau simpan di situ, di bilik hatimu—entah kapan.
Sebagaimana sering terjadi, isi kepalaku kini memuat pertanyaan-pertanyaan umum yang cenderung agak abstrak. Dalam konteks dan momentum yang lain, pertanyaan serupa pernah singgah sejenak. Tapi tak pernah kurasakan pertanyaan itu datang berulang-ulang menuntut penjelasan—seperti sekarang. Mungkin penjelasannya tak harus spesifik, dan bisa lebih bersifat umum pula, sebagaimana karakter pertanyaannya.
Apakah (dan bagaimanakah) setiap informasi tertentu yang kuterima mengubah cara pandangku atas dunia? Lebih khusus lagi, apakah (dan bagaimanakah) informasi tertentu tentang seseorang akan menggeser atau memutar haluan pandanganku atau memberiku cara pandang yang baru tentang seseorang itu? Seberapa jauh informasi tertentu (tentang seseorang) dapat menebarkan kebencian, rasa permusuhan, toleransi, permakluman, atau mungkin cinta? Seberapa penting informasi tertentu dibutuhkan untuk membuat sebuah keputusan? Apa ini ada kaitannya dengan yang pernah Sokrates nyatakan bahwa wawasan dan pengetahuan yang benar dapat menuntun pada tindakan yang benar? Jenis “wawasan dan pengetahuan yang benar” macam apa yang kiranya “dapat menuntun pada tindakan yang benar”?
Faktanya, aku menemukan hal yang tak sederhana—setidaknya sependek pengalaman dan pengamatanku. Pengetahuan dan informasi tertentu dapat menyeret seseorang pada keputusasaan, kekecewaan, penyesalan, kebencian, dan semacamnya. “Matilah terhadap segala yang kau tahu,” tulis Putu Wijaya.
Saat pikiran-pikiran ini berdatangan, tebersit bayangan andai suatu saat, atau mungkin dalam waktu dekat, kita bisa membicarakannya berdua, mereka-reka berbagai kemungkinan jawabannya tanpa harus terbebani dengan fakta-fakta lalu atau yang mungkin saja datang kemudian. Membicarakannya, kita mungkin tak harus mencoba mengantisipasi situasi spesifik yang akan terjadi. Tak harus gentar dengan itu. Fakta-fakta kita masukkan dalam kurung terlebih dahulu. Karena kenyataan memang terkadang begitu rumit—bahkan mungkin pahit. Mungkin karena kenyataan adalah semacam pertautan persona tak terhingga bersama nilai-nilai dan latar unik yang mereka bawa.
Setelah kau dan aku pelan-pelan mulai bersama-sama mengetahui semuanya, mari kita nikmati pembicaraan yang indah ini, tentang pertanyaan-pertanyaan di atas ini, sambil sesekali merayakan kegilaan kita bersama-sama. Dan kemudian, dunia tak akan lagi sama.
Label: Diary
Kamis, 10 Juni 2010
Perjalanan-dalam-Kegelapan

Sudah beberapa hari berlalu, tapi syair itu kadang masih berkelebat di pikiran saya.
Gagasan tentang perjalanan, masa depan yang gelap, kesendirian, dan keberpasrahan pada Kuasa Tuhan, buat saya sungguh menggetarkan. Adakah yang lebih menakutkan daripada ketidakpastian-dalam-kesendirian? Adakah yang lebih menakutkan selain perjalanan-dalam-kegelapan?
Telah begitu lama saya terbiasa berpikir dengan kepastian sebagaimana ditanamkan dalam paradigma sains positivistik—clear and distinct, dalam istilah René Descartes—sehingga saya kadang terlupa dan seakan menampik fakta bahwa nyatanya pengetahuan saya memiliki batas yang tak pantas untuk terlalu dibanggakan. Apakah sebenarnya saya sedang berusaha mencari penghiburan dengan selalu berusaha percaya pada kepastian?
Kegelapan ini terasa mengurung saya dari ujung ke ujung. Sungguh saya merasa tak benar-benar tahu dengan pasti bagaimana semua ini bermula dan bagaimana akan berakhir—di mana, kapan, dan seterusnya.
Lalu mengapa puisi itu mempersandingkan kegelapan dan iman? Bukankah pada umumnya orang banyak menghubungkan iman dengan Pencerahan? “Go out into the darkness and put your hand into the Hand of God,” kata puisi itu.
Menurut saya, kegelapan adalah jalan yang senyatanya sedang saya tempuh. Dalam konteks ini, kegelapan mungkin adalah semacam simbol absurditas. Absurditas ini tampak dalam gagasan bahwa rasanya hidup terlalu pendek untuk saya untuk bisa merengkuh makna semua ini dengan purna—tujuan, keinginan, penyesalan, pemahaman, dan sebagainya. Di antara hasrat saya untuk mendapatkan kesempurnaan dan kepastian, saya berhadapan dengan fakta betapa rentang perjalanan-gelap saya hanyalah sepersekian sekon dari sejarah alam raya. Dengan kata lain, setetes air di antara samudera.
Dalam kependekan, kegelapan, dan kesendirian itu, rasanya iman memberi saya makna untuk sejengkal langkah yang mungkin sempat saya buat bersama semesta. Lebih dari itu, iman di perjalanan-dalam-kegelapan—bukan di jalan yang benderang—menantang saya untuk merespons makna dan implikasi kegelapan itu dengan baik. Justru karena saya bukanlah malaikat yang berjalan di atas rel dan rute yang pasti, saya tertantang untuk membuat rekam jejak yang indah—bukan hanya untuk saya, tapi jika mungkin bahkan untuk semesta.
Kini, saat saya berada di salah satu halte perjalanan ini, saya pun mereka-reka dan mencoba menyiapkan bekal untuk perjalanan berikutnya. Saya tidak tahu pasti apakah saat ini sedang pagi, siang, sore, atau sudah malam. Buat saya, perjalanan-dalam-kegelapan juga berarti bahwa saya bisa saja tertipu oleh petunjuk “waktu objektif”—ah, saya jadi teringat Henri Bergson. Seperti di kota tempat saya tinggal sekarang, Trondheim, Norwegia, tak mudah untuk membuat patokan waktu dari gelap dan terang, paling tidak untuk seorang yang berasal dari negeri tropis. Karena itu, perjalanan-dalam-kegelapan juga menuntut saya untuk memperlakukan setiap detik dengan harga yang pantas—pantas untuk sebuah absurditas.
Sambil menunggu waktu untuk meninggalkan halte ini, di antara berkemas, saya mencoba mengingat apakah saya masih punya lilin yang tersisa di ransel saya. Semoga lilin saya masih cukup untuk sisa perjalanan ini.
Terima kasih untuk Bang Mauritz Panggabean yang telah menginspirasi tulisan ini dan mempertemukan saya dengan syair Minnie Louise Haskins (1875-1957), “The Gate of the Year”, dan lukisan Theodor Severin Kittelsen (1857-1914), "Soria Moria". Gambar diambil dari Wikipedia.
Label: Diary, European Adventures
Minggu, 23 Mei 2010
Menikmati Tarian Aurora di Langit Trondheim
 Jika kau ditanya tentang kota di Eropa yang pada akhir April salju masih turun di sana, Trondheim adalah salah satunya. Ia terletak hampir 500 kilometer ke arah utara dari ibu kota Norwegia, Oslo. Kota yang didirikan oleh Raja Norwegia Olav Tryggvason pada 997 ini memang memiliki pesona alam yang khas.
Jika kau ditanya tentang kota di Eropa yang pada akhir April salju masih turun di sana, Trondheim adalah salah satunya. Ia terletak hampir 500 kilometer ke arah utara dari ibu kota Norwegia, Oslo. Kota yang didirikan oleh Raja Norwegia Olav Tryggvason pada 997 ini memang memiliki pesona alam yang khas.
Letaknya yang mendekati lingkar Kutub Utara membuat kota ini akan sangat unik di puncak musim dingin dan musim panas. Memasuki Mei, saya sempat terpaku mengamati jadwal salat bulanan yang saya dapatkan dari Masjid Komunitas Muslim Trondheim. Betapa tidak, di akhir Mei, matahari terbit pada pukul 03.26 dan baru akan tenggelam pada pukul 23.07.
Dari tetangga kamar yang asli orang Norwegia, saya menjadi tahu bahwa di sekitar pertengahan Juni-Juli, rentang waktu dari matahari terbenam hingga terbit tak sampai empat jam, sehingga bisa dibilang ketika itu Trondheim nyaris tak punya malam. Saya jadi teringat potongan syair lagu kelompok musik asal Swedia, Roxette, berjudul June Afternoon. "It's a bright June afternoon, it never gets dark. Wah-wah! Here comes the sun".
Saya sulit membayangkan bagaimana umat Islam berpuasa pada bulan Juni atau Juli di sini. Tak hanya soal ibadah, saya pun merasa agak kesulitan mengikuti irama perubahan waktu yang menjadikan siang merentang semakin panjang. Merasa lebih nyaman belajar (membaca dan menulis) di saat malam, kini saya agak kerepotan mengatur jadwal kerja ketika hari terasa tak kunjung petang. Padahal, di sepanjang Mei, saya mesti berkejaran dengan tenggat akhir penulisan tesis.
Di tengah suhu ekstrem dan guyuran salju, saya tetap memberanikan diri berjalan kaki dari asrama mahasiswa Moholt Studentby ke kampus Universitas Sains dan Teknologi Norwegia atau Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Dragvoll. Jarak 2,2 kilometer terasa lebih jauh. Di samping karena mendaki, guyuran dan tumpukan salju di jalan terasa cukup memperlambat dan membuat berat langkah-langkah kaki saya.
Namun saya tahu bahwa mungkin saya akan cukup kesulitan untuk punya pengalaman seperti ini lagi. Sebab, menurut kabar di koran lokal Trondheim, cuaca hari itu memang terbilang ekstrem, dan menurut catatan hanya terpecahkan oleh cuaca pada 52 tahun yang lalu.
Selain demi menghemat biaya hidup yang relatif lebih mahal dibanding negara Eropa lainnya, berjalan kaki ke kampus Dragvoll memang menyenangkan. Mendaki jalanan yang menanjak, saya mendapatkan pemandangan Kota Trondheim yang seolah menyerupai negeri dongeng.
Saat mulai mendekati Dragvoll, saya dapat menyaksikan lanskap Kota Trondheim dari ketinggian. Menara Tyholt di area kampus Departemen Teknologi Kelautan NTNU tampak menjulang. Di menara setinggi 124 meter itu, saya pernah menikmati pemandangan Kota Trondheim yang masih bertabur salju di sebuah restoran yang bergerak memutar di puncak menara.
Dari atas bukit menuju Dragvoll, di seberang kota yang penduduknya hanya sekitar 170 ribu jiwa ini, tampak teluk kecil dan perbukitan bertutup salju menjadi batas akhir pandangan mata saya. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah sisi yang berseberangan dengan hamparan Kota Trondheim itu, yakni bukit-bukit yang hampir sepanjang lerengnya dipenuhi dengan rumah kayu berwarna-warni. Ada yang merah, kuning, hijau, biru, putih, abu-abu, dan berbagai nuansa warna indah yang agak sulit saya gambarkan.
Balkon dan gazebo kecil di beberapa rumah tampak benar-benar memikat. Salah satu di antaranya tampak sebuah bangunan besar yang membentuk seperti tangga berundak mengikuti kontur bukit. Memang bukitnya tak setinggi dan securam Minas Tirith, tapi cukup untuk mengingatkan saya pada kota rekaan J.R.R. Tolkiens dalam trilogi terakhir The Lord of the Rings, yang tergambar begitu eksotik di versi filmnya, itu.
Saat menyusuri jalan ke Dragvoll, sering kali saya terpesona ketika mendapati langit benar-benar cerah dan biru serta sisa-sisa salju masih tampak di atap-atap rumah dan sisi bukit yang terjal itu. Lalu langkah-langkah sepatu saya di atas salju melahirkan bunyi yang khas. Mendekati kampus Dragvoll, lereng yang dipenuhi rumah kayu berganti dengan hutan kecil yang mengelilingi salah satu sisi kampus. Sungguh pemandangan yang benar-benar indah.
Moholt atau Dragvoll mungkin bisa dibilang sudah mendekati pinggiran Kota Trondheim. Sementara itu, pusat kota Trondheim sendiri yang tak begitu luas terbilang cukup unik. Ia berada di sebuah "pulau kecil" yang terbentuk oleh liukan mulut Sungai Nidelva yang berjumpa dengan Trondheimsfjorden—teluk kecil Trondheim yang berada di sisi utara.
Sebagaimana pusat kota pada umumnya, di sana ada beberapa pusat belanja, toko-toko, dan kantor pemerintah. Sebuah pusat belanja, Trondheim Torg, berada tepat di pusat kota. Trondheim Torg terasa tampak sangat sederhana untuk ukuran kota terbesar ketiga di Norwegia.
Hal paling menarik di pusat kota tentu saja adalah Katedral Nidaros. Ia merupakan landmark kota yang pernah menjadi ibu kota Norwegia hingga 1217 ini. Katedral yang mulai dibangun pada 1070 ini hingga sekarang menjadi monumen bangunan Gothic terpenting di Norwegia dan menjadi tujuan utama para peziarah sejak Abad Pertengahan untuk Eropa wilayah utara. Peran pentingnya terlihat dari fakta bahwa raja Norwegia dinobatkan di sini.
Pesona alam dan jejak sejarah menyatu dalam kota yang menjadi pusat pendidikan dan riset teknologi di Norwegia ini. Masih di kawasan pusat kota, setiap pulang Jumatan, saya sering sulit menahan godaan untuk menikmati pemandangan rumah-rumah kayu yang di antaranya berasal dari abad ke-18. Rumah kayu tipikal Skandinavia yang berwarna-warni itu berderet rapi di tepi Sungai Nidelva yang meliuk, tepatnya di dekat kawasan Kota Lama.
Di situ pula ada jembatan tua yang pertama dibangun menjelang akhir abad ke-17. Berdiri di tengah jembatan, saya menatap ke arah liukan sungai dengan airnya yang bersih dan tenang, sementara di kejauhan tampak gedung tua kampus NTNU Gløshaugen berdiri di atas ketinggian bukit. Sungguh akan sempurna jika mendung tak sedang menutupi angkasa.
Tak jauh dari jembatan itu, terdapat Sykkelheisen Trampe, lift untuk sepeda yang merupakan satu-satunya di dunia. Lift yang dibangun pada 1993 itu panjangnya 130 meter, tepat berada di perempatan kawasan Kota Lama. Sayang, saat terakhir saya ke sana, lift itu tampak belum dioperasikan—mungkin karena tumpukan salju belum benar-benar bersih.
Lebih dari itu semua, pengalaman paling menarik selama tinggal di Trondheim sejak awal Februari lalu adalah saat saya menyaksikan aurora. Sebelumnya, saya tak menyangka bahwa di Negeri Viking ini saya akan dapat menyaksikan salah satu fenomena alam yang hanya ada di beberapa tempat di belahan bumi itu.
Aurora Borealis, cahaya langit di dekat wilayah lingkar Kutub Utara yang terlihat di malam hari, saya saksikan di pekan kedua April lalu. Begitu mengetahui akan ada aurora dari laman ramalan cuaca yang biasa saya lihat, menjelang tengah malam saya bersiap di puncak salah satu bukit di kawasan kompleks asrama Moholt. Bersama puluhan mahasiswa lain yang ternyata sudah berada di sana lengkap dengan kamera mereka, saya begadang menikmati tarian aurora di langit utara.
Dari atas bukit itu, aurora kadang tampak melintang seumpama selendang yang dikibarkan di atas bangunan kompleks mahasiswa Moholt Studentby. Jauh di belakang, tampak bukit yang bercahaya oleh lampu-lampu kota. Warna kehijauan bertaburan di langit di balik pohon yang tampak masih meranggas. Titik-titik bintang kecil bersinar keputihan di kejauhan.
Cahaya kehijau-hijauan itu berpendar di langit. Kadang ia membentang panjang dari timur ke barat, berkelebat, lalu mengental, meremang, menebal, dan menipis. Di saat yang lain, ia tampak menumpuk di langit utara dalam area yang cukup melebar, lalu sesekali mementaskan tarian lembut sebelum akhirnya menghilang ditelan langit cerah bertabur bintang. Dari sudut yang berbeda, kadang cahaya kehijauan itu membentuk seperti tanduk Viking yang menggantung di langit.
Saya tahu, teman-teman saya, mahasiswa Indonesia, yang berada di negara Eropa lainnya mungkin akan merasa iri melihat foto dan catatan saya menyaksikan aurora, karena aurora hanya ada di langit utara. Tapi saya juga perlu memberi tahu bahwa tinggal di Trondheim menuntut ketahanan mental.
Bagaimanapun, kota yang topografinya berbukit dan beriklim maritim ini bisa dibilang cukup terpencil. Ya, Norwegia, seperti juga Swedia, adalah negeri yang sunyi. Di dua negara Skandinavia ini, wilayah yang dimanfaatkan tak lebih dari 4 persen. Selebihnya hanya lahan kosong, hutan, danau, dan semacamnya. Setelah Oslo, kota besar terdekat dari Trondheim adalah Bergen, yang berjarak sekitar 650 kilometer.
Kesunyian mungkin akan terasa semakin menjadi-jadi saat musim dingin begitu panjang, dan salju masih tetap saja turun bahkan hingga awal bulan Mei. Rumput tak kunjung menghijau, pepohonan masih kerontang, dan langit cukup sering berwajah muram. Saya kadang menjadi agak heran, mengapa St. Olav dahulu menamai kota ini Trondheim, yang berarti "rumah yang nyaman ditinggali"?
Saya bertanya-tanya, jika awal Mei salju masih turun, seperti saat saya menulis catatan ini, lalu kapan saya akan menikmati daun dan bunga-bunga yang bersemi? Semoga Juni. Ya, mungkin Juni, bersama Judas Priest yang akan mengentak dan meramaikan Kota Trondheim dalam ajang festival musik rock tahunan (Trondheim Rock) di sini.
Memandangi butiran salju yang turun pagi ini, saya pun berharap semoga salju yang saya saksikan di pekan pertama bulan Mei ini tak akan menjadi salju terakhir dalam pengalaman hidup saya.
Tulisan ini dimuat di Koran Tempo, 23 Mei 2010.
Kamis, 13 Mei 2010
Keajaiban Menulis
“Saat menuliskan sesuatu, kadang tak disangka kita kemudian dibawa pada suatu titik kesimpulan atau titik pemikiran yang tak diduga sebelumnya,” kata May Thorseth, dosen pembimbing saya Selasa kemarin, saat mendiskusikan sebagian naskah awal tesis saya di kampus Dragvoll NTNU Trondheim.
Pembicaraan ini muncul saat kami mendiskusikan tulisan awal saya yang memuat kerangka umum dan alur proyek tesis saya. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang memungkinkan saya untuk dapat melihat arah dan peta yang lebih jelas dari penelitian saya. Kemudian akhirnya ia menyarankan agar saya segera menuliskan dan masuk ke poin pembahasan utama. “Dalam proses menulis, kadang kita menemukan dan memahami satu poin gagasan yang terasa baru dan mencerahkan. That’s the magic of writing,” ujarnya.
Saya tersenyum mendengar kalimat itu. Saya cukup dapat merasakan apa yang ia sebut sebagai “keajaiban menulis” itu. Benar. Saya merasa bahwa proses menulis, perlahan, dapat membentuk cara berpikir seseorang. Tidak saja dalam pengertian cara seseorang bernalar atau menyusun alur dan logika, tetapi mungkin juga memengaruhi cara seseorang memandang suatu hal atau persoalan.
Dalam rentang proses yang lebih panjang, menulis sangat mungkin membentuk identitas dan karakter seseorang. Menulis membantu memperkaya dan mengolah berbagai nuansa pengalaman dalam sudut pandang subjektif tertentu, sehingga dengan begitu ia bisa juga dilihat sebagai sebuah proses interaksi-reflektif antara pengalaman dan penafsiran. Hal atau pengalaman yang sederhana mungkin bisa terlewatkan begitu saja. Akan tetapi, dengan tingkat kepekaan tertentu yang sudah cukup terasah, hal sederhana itu bisa saja melahirkan refleksi dan poin gagasan yang mungkin cukup menarik.
Saat pengalaman yang ditafsirkan itu semakin kompleks dan beragam, matriks kemungkinan gagasan yang akan dihasilkan bisa menjadi semakin luas. Pada titik itulah proses menulis kemudian seperti menjadi proses memilah lorong-lorong menuju alur kesimpulan (sementara) yang terasa lebih dapat diterima secara subjektif sesuai dengan stok pengetahuan dan sudut pandang si penulis. Kompleksitas matriks kemungkinan itu dipilah, dicoba untuk ditata, disederhanakan, dan akhirnya disimpulkan.
Dalam proses lanjutan, saat sebuah tulisan telah rampung dan diakhiri oleh si penulis dan dilepas ke publik, ia akan terus berkembang biak sendiri lepas dari otoritas (authority, “kepengarangan”) si penulis. Kematian pengarang, sebagaimana dikabarkan oleh Roland Barthes, tentu saja bukanlah kabar buruk yang harus disesali, karena bagaimanapun teks pada akhirnya adalah juga tindakan yang memiliki hak otonominya sendiri. Sekecil apa pun, apa yang telah kita tulis pada akhirnya akan menjadi bagian dari Buku Semesta—dan ada kehadiran kita di sana, meski tak bisa purna.
Namun begitu, meski sudah lepas dari kuasa pengarang, kehadiran teks otonom tersebut ke wilayah publik telah membuka peluang pintu dialog bagi gagasan yang sebelumnya hanya sunyi sendiri dalam benak si penulis. Kesunyian sebuah gagasan yang hanya semarak dalam benak seseorang akhirnya dirayakan secara publik melalui tulisan.
Saat ide tentang tulisan ini menyergap saya semalam sebelum tidur, saya pun sempat bertanya-tanya: akan seperti apakah jadinya ide tersebut saat dituliskan dan bagaimana ia akan berakhir—dalam prosesnya maupun ketika sudah menjadi teks otonom.
Sekarang saya tahu bahwa tulisan ini sendiri (bersama ide yang muncul tadi malam itu) mungkin adalah bagian dari pencarian saya tentang makna aktivitas kepenulisan saya selama ini. Ini mungkin bagian dari cara saya merayakan jalan sunyi seorang penulis, dengan berusaha mengusir kabar kesunyian itu dengan sebuah pesta bertajuk “keajaiban menulis”.
Adakah yang mau bergabung bersama saya dalam pesta ini?
Label: Diary, European Adventures, Literacy
Minggu, 09 Mei 2010
Plagiarisme dan Komunitas Akademik yang Sekarat
Saat berdiskusi tentang penulisan tesis di program saya dengan pembimbing dan teman sekelas, ada satu gagasan yang menarik buat saya dan mengingatkan saya pada kasus plagiarisme di Indonesia. Dijelaskan bahwa salah satu tujuan penting menulis tesis atau karya akademik lain adalah mematangkan diri dan berproses menyatu dalam komunitas akademik.
Saya berpikir bahwa bisa jadi fenomena plagiarisme dan hal serupa (ijazah atau sertifikat palsu dan semacamnya) terjadi karena sebenarnya komunitas akademik di negeri kita sedang sekarat.
Komunitas akademik pada dasarnya merupakan tempat untuk berbagi pengetahuan ilmiah. Perkembangan ilmu itu sendiri terjadi dalam serangkaian proses dialogis dari berbagai ruang dan waktu yang berbeda dan terutama berlangsung melalui media tulisan. Tulisan yang bisa disebut karya ilmiah itu muncul beriringan, saling dukung, saling kritik, menggali, menguatkan, mempertanyakan, menyempurnakan, menindaklanjuti, dan seterusnya sehingga membentuk suatu akumulasi capaian pengetahuan dan ilmu tertentu.
Seseorang yang sedang menulis karya ilmiah sebenarnya sedang berusaha berkomunikasi dengan komunitas ilmiah lebih luas. Dengan media tulisan dan dukungan teknologi yang semakin canggih, proses diskursif itu berlangsung secara cukup kaya dan intens, melintasi berbagai tempat dan disiplin ilmu.
Akan tetapi, jika yang terjadi adalah plagiarisme, tentu saja proses komunikasi itu menjadi bermasalah. Salah satu masalah mendasar yang selama ini sudah cukup banyak disorot adalah problem etis. Kejujuran, tanggung jawab, penghormatan kepada orang lain jelas-jelas ternoda dalam kasus plagiarisme.
Lebih dari sekadar problem etis, plagiarisme di negeri kita, bagi saya, terutama juga merupakan pertanda bahwa komunitas akademik kita sebenarnya tengah sekarat. Sebagian komunikasi ilmiah yang terjadi di antara orang-orang yang berada di titik-titik komunitas ilmiah itu mungkin bersifat semu. Disebut semu karena aktivitas utama komunitas akademik, yakni pemelajaran, sulit ditemukan di situ. Yang ada mungkin hanyalah semacam formalitas yang kering, dangkal, dan bersifat instrumental.
Dalam komunitas akademik yang sekarat, sebagian orang berkarya cenderung tidak didorong semangat belajar, hasrat untuk menggali, dan maksud untuk berbagi. Mereka relatif hanya digerakkan dorongan periferal, seperti untuk kenaikan pangkat dan jabatan, prestise, materi, dan semacamnya.
Beberapa karya (kebanyakan?) dalam jurnal-jurnal ilmiah di tanah air mungkin tak jauh dari motif semacam itu. Mereka tak mencerminkan dialog dan interaksi akademik yang hidup, tapi berada dalam konteks ''dalam rangka'' yang tak substantif.
Sekaratnya semangat komunitas akademik tersebut bisa dikembalikan pada problem moral sebagaimana orang membaca kasus plagiarisme. Meski demikian, problem moral itu mungkin juga berakar pada kondisi objektif yang terbentuk sedemikian rupa dalam sebuah proses historis yang bisa jadi relatif panjang.
Jika kita berasumsi bahwa komunitas akademik ini mulai tumbuh, terutama melalui institusi perguruan tinggi (kampus) dan atau lembaga serupa, dapat dikatakan bahwa Orde Baru menjadi titik awal yang cukup penting dicermati. Penelitian Daniel Dhakidae (2003) menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru sulit sekali ditemukan kelompok ''cendekiawan bebas'' karena mereka berhadapan dengan aparat ideologis dan represif negara yang kuat dan totaliter. Organisasi profesional kaum cendekiawan kehilangan otonominya dan hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan negara.
Situasi semacam itulah yang terjadi dalam kurun waktu cukup panjang dan melalui proses rekayasa sosial-politik-kebudayaan canggih, yang pada gilirannya menyuburkan mental instrumental pada insan-insan komunitas ilmiah atau cendekiawan itu.
Saat ini Orde Reformasi relatif menyediakan ruang yang lebih bebas bagi kaum cendekiawan untuk menghidupkan kembali kredo akademiknya, termasuk dukungan objektif berupa kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan dan penelitian. Meski demikian, godaan kekuasaan dan pragmatisme (mentalitas menerabas, dalam istilah Koentjaraningrat) masih terus membayang dan hadir dalam beragam rupa.
Demikianlah, plagiarisme sebenarnya tak hanya memberi kita pekerjaan rumah yang sederhana. Tidak sekadar menghentikan praktik yang tak menghormati karya dan kreativitas orang lain. Lebih dari itu, plagiarisme mendorong kita untuk segera membenahi komunitas akademik kita yang sekarat.
Dalam dinamika komunitas akademik, kredo dalam berkreasi harus terus diteguhkan. Saat ini, sepertinya tak mudah menjadi sosok ilmuwan atau akademisi ideal di tengah iklim yang tak sehat, kecuali mereka tergerak oleh panggilan visi pribadi yang kuat dan bermental tangguh.
Di titik itulah tugas kita bersama untuk menyediakan ruang yang lebih baik bagi perbaikan lingkungan ilmiah (akademik) menjadi semakin mengemuka. Tujuan akhirnya, kaum cendekiawan dan para ilmuwan itu bisa terpanggil untuk konsisten melakukan berbagai hal demi perbaikan peradaban dan masyarakat.
Tulisan ini dimuat di Harian Jawa Pos, 9 Mei 2010. Bisa juga dibaca di Blog Kompasiana.
Selasa, 04 Mei 2010
Kegiatan Peduli Lingkungan di Sekolah dan Pendidikan yang Lebih Membumi
Semangat dan inspirasi kadang menunggu momen tertentu untuk muncul. Seringkali ia datang secara kebetulan. Kita tak pernah menyangka sebelumnya, bahwa hal yang tak kita rencanakan akan cukup berpengaruh mengarahkan jalur hidup kita berikutnya.
Demikianlah. Sepulang mengikuti acara Environmental Teachers’ International Convention (ETIC) akhir Maret 2008 di Kaliandra, Pasuruan, tiba di rumah saya mencoba mencari salah satu arsip artikel saya yang ditulis sekitar 13 tahun sebelumnya saat saya duduk di bangku sekolah menengah atas. Tulisan yang akhirnya saya temukan baik dalam bentuk tulisan tangan maupun versi yang sudah dicetak dengan ketikan komputer itu berjudul “Manusia dan Krisis Lingkungan: Perspektif Ekologi Islami”.
Saya mencari tulisan itu karena saya ingin mencoba merekonstruksi pikiran macam apa yang ada di kepala saya waktu itu. Pulang dari ETIC 2008 yang digelar sekitar sepekan di pedalaman Pasuruan, kepala saya dipenuhi dengan pertanyaan dan pikiran tentang nasib dan masa depan bumi. Jika saya dulu memang pernah menulis sebuah esai sepanjang 10 ribu karakter (1.600 kata) tentang isu lingkungan, mengapa tulisan itu sepertinya hanya berhenti di sana, sebagai tulisan (atau gagasan) saja, dan seperti tak memiliki cerita lanjutan?
Meramu Tiga Matra
Sampai di situ, saya berkesimpulan bahwa wawasan normatif saja sangat tidak cukup (pikiran tentang hal ini kemudian terus berkembang hingga saya masuk ke diskusi yang lebih mendalam soal berbagai pemikiran di bidang etika lingkungan). Kita butuh fakta-fakta inspiratif yang sederhana dan dekat dengan keseharian kita untuk bisa mematri, membumikan, dan menjangkarkan sebuah dimensi normatif tertentu.
Selanjutnya, dua matra itu, aspek normatif dan fakta inspiratif, tak bisa berdiri sendiri. Keduanya butuh wadah yang menggerakkan dialektika matra normatif dan faktual ke dalam wujud gerakan atau aksi nyata di lapangan.
Pulang kembali ke sekolah dari ETIC 2008, saya pun mencoba meramu ketiga matra tersebut dalam aktivitas pendidikan lingkungan di sekolah tempat saya mengajar, SMA 3 Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep. Isu lingkungan bagi komunitas tempat saya mengajar sebenarnya tidaklah terlalu asing. Sekitar dua tahun sebelumnya di situ sudah terbentuk komunitas pecinta lingkungan di sekolah dengan nama Duta Lingkungan yang dirintis oleh salah seorang guru SMA 3 Annuqayah, Muhammad-Affan. Lebih jauh, sebenarnya komunitas Pondok Pesantren Annuqayah, yang merupakan komunitas besar kami, sudah lama sekali bersentuhan dan bergiat di isu lingkungan. Pada tahun 1981 Annuqayah mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah untuk kategori penyelamat lingkungan.
Keterlibatan Annuqayah di isu lingkungan dipelopori oleh Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren Annuqayah (BPM-PPA) yang wilayah garapannya lebih banyak ke masyarakat di sekitar pesantren. Sebagai guru, saya pun mencoba fokus menekuni isu lingkungan di komunitas sekolah tempat saya mengajar.
Ramuan ketiga matra yang saya simpulkan itu kemudian pertama kali mewujud dalam bentuk aksi memulung sampah plastik pada peringatan Hari Bumi 2008. Aksi ini sebenarnya dilakukan tanpa persiapan yang matang tapi ternyata melahirkan tindak lanjut yang begitu panjang. Aksi ini disepakati setelah ada salah seorang murid di sekolah saya yang mencoba membuat tas pensil dari sampah plastik. Katanya, ia tergerak oleh salah satu kisah saya sepulang dari ETIC 2008. Memang, di kelas saya sempat bercerita tentang seorang ibu dari Jakarta yang sempat hadir dan berbagi di ETIC 2008. Ibu itu membuat tas dan kerajinan dari sampah plastik. Nah, si murid saya itu, dengan tanpa mesin jahit, ternyata berhasil membuat tas pensil sederhana dari sampah plastik.
Pemulung Sampah Gaul
Tindak lanjut aksi ini kemudian mewujud lebih solid dalam bentuk komunitas yang oleh murid-murid dinamakan Pemulung Sampah Gaul (PSG). Setelah aksi memulung itu, komunitas ini tidak hanya sekadar mengolah sampah-sampah plastik yang didapat dari beberapa tempat pembuangan akhir (TPA) di lingkungan Annuqayah yang menampung sekitar enam ribu santri dan siswa. Mereka juga berupaya mendorong tersebarnya pengetahuan, informasi, dan sikap peduli terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, terutama menyangkut sampah plastik.
Meski hanya baru bergerak di tingkat lokal, yakni di lingkungan sekolah kami sendiri, kreativitas anak-anak PSG ini mendapat perhatian dan apresiasi dari berbagai pihak, sehingga beritanya sempat dimuat di Radar Madura (13-14 Juni 2008) dan disiarkan di stasiun televisi Madura Channel (10 Juni 2008).
Untuk lebih memperluas wilayah sosialisasi, PSG hadir di salah satu stand dalam ajang Haflatul Imtihan Madrasah Annuqayah 2008, yakni kegiatan perayaan akhir tahun pelajaran yang diisi dengan berbagai kegiatan lomba dan semacamnya. Pada kegiatan ini, PSG hadir memamerkan hasil kerajinan dari sampah, melakukan sosialisasi bahaya sampah plastik, memunguti sampah plastik di lokasi pameran, dan presentasi proses kretif mengolah sampah menjadi karya kerajinan. Pada acara yang digelar mulai 3-6 Juli 2008 tersebut, dari buku tamu tercatat ada lebih dari 800 pengunjung yang ikut meramaikan stand PSG.
Sementara stand-stand yang lain berusaha memanjakan hasrat konsumtif santri dan siswa, stand PSG justru memasarkan kesadaran untuk lebih peduli dengan alam.
Semenjak itu, aktivitas PSG semakin populer sehingga sempat diundang ke sekolah dan komunitas lain di lingkungan Sumenep. Pada tanggal 30 Juli 2008 PSG melakukan presentasi di MTs Ainul Falah Bakeyong, Guluk-Guluk, Sumenep, yang mendapatkan respons sangat meriah. Tanggal 21 November 2008 utusan PSG presentasi di forum Fatayat NU Pragaan Sumenep yang kemudian menarik perhatian dan tindak lanjut cukup serius. 13 Februari 2009, anak PSG juga presentasi di komunitas ibu-ibu di Guluk-Guluk.
Sehari-hari, komunitas PSG di lingkungan sekolah berupaya menyebarkan informasi dan sikap peduli terhadap bahaya sampah plastik. Memang, idealnya langkah yang paling diutamakan adalah mengurangi (reduce) sampah. Namun disadari bahwa itu mungkin masih terlalu berat untuk masyarakat yang masih relatif buta informasi dan kurang peka atas persoalan sampah dan hal yang terkait dengannya.
Karena itulah, target utama aktivitas PSG adalah penyebaran informasi. Dengan kata lain, aspek faktual yang sederhana dan inspiratif yang diharapkan dapat menggerakkan perubahan—sekecil apa pun. Produk PSG berupa tas dan kerajinan yang lain hanyalah media. Selain untuk menarik perhatian, juga untuk mengingatkan dan menguatkan aspek informatif dan inspiratif terkait sampah plastik. Memang, beberapa orang kadang tampak salah paham memandang aktivitas PSG—melihatnya sebagai aktivitas keterampilan, padahal inti utamanya adalah mengajak orang untuk lebih peka dan peduli lingkungan.
Tersebarnya informasi tentang bahaya sampah plastik diharapkan dapat mengubah perilaku seseorang. Misalnya, belajar untuk memilah sampah plastik, kertas, dan organik. Karena di sekolah kami sebelumnya tak ada upaya pemilahan sampah, maka PSG kemudian membagikan kardus bekas khusus untuk tempat sampah plastik di kelas-kelas.
Kami juga cukup senang saat kemudian ada dua toko di dekat sekolah kami yang mulai memisah sampah-sampah plastik mereka dan kemudian diserahkan kepada PSG untuk dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan dari sampah plastik.
Semua kegiatan PSG ketika itu terutama hanya bermodalkan semangat. Sekolah kami terbilang miskin dan tak punya banyak anggaran untuk mendukung semua kegiatan murid. Tapi murid-murid kami tradisikan untuk berbuat maksimal dengan apa yang kami miliki. Untuk kegiatan PSG, misalnya, ketika itu kami hanya bisa memanfaatkan mesin jahit pinjaman. Alat-alat pendukung untuk mengolah sampah plastik itu pun kami dapat secara swadaya. PSG juga mendapatkan dana dari penjualan hasil kerajinan, baik tas dan semacamnya, yang dibuat oleh murid-murid.
Namun akhirnya ada pihak yang membantu kami menghadapi keterbatasan ini. Di bulan Januari 2009, Said Abdullah Institute di Sumenep memberikan bantuan dana untuk komunitas PSG. Sebagian dana itu kemudian digunakan untuk membeli dua mesin jahit serta peralatan lainnya dan merehab sebuah bangunan gudang di pojok sekolah untuk menjadi bengkel dan markas PSG. Selebihnya, dana kami simpan.
SCC dan Dua Adik PSG
Di akhir tahun 2008, saya mendapat informasi tentang sebuah ajang lomba yang digelar oleh British Council Indonesia bernama School Climate Challenge (SCC) Competition. Lomba ini bertujuan untuk mendorong murid dan guru sekolah menengah terlibat dalam proyek peduli lingkungan. Setelah berembuk dengan beberapa guru dan elemen penggiat lingkungan lainnya di sekolah, di akhir Februari 2009 kami mendaftarkan tiga tim untuk ajang lomba tingkat nasional ini.
Ketiga tim itu masing-masing adalah Tim Pupuk Organik, Tim Gula Merah, dan Tim Sampah Plastik. Dua tim yang pertama masing-masing terdiri dari dua guru pendamping dan 3 siswa, sedang Tim Sampah Plastik, karena relatif sudah eksis dan berkegiatan, hanya menempatkan saya sendiri sebagai guru pendamping ditambah dengan empat orang murid. Saya sendiri juga didaulat sebagai koordinator guru pendamping untuk ketiga proyek tersebut. Sebagai bentuk langkah kaderisasi, masing-masing tim juga didukung oleh sejumlah murid yang juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kerja proyek yang dilaksanakan sepanjang Maret hingga Mei 2009. Ketiga proyek ini menggunakan kas dana PSG dan sama sekali tak mengambil dana sekolah.
Saya sangat senang karena setidaknya ada empat guru lainnya yang mulai intens masuk bergiat ke isu pendidikan lingkungan dalam dua proyek SCC yang lain tersebut. Lebih dari itu, isu yang ditekuni mulai meluas, tak hanya sampah plastik, tapi juga pupuk organik dan gula merah atau pangan lokal.
Lebih tiga bulan intens mengerjakan dan mendampingi proyek SCC ini, saya berusaha mensinergikan tiga matra yang ada dalam benak saya itu: aspek normatif, sisi faktual, dan gerakan yang terorganisasi.
Pada aspek normatif, saya mencoba memberi sentuhan pendekatan filsafat moral dalam semua proyek dan kegiatan tersebut. Latar belakang pendidikan sarjana saya sebagai lulusan dari jurusan filsafat menjadi modal tersendiri. Apalagi saya memang meminati bidang etika (filsafat moral) dan mencoba merintis pengenalan wacana filsafat moral di lingkungan Pesantren Annuqayah pada umumnya. Pada sesi penguatan kapasitas, saya mencoba mengajak murid-murid untuk berpikir sedikit radikal menghadapi persoalan lingkungan. Memang, bidang etika lingkungan buat saya terbilang baru, karena di Indonesia sendiri bidang ini terbilang belum cukup populer.
Pada sisi faktual, saya mengajak murid-murid untuk menghimpun data dan fakta terkait dengan masing-masing proyeknya, terutama dari internet, untuk dibuat semacam kliping digital. Kliping ini saya harapkan akan menjadi bahan penguatan kapasitas para anggota komunitas penggiat lingkungan lainnya di sekolah. Sekali lagi, sisi faktual ini dicari yang sederhana dan inspiratif.
Tak hanya diajak menekuri buku atau laman-laman di internet, murid-murid juga diajak untuk belajar peka membaca fakta di sekitar mereka. Beberapa kali murid diajak untuk riset lapangan, misalnya ke komunitas petani gula merah, dan sebagainya.
Melalui proyek SCC, pada level gerakan murid-murid mulai diajak untuk berjejaring dengan komunitas dan sekolah yang lain di wilayah Sumenep, seperti Madrasah Aliyah Nasy’atul Muta’allimin Gapura, Madrasah Aliyah Sumber Payung Ganding, dan sebagainya. Beberapa sekolah tampak antusias dengan kegiatan kami dan ada pula yang kemudian ikut membentuk komunitas peduli lingkungan di sekolahnya.
Gerakan penyebaran informasi dan kesadaran yang dilakukan oleh ketiga proyek SCC ini juga sempat mendapat dukungan dari sebuah radio lokal, Ganding FM, saat kami diberi kesempatan gratis untuk on-air dan berbagi pengalaman terkait proyek kami. Selain itu, stasiun televisi Madura Channel juga mengundang saya untuk tampil secara langsung dalam dialog memperingati Hari Bumi 2009.
Saat menutup rangkaian ketiga proyek SCC tepat di penghujung Mei 2009 dan ketiga tim proyek SCC mempresentasikan kegiatan mereka selama tiga bulan di hadapan para undangan yang terdiri dari siswa, masyarakat, dan instansi terkait, pelan-pelan saya dapat menangkap betapa murid-murid—juga guru—yang bergiat di proyek ini tidak saja dilatih untuk mengembangkan potensi kreativitas, kepemimpinan, jiwa wirausaha sosial, dialektika aksi-refleksi, dan menyebar kepedulian terhadap lingkungan.
Pendidikan yang Membumi
Dalam konteks pendidikan lingkungan, proyek SCC yang kemudian berkembang sebagai tiga bidang garapan komunitas lingkungan di SMA 3 Annuqayah juga adalah ikhtiar untuk membumikan proses pendidikan dalam kehidupan aktual sehari-hari di sekitar kita. Ada satu kutipan sangat menarik yang saya dapatkan dari Dewi Lestari, atau yang populer disebut Dee, penulis dan penyanyi yang juga memiliki minat yang besar terhadap isu lingkungan.
Di blog yang menjadi salah satu favorit saya itu, Dee mengutarakan bahwa kita tidak dididik untuk tahu—atau mau tahu—tentang dari mana benda-benda yang kita konsumsi berasal, berapa banyak sumber daya alam yang digunakan untuk memproduksi itu semua, dan ke mana semua itu akan berakhir riwayatnya—kertas, tisu, bungkus permen, puntung rokok, komputer, pakaian, dan sebagainya. Pelajaran Biologi, misalnya, mungkin sebagian relatif gagal karena tidak membuat murid bertanya mengapa petani cukup sering mengalami kekurangan pupuk, atau mengapa sumber air bersih di sekitar mereka sudah tak lagi jernih.
Menguatkan pendidikan lingkungan di sekolah dari sudut pandang ini sebenarnya juga berarti membawa kurikulum sekolah ke arah yang lebih kontekstual , membumi, dan mengakar dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat tempat murid itu berasal. Di tengah iklim pendidikan formal yang terkesan textbook dan kaku, sungguh kegiatan peduli lingkungan dengan impian akan jaringannya yang kuat akan tampak sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk terus ditekuni.
Intinya, bergiat di aktivitas pendidikan lingkungan akan memiliki banyak nilai lebih yang juga akan sangat relevan dengan peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan generasi muda yang lebih berkarakter.
Hal yang paling memuaskan buat saya setelah mengerjakan dan mendampingi 3 proyek SCC itu adalah lahirnya kader-kader baru serta bidang baru di komunitas peduli lingkungan di sekolah kami. Saya senang bahwa paling tidak ada guru yang juga tertarik untuk mendampingi murid di kegiatan lingkungan di sekolah. Salah satu di antaranya adalah guru Biologi, Pak Mahmudi, yang sebenarnya tak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang itu, tapi karena cukup bersemangat dan belajar secara otodidak ia dipercaya memegang materi itu di sekolah. Yang lebih menggembirakan, proyek yang didampinginya, yakni proyek pupuk organik berbahan dasar limbah pertanian, berhasil masuk sebagai peringkat kelima dalam ajang lomba SCC yang diikuti oleh hampir 200 proyek dari berbagai sekolah di Indonesia.
Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri tidak hanya untuk dia, tapi juga buat saya dan seluruh civitas kependidikan di sekolah kami.
Karena kebetulan di lingkungan Pondok Pesantren Annuqayah saya juga mendampingi beberapa komunitas kepenulisan dan aktif mendorong terciptanya iklim jurnalisme warga, saya juga mendorong anak-anak yang terlibat di kegiatan proyek SCC dan PSG untuk mendokumentasikan kegiatan mereka dalam bentuk tulisan.
Di samping untuk melatih menuturkan pengalaman dan gagasan melalui media tulisan, menuliskan catatan pengalaman dalam kegiatan lingkungan ini bagi saya tidak saja berarti mereka membagikan pengalaman mereka yang cukup kaya itu. Saya harap dengan hal ini mereka juga bisa berbagi kepedulian dengan orang dan komunitas lain yang lebih luas.
Hasilnya, puluhan tulisan sudah dihasilkan oleh murid-murid yang tergabung di komunitas peduli lingkungan ini. Semuanya dipublikasikan di blog sekolah. Kebetulan saya sendiri yang menggawangi blog tersebut—kebetulan juga saya di sekolah mengajar pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.
Mengembangkan Kerangka Etis
Setelah SCC rampung di bulan Juni 2009, saya sebenarnya ingin sekali mengusahakan agar tulisan-tulisan para murid itu dapat tersaji lebih utuh dan lebih baik dalam bentuk semacam buku berisi kisah sukses bergiat di aktivitas peduli lingkungan di sekolah.
Sayangnya saya belum bisa merealisasikan gagasan ini. Untuk sementara waktu, saya tak bisa secara langsung bersama murid-murid dan rekan-rekan guru SMA 3 Annuqayah, karena di awal September 2009 saya melanjutkan studi saya ke Eropa. Alhamdulillah, di awal Mei 2009 saya mendapat kabar gembira bahwa aplikasi saya untuk program Erasmus Mundus Masters Course in Applied Ethics diterima. Saya mendapat kesempatan untuk mendalami bidang etika terapan di dua kampus di Eropa, yakni Utrecht University, Belanda, dan NTNU Trondheim, Norwegia, selama dua semester.
Pilihan saya untuk melanjutkan studi sebenarnya didorong oleh minat dan keterlibatan saya pada isu lingkungan, sehingga kemudian tertarik untuk secara khusus mendalaminya. Karena saya lihat di Indonesia masih belum ada kampus yang secara khusus mengarah ke sana, saya mencoba mengajukan aplikasi ke program yang disponsori oleh Uni Eropa tersebut, dan alhamdulillah diterima.
Sebelum berangkat ke Eropa, pertengahan Juni 2009 saya sempat diundang British Council Indonesia yang bekerja sama dengan PMPTK Depdiknas untuk mengikuti lokakarya penyusunan modul pembelajaran yang berusaha mengintegrasikan berbagai disiplin pelajaran di sekolah dengan perspektif pendidikan lingkungan. Acara yang diadakan di Malang pada 15-19 Juni ini bagi saya memberi banyak inspirasi untuk pengembangan isu pendidikan lingkungan di sekolah tempat saya mengajar, khususnya mengenai langkah teknis untuk memasukkan isu pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum secara lebih tertata. Namun saya tidak bisa menindaklanjuti agenda spesifik ini karena saya harus menyiapkan banyak hal sebelum keberangkatan saya ke Eropa.
Selama studi di Eropa, saya tetap menyempatkan diri berkomunikasi dengan murid-murid yang bergiat di komunitas peduli lingkungan di sekolah. Kaderisasi dan konsolidasi menjadi salah satu target penting, karena dalam banyak kasus suatu komunitas kemudian macet karena masalah kader—poin ini sebenarnya juga menjadi salah satu bagian yang sedang saya pikirkan secara lebih mendalam. Dalam beberapa kesempatan, saya bahkan sempat ikut rapat online dengan mereka menggunakan video conference Skype.
Saya senang sekali mendapat kabar bahwa mereka masih terus bergiat, termasuk memenuhi undangan sekolah atau komunitas lain di Sumenep untuk berbagi pengalaman dan presentasi. Di bulan Oktober 2009, misalnya, mereka sempat hadir mewakili Kecamatan Guluk-Guluk dalam Pameran Pembangunan di Kabupaten Sumenep, dan tampil dengan memamerkan aktivitas dan visi hijau mereka.
Kabar terakhir, mereka tengah menyiapkan diri untuk presentasi di forum "24th Conference of the Caretakers of the Environment International" yang akan diselenggarakan di Malang awal Juli nanti.
Saat ini saya tengah menyusun tugas akhir (tesis) untuk program saya. Saya menulis tentang kerangka etis pendidikan lingkungan untuk konteks Indonesia. Penelusuran sementara saya menyimpulkan bahwa persoalan pendidikan lingkungan di Indonesia memiliki nuansa yang begitu luas. Konteks Indonesia sebagai negara berkembang membuat pendidikan lingkungan memiliki kaitan yang sangat erat dengan isu pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Pada titik ini, pendidikan lingkungan menurut saya kemudian juga mesti menyentuh isu kemiskinan, keadilan, dan semacamnya, yang dalam konteks Indonesia memiliki kaitan erat dengan isu lingkungan.
Saya senang karena selama menempuh studi di Eropa saya bisa melakukan semacam refleksi baik atas kegiatan peduli lingkungan di sekolah tempat saya mengajar pada khususnya dan Indonesia pada umumnya serta refleksi untuk lebih membumikan dan menyediakan kerangka normatif— dalam hal ini berbagai pemikiran dalam bidang etika lingkungan atau etika pada umumnya—yang kokoh untuk gerakan dan proyek pendidikan lingkungan. Kerangka etis yang bersifat aksiologis maupun strategis ini menurut saya akan bermakna penting jika kita melihat bahwa pendidikan lingkungan pada dasarnya adalah bagian dari pendidikan moral—pendidikan moral untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk merawat kehidupan, alam semesta, dan generasi masa depan.
Tentu saja saya sepenuhnya sadar bahwa kerangka etis ini terutama terkait dengan salah satu matra, yakni aspek normatif. Tantangannya, saya tetap harus bisa meramu dan mengintegrasikannya dengan kedua aspek lainnya, yakni sisi faktual dan aspek gerakan, dan juga menerjemahkannya dalam bentuk yang lebih konkret dan aplikatif.
Untuk tantangan ini, sungguh saya sudah merasa tak sabar menunggu saat pulang pertengahan Juni nanti. Ide-ide di kepala rasanya sudah berletupan dan menunggu untuk diwujudkan. Semoga saya, murid-murid dan rekan guru di sekolah saya, serta kita semua, diberi kekuatan untuk dapat mewariskan bumi dan peradaban yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Tulisan ini terpilih sebagai Juara Pertama Nokia Green Ambassador Tahap Ketiga 2010.













.jpg)