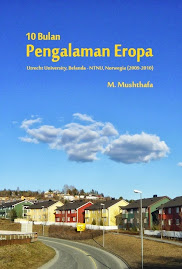Judul buku: Area X: Hymne Angkasa Raya
Judul buku: Area X: Hymne Angkasa Raya
Penulis: Eliza V. Handayani
Pengantar: Taufiq Ismail
Penerbit: DAR! Mizan, Bandung
Cetakan: Pertama, 2003
Tebal: xxiv + 368 halaman
Semarak kepenulisan dunia sastra tanah air yang belakangan semakin meriah kali ini semakin bertambah dengan hadirnya novel karya Eliza V. Handayani yang berjudul Area X: Hymne Angkasa Raya ini. Meski terhitung sebagai pendatang baru di lingkungan kepenulisan sastra Indonesia, nama Eliza patut diperhitungkan karena di samping usianya yang masih cukup belia (21 tahun), tema dan kisah yang diangkat dalam novel ini relatif jarang dirambah para penulis novel di Indonesia, yaitu fiksi sains.
Kita mungkin bisa mengajukan novel Supernova: Episode Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh sebagai novel dengan tema fiksi sains, karena di situ Dewi Lestari, penulisnya, menyajikan begitu banyak teori-teori fisika mutakhir. Bila Supernova mengandalkan kecanggihan teknik dengan cara menyaling-nyilangkan perjalanan kisah Dhimas dan Ruben secara berdampingan dengan kehidupan Diva, Ferre, dan Supernova, serta bumbu romantisme yang cukup kental, maka karya Eliza ini sarat dengan obsesi dan idealisme sosial berkait dengan Indonesia masa depan dalam konteks penguasaan teknologi dan masa depan peradaban dunia pada umumnya.
Obsesi dan idealisme itu terbungkus dalam model futuristik yang dipilih Eliza dalam menjalin kisah yang dirajutnya. Novel yang berasal dari naskah yang memenangkan Lomba Penulisan Nasional Film/Video 1999 ini (ketika itu Eliza masih duduk di kelas dua SMU Taruna Nusantara Magelang) mengambil setting Indonesia tahun 2015, ketika Indonesia (diimajinasikan) sudah cukup maju dalam bidang pencapaian teknologi. Saat itu seluruh dunia dilanda krisis energi minyak bumi yang menjadi ancaman cukup serius, termasuk Indonesia. Pencarian sumber energi alternatif oleh masing-masing negara digambarkan sebagai detik-detik yang begitu mencemaskan, karena di satu sisi dapat memicu meletusnya konflik global, bahkan kemungkinan penjajahan negara-negara lemah oleh negara-negara kuat.
Di tengah suasana itulah, kisah novel ini diolah dan disajikan dengan berporos pada satu pusat penelitian teknologi yang didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2005, bernama Area X (Area Kesepuluh), yang bergerak di bidang penelitian teknologi militer dengan status Ultra Top Secret. Status inilah yang menjadi magnet pemicu rasa penasaran bagi tokoh-tokoh novel ini. Kisah novel ini dibuka dengan penyusupan menegangkan yang dilakukan oleh Yudho dan Rocki ke Area X, hanya dengan maksud mempelajari sistem pengamanan di sana. Tapi tragis, Rocki tertangkap dan tahu-tahu meninggal tak lama setelah ia dibebaskan dari Area X.
Kemudian, Yudho, yang putus asa akibat kematian sahabat terkaribnya itu, ditemui Elly, seorang gadis muda yang menaruh minat terhadap fenomena UFO dan sangat curiga dengan aktivitas penelitian di Area X. Elly yang mengalami konflik dengan orang tuanya lantaran menaruh minat pada fenomena yang oleh masyarakat umum dinilai tidak ilmiah itu akhirnya bertualang bersama Yudho dan sejumlah kawan mudanya, Arfan, Tammi, Marina, dan Rendy, untuk menyibak misteri Area X.
Di banyak bagian novel ini, kerap ditemukan dialog, perbincangan, atau perdebatan tentang aspek-aspek teknologi dan masa depan peradaban dunia. Semuanya bertolak dari keprihatinan Elly atas krisis energi dunia dan kecurigaannya bahwa Area X berusaha menemukan teknologi Zero-Point dan Anti-Gravitasi guna mengatasi krisis tersebut dan menemukan media transportasi antar-galaksi yang memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam di planet lain. Pengembangan teknologi ini diduga dipelajari dengan media bangkai pesawat UFO yang terjatuh di kawasan Hadeslan, sebuah kota satelit di pinggiran Jakarta.
Akhirnya, ketika Elly dan Yudho berhasil menyusup ke Area X, terkuaklah misteri pusat penelitian itu. Ternyata Area X memang diabdikan sebagai pusat pengembangan teknologi persenjataan yang dimaksudkan untuk menangkal ancaman serangan invasi para alien. Tapi bagi Yudho dan Elly, bila memang itu tujuannya, tidak semestinya umat manusia hanya mengandalkan pada teknologi dan keunggulan yang dipelajari dari para alien itu. Manusia menyimpan energi berharga berupa keberanian untuk mencipta dan mencinta. Tidakkah lebih baik bila umat manusia mengajarkan faedah hidup berdampingan yang penuh kedamaian, sebuah koeksistensi untuk bersama-sama merawat kehidupan.
Di tengah nyaris tidak adanya karya fiksi sains di negeri ini, novel ini menyimpan banyak sisi menarik. Tidak cuma dari sisi kebaruan tema yang diangkat dan kedalaman bacaan yang menjadi bahan rujukannya, tapi juga obsesi dan pesan tersirat yang digumamkannya ke hadapan pembaca menjadi kekuatan tersendiri. Obsesi Eliza terlihat dalam tema besar yang menggambarkan tantangan konkret masa depan teknologi di negeri ini serta dalam penokohan yang banyak diperankan oleh sosok-sosok muda berbakat dengan kuriositas dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa.
Secara lebih luas, dalam novel ini juga banyak ditemukan renungan-renungan, eksplisit maupun implisit, tentang makna keberadaan manusia yang dibenturkan dengan pencapaiannya di bidang teknologi. Yang menarik, Eliza banyak mengembalikan semua arus perenungan itu ke nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat mendasar dengan memberi penghargaan yang tinggi kepada nilai cinta, semangat hidup, kemanusiaan, dan kebersamaan. Di situlah terlihat keyakinan Eliza bahwa di antara selaksa krisis yang saat ini merintangi perjalanan bangsa ini untuk berbenah diri, termasuk juga tantangan di masa depan berupa krisis energi dan eksploitasi kekayaan alam yang dapat lebih bermanfaat, nilai-nilai mendasar itu dapat menjadi kekuatan luar biasa sehingga patut dikembangkan dan ditanamkan dalam-dalam.
Alur dan cara bertutur novel ini yang mirip dengan cerita detektif membuatnya asyik dibuntuti. Selain itu, deskripsi suasana di novel ini banyak yang tetap konsisten dan tema sains yang diangkat. Misalnya, ketika menggambarkan bagaimana Yudho dan Elly yang mulai jatuh cinta, Eliza menulis: “Mereka bagai dua planet kecil yang terlepas dari orbitnya, berkelana mengarungi angkasa kelam, tersesat dalam galaksi pencarian—kini mereka telah saling menemukan matahari mereka, tata surya mereka.”
Lebih dari itu semua, kehadiran novel karya Eliza, yang kini menempuh studi di Wesleyen University, Amerika, seperti membisikkan harap dan doa, bahwa semoga Indonesia di tahun 2015 masih tetap utuh, dan meraih sejumlah hal yang patut dibanggakan di kancah dunia.
Selasa, 30 September 2003
Idealisme Kaum Muda yang Dinantikan
Label: Book Review: Novel
Minggu, 14 September 2003
Determinasi Ekologi dalam Sejarah Madura
 Judul Buku : Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940
Judul Buku : Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940
Penulis : Prof. Dr. Kuntowijoyo
Penerbit : Mata Bangsa, Yogyakarta, bekerja sama dengan Yayasan Adikarya
IKAPI dan The Ford Foundation
Cetakan : Pertama, November 2002
Tebal : xxiv + 679 halaman
Pluralitas etnis dan budaya di Indonesia selama ini menjadi semacam khazanah kekayaan bangsa yang terpendam. Kajian-kajian serius terhadap beragam kultur lokal belum pernah diangkat secara luas menjadi wacana publik. Sementara itu, arus kebebasan yang dipicu oleh Orde Reformasi di satu sisi telah menyuburkan penerbitan karya-karya penelitian etnografis yang telah dihasilkan oleh berbagai kalangan intelektual. Salah satunya adalah buku karya sejarawan terkemuka, Prof. Dr. Kuntowijoyo ini.
Buku yang mulanya adalah disertasi doktoral di Columbia University ini menyajikan gambaran yang cukup mendalam tentang proses perubahan sosial di Madura dalam periode satu abad menjelang kemerdekaan Indonesia. Sudut pandang sejarah yang digunakan Kunto lebih bersifat sosiologis, dengan menekankan pada formasi-formasi sosial dan cara-cara masyarakat melakukan aktivitas produksi.
Tesis utama buku ini adalah bahwa sejarah masyarakat Madura dibentuk sedemikian rupa oleh berbagai kekuatan alam, baik itu ekologi fisik maupun ekologi sosial. Dari proses historis yang diamati Kunto dapat disimpulkan bahwa Madura adalah suatu unit lingkungan sejarah yang cukup unik dan berbeda dengan wilayah geografis yang lain di Indonesia. Di Madura, sisi pengaruh berbagai kebijakan kolonial Belanda kurang menampakkan pengaruhnya: struktur desa dan kelompok strata sosial yang hidup di dalamnya, struktur birokrasi kolonial, dan juga penetrasi dagang kaum kapitalis Eropa.
Di bagian awal Kunto berusaha memberikan gambaran ekologi fisik Madura yang dikenal gersang, bercurah hujan rendah, dan memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Pengaruhnya terlihat pada tatanan kepemukiman masyarakatnya. Berbeda dengan masyarakat luar Madura yang memiliki pusat-pusat pemukiman di tiap desa, pemukiman penduduk di Madura lebih bersifat tersebar dalam kelompok-kelompok perdusunan kecil dengan hubungan keluarga sebagai faktor pengikatnya. Desa bukannya dibentuk oleh suatu kompleks pemukiman penduduk dan dikitari oleh persawahan. Hal ini membuat kontak sosial antar-warga menjadi cukup sulit, sehingga tidak aneh bila orang-orang di Madura relatif sulit membentuk solidaritas desa dan lebih didorong untuk memiliki rasa percaya diri yang bersifat individual. Ini berarti bahwa hubungan sosial lebih berpusat pada individu-individu, dengan keluarga inti (yang mendiami dusun-dusun kecil itu) sebagai unit dasarnya.
Pada titik inilah peranan pemuka agama (kiai) menjadi penting, yakni sebagai perantara budaya masyarakat dengan dunia luar, termasuk juga dengan penguasa.
Naga-naga perubahan sosial di Madura bermula dari berakhirnya kejayaan kerajaan-kerajaan tradisional Madura (Sumenep, Pamekasan, dan Bangkalan), ketika mereka menyerah pada penguasa kolonial Belanda pada paruh kedua abad ke-19. Sistem upeti misalnya yang sebelumnya memang sudah hampir tak berdaya melawan arus kekuatan pedagang Cina menjadi semakin sulit mendapat tempat, seperti juga akhirnya para bangsawan tidak lagi mendapat kursi kekuasaan tradisional, dan akhirnya masuk ke dalam sistem birokrasi kolonial Belanda dan mewujud dalam bentuk kelas sosial priyayi.
Sejalan dengan itu, proses dan pengaruh struktur ekologis mengantarkan Madura dalam suatu situasi kelangkaan ekonomi yang cukup signifikan, ditambah lagi dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Menghadapi hal ini, terjadi migrasi yang cukup besar sebagian masyarakat Madura ke wilayah timur Pulau Jawa. Apalagi saat itu di situ sedang semarak dibangun proyek-proyek perkebunan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Solidaritas sosial di Madura sempat berkembang pada awal abad ke-20, mengiringi gerakan nasional dan didukung oleh hasil pengaruh politik etis (pendidikan) kolonial. Organisasi Sarekat Islam misalnya sempat aktif di Madura, bahkan sempat memberikan sedikit aksi massa seperti perlawanan sosial-ekonomi, baik terhadap penguasa kolonial maupun kapitalis Cina. Tapi itu tidak bertahan terlalu lama.
Dari keseluruhan uraian dalam buku ini, pertanyaan kontekstual yang muncul adalah apakah saat ini ekologi fisik dan sosial di Madura sudah mengalami perubahan, sehingga dapat mendorong terjadi perubahan sosial ke arah yang berbeda? Di bagian epilog yang ditulis khusus untuk buku ini Kunto memberikan jawaban bahwa belum ada perubahan signifikan, sehingga “ke-Madura-an” orang Madura tetap begitu lekat.
Buku ini begitu berharga bagi perkembangan perjalanan bangsa ini, dan terutama bagi masyarakat Madura. Ada kecenderungan bahwa bangsa ini mulai kehilangan dasar-dasar pijakan historisnya sehingga seringkali arah perjalanan bangsa, atau kelompok masyarakat tertentu, tercerabut dari akar sejarahnya sendiri. Sudah waktunya bangsa yang besar ini memungut dan menata kembali warisan sejarahnya yang panjang, untuk dimaknakan sebagai etos yang bersifat orientatif dan sebagai pendorong kemajuan bangsa.
Buku ini menyajikan data-data dan analisis sejarah yang cukup kaya, yang ternyata banyak ditemukan di pusat-pusat kajian di Belanda. Sejarawan kita benar-benar ditantang untuk mengumpulkan dan menganalisis arsip-arsip perjalanan bangsa yang berserakan di mana-mana, termasuk juga dalam sejarah lisan yang hidup di tengah masyarakat.
Tulisan ini dimuat di Harian Sinar Harapan, 13 September 2003.
Minggu, 07 September 2003
Familiisme Politik Orde Baru
Judul Buku: Pahlawan-Pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik
Penulis : Saya Sasaki Shiraishi
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation
Cetakan: Pertama, April 2001
Tebal: x + 290 halaman
Harga: Rp 30.000,-
Di antara sekian banyak kosakata yang kerap kali digunakan dalam bidang politik terselip ungkapan-ungkapan yang memiliki hubungan erat dengan dunia keluarga. Dalam otobiografi mantan Presiden Soeharto misalnya terdapat ungkapan yang menyebutkan bahwa menteri-menteri di pemerintahannya disebutnya sebagai anak-anaknya. Dalam sebuah konflik atau pertentangan yang bersifat sosial atau politik dikenal ungkapan ‘penyelesaian dengan cara kekeluargaan’.
Gejala seperti ini bagi orang kebanyakan mungkin dianggap sesuatu yang wajar dan biasa—mungkin disebut-sebut sebagai kekhasan ‘budaya timur’. Akan tetapi, bagi Saya Sasaki Shiraishi, penulis buku ini, hal itu bukan suatu kebetulan yang tak ada artinya. Dalam buku ini Shiraishi menunjukkan secara jernih dan argumentatif bahwa ada suatu hubungan yang erat antara politik dan keluarga di Indonesia, dan itu berpengaruh bagi keberlangsungan pengelolaan dan proses hidup bernegara di negeri ini.
* * *
Buku ini sendiri, yang semula adalah disertasi di Departemen Antropologi Cornell University pada tahun 1997, ditulis dengan tujuan meneliti dan mencari kemungkinan untuk menerobos, dan akhirnya menyingkap, susunan antropologis dan kultural masyarakat Orde Baru Indonesia yang amat tertekan dan tertindas. Mengapa dalam bayang-bayang ketertindasan itu masyarakat tetap bisa dikendalikan untuk tidak melawan secara frontal.
Kesimpulan penting yang diajukan buku ini adalah bahwa ada sebuah ideologi samar yang nyaris tak disadari yang menuntun dan membimbing jalannya sejarah politik di Indonesia—tidak hanya pada masa Orde Baru. Itulah ideologi keluarga atau familiisme. Gambaran sederhana yang dapat diberikan tentang ideologi ini adalah fakta bahwa dalam proses interaksi kehidupan berbangsa di Indonesia ada semacam isomorfisme antara hubungan guru dan murid, presiden dan rakyat atau pembantu pemerintahannya, pimpinan militer dan pasukannya, ketua organisasi dan anggotanya, dengan pola hubungan yang diatur oleh prinsip-prinsip yang sama dan dinyatakan dalam bahasa kekeluargaan yang menunjuk kepada bapak/ibu dan anak. Bahasa kekeluargaan ini ditopang oleh gagasan tentang keluarga, yang menyamakan sekolah sebagai keluarga, ABRI sebagai keluarga, perusahaan sebagai keluarga, dan bangsa sebagai keluarga (hal. 5).
Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah konsep keluarga yang mana yang dominan dalam ideologi familiisme ini, sementara di Indonesia ada keragaman khazanah budaya yang juga meliputi sistem keluarga yang tiada terkira.
Jawaban atas pertanyaan ini dapat ditemukan ketika secara cukup tajam dan argumentatif, penulis buku ini secara historis melacak ideologi familiisme di Indonesia yang ternyata berasal-usul dari masa sebelum kemerdekaan. Familiisme dalam politik ini sudah menjadi suatu perdebatan antara tokoh nasionalis Jawa yang juga pendiri Taman Siswa, Soetatmo Soerjokoesoemo, yang didukung kuat oleh Ki Hajar Dewantara, dengan seorang tokoh nasionalis Hindia, Tjipto Mangoenkoesoemo. Model familiisme Soetatmo adalah model Soeharto, Bapak-tahu-segala (Fathers-knows-best) yang reaksioner dan model Tjipto adalah model hubungan bapak-anak yang revolusioner (hal. 131).
Peristiwa Rengasdengklok yang melibatkan Soekarno dan merupakan detik-detik revolusioner menuju momen proklamasi oleh penulis buku ini digambarkan secara jernih sehingga menunjukkan gaya hubungan bapak-anak yang revolusioner. Saat itu Soekarno (sebagai bapak) ditangkap, diculik, dan dibawa oleh anak buahnya sendiri dipaksa untuk mengikuti kemauan mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Akan tetapi, model revolusioner hubungan bapak-anak ini tidak bertahan lama karena begitu kuatnya pengaruh kuat familiisme ala Ki Hajar Dewantara yang diinvestasikan melalui media Taman Siswa selama masa pra-kemerdekaan. Model familiisme Ki Hajar inilah yang dominan, hingga secara pasti diperankan oleh Soeharto dalam peristiwa G-30-S tahun 1965. Dalam peristiwa ini, menurut analisis dan penafsiran penulis buku ini, Soeharto bertindak mengamankan kehangatan hidup keluarga (bangsa) yang terenggut oleh semangat revolusioner yang berlebihan ini dan menempatkan hubungan bapak-anak dalam pola yang harmonis: ayah yang bijak, ibu yang penuh perhatian, anak yang tahu-diri, tugas dan tanggung jawab. Inilah gerakan dan pola pikir yang bersifat kontra-revolusioner dalam pola hubungan bapak-anak.
* * *
Memulai rezim Orde Baru yang dibangunnya, Soeharto kemudian menempatkan dirinya sebagai Bapak Tertinggi (Supreme Father) bagi bawahannya dan rakyat Indonesia. Prinsip harmoni dalam keluarga merupakan kunci pengaturan negara yang memungkinkan rakyat (anak) tak berani menentang pemerintah (bapak)—anak yang tahu diri.
Pengaruh pemikiran-pemikiran Ki Hajar yang dalam buku ini disebut sebagai gabungan dari kreasi pemikiran Jawa-Belanda seringkali terlihat dari pernyataan Soeharto, seperti seringnya penggunaan semboyan tut wuri handayani. Arti petikan tersebut yang tidak lain adalah “membimbing dari belakang” pada dasarnya bermakna pemberian kesempatan bagi seorang anak untuk membina diri sendiri secara wajar dengan bimbingan orang tua (bapak) di belakang yang siap memberi petunjuk bila ada kesalahan. semboyan yang seringkali dikutip dalam panggung politik di Indonesia.
Akan tetapi, sayangnya, ketika dialihkan ke dalam khazanah politik nasional, semboyan itu ternyata tidak lagi dipahami sebagai upaya bimbingan dari belakang, malah mengisyaratkan adanya mata yang siap menghukum dan mengawasi dari belakang, yang siap menerkam kebebasan si anak itu sendiri.
Sementara itu, bapak-bapak Orde Baru yang merupakan bapak dari generasi kontra-revolusioner mewarisi corak dualisme bahasa kolonial antara komitmen terhadap hukum peraturan organisasi di satu pihak dan toleransi dan kesewenang-wenangan atas nama ikatan keluarga di pihak lain. Aturan dan peraturan hukum disiasati, sehingga lahirlah ungkapan terkenal: semua bisa diatur.
Ideologi familiisme ini selama Orde Baru dibangun melalui sarana sekolah, birokrasi, perusahaan, kantor, dan semacamnya. Pelajaran Bahasa Indonesia yang menurut penulis buku ini sama sekali belum memiliki acuan sosiologis yang jelas juga disusupi familiisme dalam proses pengajarannya terhadap anak-anak sekolah.
* * *
Dengan meminjam terminologi dan pola kerangka pikir yang digunakan penulis buku ini, saat ini kita semua sedang menyaksikan pola hubungan bapak-anak yang cukup rumit dan membingungkan. Para bapak sedang ribut berebut kursi kekuasaan dan membiarkan anak-anaknya terlantar. Sementara itu, beberapa anak malah mengancam memisahkan diri, dan yang lain sibuk bertengkar memperebutkan sepiring nasi.
Haruskah keluarga bangsa ini hancur lebur atas nama reformasi dan demokratisasi? Buku ini memang telah cukup bagus dan dengan cerdas memaparkan kekurangan-kekurangan pola hubungan bernegara yang telah menerpurukkan bangsa ini dalam krisis berkepanjangan. Karena itulah, dari buku ini, kita bersama hendaknya dituntut mendefinisikan ulang pola hubungan hidup bernegara ini dalam kerangka sistem negara yang lebih ajek. Kritik yang diajukan buku ini sehubungan dengan menguatnya pola ideologi familiisme adalah ketika kekeliruan dalam dunia politik dilihat semata sebagai soal individu—seperti dalam keluarga. Bertolak dari ini, saat ini kita semua mesti berpikir tentang landasan sistemik yang bersifat struktural untuk menghadang segala kemungkinan buruk dari sistem kultur yang sedemikian ini.
Dari paparan di atas, buku ini menampakkan nilai signifikansinya dalam kehidupan bangsa ini. Dengan menggunakan data-data lapangan berupa peristiwa-peristiwa keseharian di tingkat keluarga yang sederhana (menjemput di terminal, arisan, pernikahan, kelahiran, dan sebagainya) hingga buku-buku dan majalah, buku ini berhasil mengungkap satu sisi budaya politik yang tanpa sadar menyeret bangsa Indonesia ke titik krisis yang belum juga teratasi. Buku ini memberikan peringatan dan pelajaran sejarah bangsa demi membangun masa depan bangsa dan kebudayaannya yang lebih baik.
Tulisan ini dimuat di Harian Sinar Harapan, 6 September 2003.


.jpg)