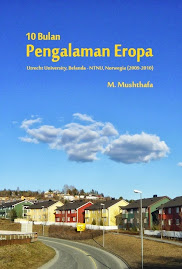Judul Buku : Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah
Judul Buku : Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah
Penulis : Ivan Illich
Penerjemah : A. Sonny Keraf
Penerbit : Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Cetakan : Pertama, Agustus 2000
Tebal : xii + 166 halaman
Benarkah sekolah adalah satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang pendidikan bagi masyarakat? Benarkah orang yang tidak bersekolah identik dengan predikat tak berpendidikan?
Ivan Illich melalui buku yang semula berjudul Deschooling Society ini jelas-jelas mengatakan bahwa anggapan mengenai sekolah sebagai satu-satunya lembaga pendidikan adalah bias dari kehidupan kapitalis yang telah merasuk dalam kesadaran masyarakat. Menurut Illich, sekolah adalah fenomena modern yang lahir seiring dengan perkembangan masyarakat industri kapitalistik. Konspirasi terselubung antara pendidikan dan kapitalisme ini juga tak lepas dari dukungan pemerintah (kekuasaan) sehingga daya hegemonik yang diciptakannya menjadi cukup massif.
Struktur masyarakat industri menurut Illich telah menyeret kesadaran masyarakat kepada dependensi institusional dalam banyak hal. Masyarakat selalu dan hanya mengaitkan pendidikan dengan sekolah, pelayanan kesehatan dengan rumah sakit, mobilitas pribadi dengan frekuensi aktivitas yang banyak, dan seterusnya. Inilah fenomena ketika kebutuhan-kebutuhan non-material dalam spektrum masyarakat kapitalis telah diubah menjadi permintaan terhadap barang, yang tentu saja berada dalam jaringan sistem kapitalisme.
Ketergantungan masyarakat terhadap institusi sekolah untuk memperoleh pendidikan ini menurut Illich merupakan suatu bentuk pelembagaan nilai yang mau tidak mau pada akhirnya menimbulkan polusi fisik, polarisasi sosial, dan ketidakberdayaan psikologis. Definisi dan label-label sosial diciptakan dalam kerangka hubungannya dengan lembaga sekolah.
Di Meksiko misalnya kaum miskin dirumuskan sebagai orang yang tidak menempuh pendidikan sekolah tiga tahun, dan di New York orang miskin adalah orang yang berpendidikan di bawah dua belas tahun. Patokan-patokan kemiskinan dibuat oleh teknokrat dengan sesuka hatinya, dengan melulu menggunakan perspektif mereka—suatu perspektif yang bias kaum borjuis.
Pada level internasional, kewajiban bersekolah di suatu negara dan pencapaian pelaksanaannya dalam masyarakat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan peringkat kemajuan negara. Jadilah masyarakat dibagi ke dalam kutub-kutub berseberangan yang dalam konteks global menciptakan sistem kasta internasional.
Padahal, menurut Illich, sekolah dalam lingkungan kapitalis sama sekali tidak mengembangkan kegiatan belajar atau mengajarkan keadilan, sebab sekolah lebih menekankan pengajaran menurut kurikulum yang telah dipaket untuk memperoleh sertifikat. Sertifikat ini nantinya akan digunakan sebagai alat legitimasi bagi individu untuk memainkan perannya dalam pasar kerja yang tersedia.
Hal ini terjadi karena sekolah adalah lembaga yang dibangun atas dasar anggapan bahwa kegiatan belajar adalah hasil dari kegiatan mengajar. Guru dianggap sebagai pengawas, pengkhotbah, sekaligus ahli terapi untuk memberi petuah-petuah moral. Jadilah guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga berfungsi sebagai ideolog, hakim, dan dokter, yang memerkosa masa depan peserta didik.
Kehadiran sekolah juga telah membatasi usia seseorang dengan tingkat pendidikan yang dapat diikutinya. Masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan orang tua dibagi dan dipaket untuk tingkat pendidikan tertentu. Seorang anak-anak menurut Illich melewati suatu proses konflik yang tidak manusiawi ketika oleh sistem masyarakat diharuskan masuk dalam lembaga sekolah. Anak-anak terpaksa melewati masa kecilnya dengan kurang bahagia.
Kondisi pendidikan yang sedemikian itu bagi Illich telah mengabaikan motivasi tiap individu bagi aktivitas pendidikan yang diikutinya, dan memasukkan individu ke dalam struktur mekanis kebutuhan industri terhadap posisi-posisi tertentu masyarakat kapitalis. Pendidikan hanya menjadi pelayan kapitalisme.
Untuk itu, Illich mengusulkan bahwa lembaga pendidikan (formal) baru yang ideal adalah lembaga yang bertolak dari asumsi motivasi pribadi untuk belajar, serta adanya ketersediaan dan akses terhadap sarana bagi semua orang yang ingin belajar dan mengajar.
Usul Illich tersebut berpusat pada upaya pemanfaatan jaringan-jaringan sumber daya pendidikan untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal. Berbagai fasilitas umum yang dapat digunakan sebagai perangkat pendidikan harus dibuka aksesnya bagi semua orang yang ingin belajar: perpustakaan, laboratorium, museum, teater, pabrik, dan sebagainya. Birokrasi ketat harus dienyahkan sehingga jasa referensial yang dimiliki sarana-sarana itu dilepas untuk kepentingan pendidikan seluas-luasnya.
Orang-orang yang memiliki keterampilan khusus dimanfaatkan secara baik dengan menghapuskan persyarakatan kelembagaan serta membiarkan mereka mengolah dan mempertukarkan keterampilannya dalam suatu komunitas yang lebih terbuka. Seorang pemilik keterampilan tertentu tak boleh diasingkan sehingga menjadikan suatu keterampilan tertentu menjadi langka.
Peserta didik juga diberi kesempatan untuk memperluas hubungan-hubungan sosial dengan sesamanya (teman sebaya). Mereka tidak hanya dikumpulkan dan dipertemukan di sekolah, tetapi diberi kesempatan pula untuk menjalin kontak dengan individu lain yang memiliki minat dan kecenderungan yang serupa. Di sinilah makna penting dari komunitas atau organisasi di luar sekolah yang menampung minat dan hobi yang bersifat khusus.
Lebih jauh lagi, peserta didik dibebaskan dari harapan-harapan yang terlalu berlebihan dengan menggantungkan masa depannya kepada jasa-jasa profesi manapun (sekolah). Peserta didik sebaiknya lebih dibebaskan menurut motivasi dan keinginannya untuk membentuk lingkungan belajar dan arah belajar yang diinginkan sehingga otonomi individu benar-benar terjaga.
Kritik dan pemikiran Ivan Illich ini menarik terutama dalam konteks pembangunan suatu bangsa. Sudah saatnya untuk disadari bahwa otoritas pendidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga sekolah, tetapi juga berada dalam setiap sisi kehidupan masyarakat. Karena itulah, pemberdayaan pendidikan sebenarnya dapat dilakukan di mana saja, asal semua sumber daya tersebut dibebaskan seluruhnya demi dikelola bagi kepentingan pendidikan.
Revolusi Budaya yang diinginkan Illich adalah dengan melepas mitor sekolah dan lembaga sosial lainnya yang berperan terlalu dominan dalam kehidupan masyarakat saat ini, sehingga akhirnya mendikte laju kehidupan individu dan membelenggu aktivitas dan otonomi masyarakat.




.jpg)