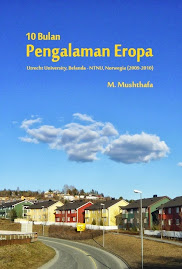Kehidupan sastra di pondok pesantren (Madura), khususnya di Pondok Pesantren Annuqayah, memang merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diamati. Sastra pesantren (Madura) oleh beberapa kalangan dinilai memiliki prospek yang cerah pada dekade mendatang.1
Komunitas sastra yang terbentuk di dalamnya bergerak terus mengikuti arus perkembangan sastra dengan langkah pasti. Kelompok-kelompok pecinta dan pekerja seni bermunculan dan aktif melakukan kegiatan-kegiatan kesenian. Mempertimbangkan potensi dasar yang dimiliki pondok pesantren dalam hal pengembangan sebuah komunitas sastra yang lebih baik, dirasa perlu untuk terus meningkatkan kualitas sastra pondok pesantren secara lebih terarah, tanpa meninggalkan kode-kode etik kepesantrenan yang merupakan ciri khas kehidupan santri.
Namun, juga harus diakui bahwa hingga saat ini mayoritas dari komunitas sastra yang ada di pesantren (Madura), Annuqayah khususnya, masih berada dalam tahap awal. Minat untuk melahirkan karya-karya semisal puisi memang begitu besar dirasakan. Hanya sayangnya, mereka terlalu mengkonsentrasikan kegiatan kesusastraannya kepada proses penciptaan karya sastra saja, dan kurang mengimbangi dan memperhatikan aspek-aspek yang lebih mendasar dan lebih dinamis.2
Maka tak heran bila pada tanggal 28 Februari 1997 yang lalu, ketika Kuswaidi Syafi’ie bersama Syaf Anton WR datang ke Annuqayah dalam rangka Silaturrahim Penyair Sumenep ke P.P. Annuqayah—yang diselenggarakan oleh Sanggar Andalas—yang diisi dengan kegiatan dialog terbuka bersama Kuswaidi Syafi’ie, para peminat sastra di Annuqayah dibuat geger.
Kuswaidi Syafi’ie—seorang kelahiran Bluto, yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester X Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta—telah membakar santri-santri penggemar sastra di Annuqayah dengan satu ide besarnya: tentang Gerakan Sastra Anti Zawawi-isme yang digembonginya. Diawali dengan pembacaan puisinya yang berjudul Terbacok Celurit Sendiri (
Maka melalui tulisan berikut ini, penulis ingin sekedar menyumbangkan beberapa butir pemikiran guna menjelaskan dasar-dasar Gerakan Sastra Anti Zawawi-isme itu dalam perspektif filosofis. Ini bukan berarti bahwa penulis adalah seorang pendukung Kuswaidi Syafi’ie, walau bukan berarti pula sebagai penentangnya. Hanya saja, penulis beranggapan bahwa ada sesuatu yang perlu dipelajari lebih lanjut di balik “ide-ide nakal” seorang Kuswaidi Syafi’ie itu, yang amat signifikan guna lebih meningkatkan kualitas komunitas sastra Madura pada umumnya, dan komunitas sastra di pesantren (Annuqayah) pada khususnya.
Zawawi dan Komunitas Sastra Madura
Tak dapat disangkal bahwa D. Zawawi Imron adalah seorang sosok penyair Madura yang cukup sukses di pentas nasional. Setelah pada tahun 1987 bukunya yang berjudul Nenek Moyangku Airmata mendapat hadiah Yayasan Buku Utama, pada tahun 1990 kumpulan sajak berjudul Celurit Emas dan Nenek Moyangku Airmata terpilih sebagai buku terbaik oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Terakhir, pada penghujung 1995 yang lalu Zawawi memenangkan Lomba Cipta Sajak yang diselenggarakan oleh ANteve. Sajaknya yang berjudul Dialog Bukit Kemboja itu oleh A. Mustofa Bisri diolok-olok sebagai “sajak termahal di dunia” karena honornya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta
Apalagi di pulau kelahirannya, Madura. Nama Zawawi betul-betul dikenal dengan baik. Karena beliau memilih untuk tetap tinggal di desa kelahirannya di Batang-Batang, Zawawi sering kali mengisi kegiatan-kegiatan diskusi sastra dan kegiatan-kegiatan sastra yang lain di Madura, sehingga terjalin sebuah komunikasi yang begitu dekat. Ini membuat namanya semakin populer di kalangan pecinta sastra Madura.
Terlalu banyak hal-hal yang menjadi kepopuleran Zawawi di mata komunitas sastra Madura tetap bertahan hingga kini. Perilaku Zawawi—yang sehari-hari di dusunnya beliau disebut kiai6—yang sederhana, ramah dan peduli dengan “orang-orang kecil” bisa dijadikan sebagai contoh yang simpel.
Namun, satu hal yang amat disayangkan oleh Kuswaidi adalah bahwa ternyata popularitas Zawawi itu kemudian menciptakan sebuah kondisi yang kurang sehat dalam komunitas sastra Madura. Menurut Kuswaidi, pengaruh popularitas Zawawi yang begitu kuat ini kemudian membuat para pecinta sastra Madura dalam beberapa sisi banyak mengikuti gaya-gaya Zawawi dalam penulisan karya sastra (baca: puisi). Kelanjutannya tentu bisa ditebak: model dan
Kondisi inilah yang digugat dan ditentang oleh Kuswaidi.
Menurut Kuswaidi, kondisi ini dalam tahap yang lebih jauh memandulkan kreativitas para pecinta sastra Madura dengan hanya berkutat dalam satu
Kuswaidi sendiri tidak begitu bangga dengan Zawawi, karena Zawawi tak lebih dari sekedar penyair lokal saja. Pandangannya ini berdasar pada kenyataan bahwa Zawawi sering menggunakan idiom-idiom bahasa Madura yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.8 Kuswaidi juga melihat bahwa pilihan-pilihan kata yang digunakan Zawawi dalam puisi-puisinya masih berbau lokal. Akibatnya, kata-kata seperti runjangan, pohon pelambang, dan sebagainya—yang dapat kita temui dalam puisi-puisi Zawawi—oleh Kuswaidi dikritik akan menjadi sulit bila diterjemahkan ke dalam bahasa lain.
Ide-Ide Kuswaidi dan Trend Postmodernisme
Bila ditelusuri dengan cermat, Gerakan Sastra Anti Zawawi-isme ala Kuswaidi ini adalah salah satu bentuk model gerakan postmodernisme dalam dunia sastra (Madura).
Subversif. Itulah ungkapan yang cukup representatif untuk menggambarkan bentuk gerakan pemberontakan Kuswaidi.9 Kuswaidi telah bertindak subversif dengan ingin memberontak tatanan komunitas sastra Madura yang telah “mapan”. Pemberontakan Kuswaidi ini dalam perspektif postmodernisme bisa dilihat sebagai salah satu perwujudan strategi dekonstruksi ala Derrida. Dalam arti usaha untuk menggugat pemusatan dan homogenitas yang mensubordinasikan mereka yang dianggap the other—menurut istilah Michel Foucault—dalam komunitas sastra Madura.10
Seperti sudah dimaklumi, gerakan postmodernisme pada dasarnya juga melakukan perlawanan terhadap klaim adanya “yang tunggal” yang berperan sebagai pusat. Bagi postmodernisme, tak ada pusat yang tunggal. Yang ada adalah pluralitas radikal.
Arah komunitas sastra Madura yang selama ini memusat pada gaya-gaya Zawawi, inilah yang ditentang Kuswaidi. Dengan membongkar situasi yang demikian, Kuswaidi ingin membela suara kelompok-kelompok sastra yang sebenarnya memiliki kualitas cukup baik, tetapi raib di bawah dominasi dan pengaruh Zawawi yang melebihi batas. Dalam konteks yang demikian,
Demikianlah. Kelompok komunitas sastra Madura yang masuk dalam kategori “wacana-wacana tertindas” itu kemudian melakukan resistensi sebagai upaya subversif untuk melepaskan diri dari cengkeraman homogenitas yang tiranik. Dalam kategori kelompok inilah sebenarnya Kuswaidi menggembongi gerakannya.
Menghadapi kondisi yang demikian Kuswaidi menggunakan strategi “mikro-politik” post-Marxist, dengan mengaktifkan paralogy. Paralogy yang dimaksud adalah ‘gerakan menggerogoti permainan bahasa yang telah mapan dan dominan dengan cara mengaktifkan perbedaan-perbedaan, serta mengadakan inovasi dan eksprimentasi terus-menerus’. Tujuannya ialah agar ‘memberikan peluang bagi karakter-karakter lokal tiap wacana, argumentasi dan legitimasi untuk dihargai’ sehingga akhirnya terbentuk ‘keragaman narasi-narasi kecil dan meta-argumen yang saling mencari peluang untuk tampil kokoh dan diakui dalam percaturan bahasa’.11
Akhirnya, yang diinginkan Kuswaidi mungkin adalah intensifikasi dinamisme—sebuah ciri khas yang disebutkan oleh ‘bapak’ postmodernisme, Jean-Francois Lyotard dalam bukunya yang amat terkenal: The Postmodern Condition: A Report on Knowledge—yaitu ‘upaya yang tak henti-hentinya untuk mencari kebaruan, eksprimentasi dan revolusi kehidupan terus-menerus’.12
Mungkin, inilah titik kulminasi gerakan subversif Kuswaidi. Seperti kata Kuswaidi sendiri bahwa ia menginginkan agar komunitas sastra Madura dapat lebih baik dengan lahirnya karya-karya tulis yang beragam dan tidak monoton pada gaya seorang Zawawi, sehingga akhirnya kreativitas komunitas sastra Madura akan lebih berkualitas dan kaya dengan khazanah-khazanah sastra yang masih akan memiliki keunikan tersendiri.
Dari sini kita dapat menatap lebih jauh bahwa sasaran Kuswaidi selanjutnya adalah kesemarakan dunia sastra (Madura) yang dinamis. Untuk target yang diinginkan ini, Kuswaidi memesankan para pecinta sastra Madura agar lebih memperkaya wawasan kesusastraan mereka. Ini bisa dilakukan dengan tidak hanya menjadi penyantap puisi-puisi Zawawi saja. Perlu pula mempelajari model-model penulis puisi yang lain. Karya-karya Goenawan Mohammad, Afrizal Malna, Nirwan Dewanto, dan para penyair yang lain tidak kalah menariknya untuk dinikmati. Di samping itu, satu hal yang amat penting menurut Kuswaidi adalah pemekaran wawasan dengan jalan membaca berbagai buku-buku ilmu pengetahuan—semacam filsafat, sains, sejarah, dan sebagainya—sehingga sang penulis bisa menemukan idiom-idiom baru yang segar dalam imajinasinya.
Sikap-sikap eksklusifisme dalam menerima bentuk-bentuk baru dari luar memang perlu diwaspadai. Sebab ia akan menyekap imajinasi kita dalam sebuah goa gelap yang kemudian membuat kita buta dengan realitas-realitas lain yang ada.
Catatan Penutup
Dengan dasar konsep-konsep postmodernismenya, Kuswaidi memang hadir begitu mengejutkan. Terutama di kalangan komunitas sastra Madura. Keterkejutan yang hadir sama persisnya dengan keterkejutan para ilmuwan dalam menanggapi kondisi postmodernisme seara umum.
Tetapi, konsep-konsep postmodernisme yang hadir begitu mencengangkan itu memang masih serba absurd dan penuh dengan ambiguitas. Ada sebagian kalangan yang memberikan peringatan akan hadirnya sikap dan tindakan yang anarkis di balik gerakan postmodernisme.13 Dekan Fakultas Sastra UGM, Djoko Suryo berkomentar bahwa bila konsep-konsep postmodernisme tidak dilandasi dengan pemahaman yang kuat tentang akar-akar spiritualitasnya, ia akan mencipta seni atau budaya yang anarkis.14
Dalam konteks kritisisme Kuswaidi kepada kondisi komunitas sastra Madura yang sedemikian rupa ini, patut disadari akan bahaya munculnya sikap-sikap yang melampaui nilai-nilai etis para penyair dengan tetap menjaga nilai-nilai persaudaraan di antara mereka.15 Walaupun ‘perang ide’ itu harus bebas dari segala bentuk ekspresi fisik yang tidak etis, tetapi sebuah ‘perang ide’ bagaimanapun memang harus dijaga kesinambungannya untuk tidak menimbulkan sikap-sikap subyektif dan ambivalen.
Biarpun demikian, pada akhirnya memang patut disadari bahwa semangat postmodernisme memang sudah mulai menghentak-hentak dan merasuki komunitas sastra Madura. Inti kehadirannya adalah: menghargai mereka yang semula disisihkan, dilecehkan, dan ditindas—walaupun dalam konteks ini memang agak berlebihan.
Catatan Kaki
1. Lihat, kata pengantar Syaf Anton WR berjudul Isyarat Moral Melalui Gelombang dalam Antologi Isyarat Gelombang, Sanggar Andalas, PPA Lubra Guluk-Guluk, November 1996, h. vii.
2. Suatu hal yang bisa dijadikan indikator adalah bahwa ternyata masih amat jarang para pecinta dan pekerja seni di pesantren yang suka membaca tulisan-tulisan yang bermuatan analisis sastra di majalah-majalah ataupun koran. Bahkan, cerpen—sebagai salah satu bentuk karya sastra yang memiliki keunikan tertentu—masih cukup jarang disentuh mereka. Indikator yang lebih nampak adalah ketika diselenggarakan kegiatan diskusi sastra.
3. Dapat dilihat dalam Antologi Risalah Badai, Ittaqa Press,
4. Hal ini diindikasikan ketika dibuka kesempatan dialog ternyata—seperti yang sudah penulis duga sebelumnya—hampir semua pertanyaan yang diajukan tidak berhubungan dengan apa yang dipresentasikan Kuswaidi, yaitu tentang Gerakan Sastra Anti Zawawi-isme, kecuali hanya dua pertanyaan saja.
5. Lihat, tulisan Abdul Wachid B.S. dalam pengantar Wawancara Proses Kreatif bersama D. Zawawi Imron dalam D. Zawawi Imron, Bantalku Ombak, Selimutku Angin, Ittaqa Press, Yogyakarta, Agustus 1996, h. 136.
6. Ibid.
7. Semua yang penulis ungkapkan mengenai ide-ide Kuswaidi tentang Gerakan Sastra Anti Zawawi-isme dalam tulisan ini berdasar kepada ingatan penulis ketika mengikuti acara Silaturrahim Penyair Sumenep bersama Kuswaidi Syafi’ie dan Syaf Anton WR, pada tanggal 28 Februari 1997 yang dilaksanakan oleh Sanggar Andalas di PP. Annuqayah. Sayang sekali, ketika penulis menghubungi Sanggar Andalas untuk meminjam dokumentasi rekaman acara dialog bersama Kuswaidi itu, ternyata kasetnya tidak terlacak karena sedang dipinjam seseorang. Dokumentasi pribadi pun yang penulis miliki berupa oret-oretan singkat ketika mengikuti acara tersebut juga tidak ditemukan. Selain itu, tulisan ini ditulis dengan jatah waktu yang amat terbatas, mengingat permintaan redaksi yang amat mendesak.
8. Seperti judul buku kumpulan puisi Zawawi yang berjudul Bantalku Ombak Selimutku Angin yang diterbitkan oleh Ittaqa Press,
9. Menurut Ihab Hassan, “Postmodernism is essentially (sic) subversive in form and anarchic in its cultural spirit” (Postmodernisme pada dasarnya subversif dalam bentuk, dan anarkis dalam semangat kulturalnya). Ungkapan Ihab Hassan ini bisa dilihat dalam tulisannya, “Postmodernism: A Paracritical Bibliography”, sebagaimana dikutip oleh Julia I. Suryakusuma, “Pascamodernisme dan Feminisme: Les Liaisons Dangereuses” dalam Majalah Horison, No. 02 Th. XXVIII, 1994, h. 41.
10. Dalam konteks yang lebih luas tentang pemberontakan “wacana-wacana tertindas” ini, cukup menarik pendapat Faruk HT, peneliti muda pada Pusat Penelitian Kebudayaan (PPK) UGM. Menurut Faruk, karena dunia kesenian dan kesusastraan kita telah lama mengalami kegelisahan akibat berbagai dominasi nilai dan otoritas dari pusat, seniman-seniman
11. I. Bambang Sugiharto, Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat, Kanisius,
12. Ibid.
13. Yos Rizal Suriaji, “Awas, Anarki di Belakang Posmo!”, dalam Republika, 20 Januari 1994.
14. Ibid.
15. Dalam pengantarnya pada acara Silaturrahim tersebut, Syaf Anton WR menegaskan perlunya upaya untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etis dalam proses interaksi antar komunitas sastra Madura.
Tulisan ini dimuat di Jurnal Pentas, Jurnal Keilmuan Siswa Madrasah Aliyah 1 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep edisi keenam bulan Maret 1997.


.jpg)