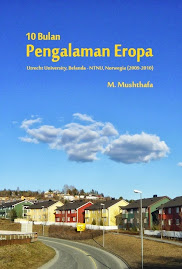Sungguh saya merasa sangat beruntung berkesempatan untuk bersepeda di negeri Kincir Angin ini. Tak seperti saat di Jogja, saya dan para pengguna sepeda yang lain di sini mendapatkan banyak keistimewaan dan kenyamanan dalam mengayuh kereta angin dan menyusuri berbagai sudut negeri Belanda. Ada jalur khusus sepeda lengkap dengan rambu-rambunya. Tempat parkir sepeda dapat ditemukan dengan mudah di mana-mana. Beberapa peta yang saya dapatkan, dari kampus dan dari pengelola apartemen, juga mencantumkan jalur khusus sepeda dengan tanda tertentu. Lebih dari itu, di jalanan, sepeda dianakemaskan oleh aturan lalu-lintas: di banyak tempat dengan tanda khusus, kendaraan bermotor wajib mendahulukan atau memberi kesempatan bagi pengguna sepeda untuk melintas.
Karena itulah, tak heran jika 85 persen orang Belanda memiliki paling tidak satu sepeda. Tiap tahun, 1,3 juta sepeda baru terjual di negeri yang juga terkenal dengan bunga tulip dan berpenduduk sekitar 16 juta orang ini. Setiap berangkat ke kampus di pagi hari dengan bersepeda, sepanjang jalan saya akan mengayuh bersama para pengguna sepeda yang lain. Ada yang sudah berusia cukup lanjut, dan bahkan ada juga yang tampak berusia masih setingkat anak Sekolah Dasar. Mereka mengayuh sepeda dengan cepat dan tangkas.
Kekaguman saya semakin bertambah saat menyadari bahwa ternyata sepeda di sini sangat fungsional. Sejauh saya berkeliling di sekitar kawasan kota Utrecht dan Zeist dalam hampir dua bulan ini, saya menemukan berbagai desain sepeda sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masing-masing. Tak hanya keranjang belanja di depan kemudi sepeda atau tempat duduk balita yang sempat saya lihat, ada juga semacam kereta kecil yang kadang disambungkan di bagian belakang sepeda, atau bahkan di depan. Kereta kecil di belakang sepeda kadang untuk bayi, lengkap dengan penutup di bagian atasnya, sehingga si bayi dapat dengan aman dan nyaman berbaring di sana. Saya juga pernah menjumpai kereta yang isinya seekor anjing duduk manis di dalamnya. Bisa Anda bayangkan?.jpg) Tak jarang, mereka yang hendak bepergian ke luar kota juga membawa sepeda lipat mereka. Jika tak punya sepeda lipat dan hanya punya sepeda biasa, sepeda diparkir di stasiun. Karena itu, di stasiun Utrecht, misalnya, saya melihat banyak sekali sepeda yang diparkir—pasti ribuan, atau mungkin puluhan ribu. Teman apartemen saya yang asli orang Belanda mengatakan bahwa dia cukup sering kesulitan menemukan tempat parkir untuk sepedanya di stasiun Utrecht.
Tak jarang, mereka yang hendak bepergian ke luar kota juga membawa sepeda lipat mereka. Jika tak punya sepeda lipat dan hanya punya sepeda biasa, sepeda diparkir di stasiun. Karena itu, di stasiun Utrecht, misalnya, saya melihat banyak sekali sepeda yang diparkir—pasti ribuan, atau mungkin puluhan ribu. Teman apartemen saya yang asli orang Belanda mengatakan bahwa dia cukup sering kesulitan menemukan tempat parkir untuk sepedanya di stasiun Utrecht.
Minat orang Belanda untuk bersepeda juga tergambar dari sebuah website bernama “Cycling in the Netherlands” yang dikelola oleh dua orang Belanda bernama Anja de Graaf dan Paul van Roekel yang mengaku sudah lebih 30 tahun bersepeda keliling Belanda dan dunia. Laman ini menyediakan banyak informasi penting seputar bersepeda. Saya senang dengan kenyataan bahwa ada orang yang mau berbagi informasi seperti ini, untuk hal yang, mungkin bagi beberapa orang, tampak sepele—padahal bisa memberi banyak manfaat dan bisa jadi inspiratif.
Meski begitu, satu hal yang cukup menjadi hambatan dalam bersepeda bagi saya yang berasal dari negeri tropis adalah soal cuaca. Di hari kedua saya di Belanda, saya diajak rekan saya yang baik, Mas Waldi, bersepeda dari apartemen saya di Warande, Zeist, ke kampus Uithof Utrecht University. Dengan menggunakan sepeda pinjaman, saya bersepeda bersama Mas Waldi. Saat itu menjelang pukul 10 pagi. Dengan mengenakan kaos, kemeja, dan switer, sepanjang perjalanan yang beberapa di antaranya melintasi kawasan sepi yang penuh dengan pepohonan besar, saya merasakan angin yang menerpa tubuh saya menelusup di antara 3 rangkap pakaian saya itu. Sungguh, angin dingin itu terasa menusuk. Walhasil, saya sering tercecer beberapa meter di belakang Mas Waldi.
Gara-gara cuaca, kecepatan rata-rata bersepeda saya yang saya ukur selama lebih 5 tahun bersepeda di Jogja, yakni sekitar 20km/jam, menjadi sedikit menurun. Karena itu, setelah saya punya sepeda sendiri, yang, sekali lagi, saya dapatkan atas kebaikan dan pertolongan Mas Waldi, saya pun membeli perangkat-perangkat penangkal dingin: sarung tangan, topi dan jaket penahan dingin yang berbahan parasut seperti jas hujan. Sekarang, setiap kali bersepeda, hampir dipastikan saya mengenakan semua senjata penahan dingin itu.
Saat ini, setelah ketakjuban saya dengan fakta-fakta mendasar tentang sepeda di Belanda terasa mulai berkurang, mungkin karena sudah agak terbiasa, tiba-tiba terbersit satu pertanyaan lain di benak saya. Jika kenyamanan bersepeda di sini dapat dirasakan oleh semua pengguna sepeda, termasuk saya yang nota bene seorang pendatang, pertanyaannya: bagaimana kenyamanan ini pada mulanya dibentuk? Apakah ini hasil dari suatu kebijakan yang tertata tentang sistem transportasi publik, atau semata tumbuh dari bawah, dari hobi orang-orang Belanda dalam bersepeda? Apakah ini juga didorong oleh semacam nilai kepedulian atau ramah lingkungan?
Pertanyaan saya ini muncul atas dasar sebuah kecemburuan, mungkin juga mimpi, bagaimana agar ada satu kota atau satu daerah saja di Indonesia yang orang-orangnya populer menggunakan sepeda. Dengan kata lain, ramah lingkungan. Saya jadi teringat sebuah artikel di National Geographic yang menyebutkan sekilas tentang sebuah kota di Jerman, Freiburg, yang sepertiga penduduknya menggunakan mode transportasi ramah lingkungan, tanpa bahan bakar minyak. Saya jadi teringat komunitas Bike-to-Work di Indonesia. Saya jadi teringat sepeda saya di rumah—siapa yang kini menggunakannya?
Tentu saja, sebagaimana setiap peradaban memiliki sisi kelamnya masing-masing, saya juga menemukan sisi gelap “peradaban sepeda” di sini, yakni: maling sepeda. Saya mendengar cerita tentang sepeda yang hilang. Saya juga diperingatkan untuk benar-benar menjaga sepeda saya, paling tidak dengan menguncinya dan mencari tempat yang terasa aman untuk diparkir. Beberapa kali saya mendapati sepeda yang “dimutilasi”: ban depan dan atau ban belakangnya hilang dicolong orang—pemandangan serupa saya temukan di kota Paris, tepatnya di dekat Louvre. Saya juga pernah mendengar langsung umpatan seorang gadis tetangga apartemen di pagi buta saat ia tak menemukan sepedanya di tempat parkir di halaman—mestinya dia menyimpan sepedanya di gudang.
Mau menikmati video yang saya rekam sambil bersepeda di pinggiran Zeist, Belanda? Klik di sini. Atau di sini. Beri rating untuk tulisan ini di Blog Radio Nederland Wereldomroep.
Sabtu, 24 Oktober 2009
Bersepeda di Belanda
Label: Daily Life, European Adventures
Jumat, 16 Oktober 2009
Labirin Metro Kota Paris
“Deux vitres nous séparaient lorsque nos yeux se sont croisés. Dans le métro comme foudroyées, nous nous sommes regardées, choquées... Nous avions la même robe!” * Magali V. – Paris
Jika ada seseorang yang pertama kali berkunjung ke Paris, maka rekan-rekannya yang lain yang masih belum mendapat kesempatan serupa pasti akan memintanya untuk bercerita tentang situs-situs wisata terkemuka: Eiffel, Louvre, Notre-Dame, dan yang lainnya. Bila tidak dengan cerita, rekan-rekannya itu akan meminta untuk melihat foto-foto yang sempat diabadikan oleh temannya.
Menghabiskan akhir pekan selama tiga hari di Paris seminggu yang lalu, saya tak cukup punya kesan mendalam tentang simbol-simbol utama Kota Cahaya itu. Mungkin karena saya hanya sekadar—katakanlah—melintas di tempat-tempat terkenal yang telah menyedot banyak turis dunia itu. Mungkin sebenarnya saya kurang bisa menikmatinya, dan musti kembali lagi ke sana untuk bisa lebih dalam menyelaminya dengan intensitas yang lebih baik.
Karena itu, saya tak akan bercerita tentang bermacam landmark kota Paris itu. Biarlah kali ini saya berdiri di pinggiran saja, dan akan menuturkan sedikit cerita tentang labirin metro kota Paris. Ya, benar, metro. Mungkin pilihan ini juga terkait dengan kedatangan saya di Paris pada Jum'at subuh yang lalu. Saya tiba di Paris melalui Terminal Bus Internasional Gallieni, dan langsung menyusuri metro kota Paris menuju KBRI Paris di Cortambert 47.
Saat itu pagi masih begitu dingin dan irama kehidupan metro yang sebenarnya masih belum terasa. Menjelang pukul 7 pagi, saat matahari masih sejam kemudian baru akan terbit, lorong-lorong metro memang masih cukup lengang. Orang-orang mungkin masih bermalas-malasan di balik selimut tebal mereka dan menunggu matahari keluar dari peraduannya.
Ini adalah pengalaman pertama saya menggunakan jalur transportasi kereta bawah tanah, yang sebelumnya hanya saya saksikan di film-film. Begitu masuk ke lorong metro, saya langsung terkesan dengan lorong-lorongnya yang mirip labirin: berkelok, dan bercabang-cabang. Saya semakin terkesan saat singgah di beberapa stasiun metro lainnya yang memiliki lebih banyak lorong, seperti République dan Châtelet Les Halles.
Dinding-dinding lorong metro Paris tak dibiarkan kosong begitu saja. Di kanan kiri lorong, saya menyaksikan bermacam iklan yang dibingkai dengan sangat artistik. Isinya pun juga aneka macam, mulai dari iklan produk, iklan wisata, pertunjukan teater, konser atau pameran, atau iklan layanan masyarakat.
Memperhatikan poster-poster iklan dan lalu-lalang orang di sepanjang labirin dan kereta metro kota Paris, saya dapat menangkap nuansa seni dan keragaman budaya kehidupan dan warga kota Paris. Dari kehidupan bawah tanah kota metropolitan yang dihuni oleh sekitar 12 juta orang ini, terbayang arus perjumpaan yang mungkin sangat intens di antara beragam kebudayaan dunia. Dengan cara yang cukup sederhana, lorong-lorong metro kota Paris seolah menceritakannya kepada saya.
Metro kota Paris adalah metro tersibuk kedua di kawasan Eropa setelah Moskwa. Konon, setiap hari ia melayani 4,5 juta penumpang di sepanjang 214 km rel yang dimilikinya. Saat tahu bahwa dari keenam belas jalur yang ada beberapa di antaranya sudah berusia lebih dari satu abad, terbayang betapa peradaban kota Paris dalam bidang transportasi telah dibangun sejak lama. Paris telah menyediakan basis material yang cukup baik untuk melayani pergerakan orang-orang yang hidup di dalamnya untuk mengerjakan proyek peradabannya masing-masing—untuk menyusun batu bata kecil peradabannya sehingga perlahan membentuk bangunan yang mapan dan kemudian diwariskan pada generasi berikutnya.
Saya teringat pengamen dengan harmonika di salah satu stasiun yang saya sudah lupa di mana tepatnya. Saya juga teringat seorang pengemis tua yang duduk di lantai lorong metro di atas hamparan koran yang ia gelar. Saya teringat grafiti warna-warni yang berkelebat di antara lorong kereta yang gelap—saya bertanya-tanya: bagaimana grafiti-grafiti ini dibuat? Saya teringat poster besar yang memuat gambar para pemain sepak bola tim nasional Perancis yang beberapa di antaranya berkulit hitam. Saya teringat rombongan pemuda kulit hitam yang menyanyi sepanjang lorong metro merayakan kemenangan telak Perancis atas Kepulauan Faroe, yang memberi peluang bagi Perancis untuk berlaga di Piala Dunia Afrika Selatan tahun depan.
Saya juga teringat pembicaraan-pembicaraan saya dengan beberapa teman saat menyusuri lorong-lorong metro kota Paris. Saya teringat teriakan pemuda-pemudi yang berlarian di antara kereta yang akan segera berangkat. Saya teringat poster besar bermotif seperti kaligrafi khat kufi yang saya jumpai di beberapa stasiun. Saya teringat kata-kata bijak dalam bahasa Perancis yang memuat pesan sangat multikultural di République.
Baca juga:
>> Di Jalanan Kota Jakarta
Label: Cultural Issues, Diary, European Adventures, Journey
Era Tragedi dan Pelajaran Empati
Beberapa tahun terakhir, negeri ini cukup sering diterpa bencana alam. Kali ini, gempa dahsyat terjadi di Sumatera. Ratusan korban meninggal, bangunan dan rumah tinggal roboh. Kerugian tak hanya material, karena efek psiko-sosial dari setiap bencana alam juga terus membayang.
Berbagai tragedi bencana (alam) yang susul-menyusul belakangan ini, mulai dari tsunami Aceh, banjir bandang dan longsor di sana-sini, gempa dahsyat di Yogyakarta, muntahan lumpur panas di Sidoarjo, dan yang terakhir, gempa di kawasan Sumatera, dalam tataran subjektif-spekulatif, mungkin dapat dibaca sebagai sebuah pelajaran bagi bangsa ini untuk bisa lebih penuh memahami dan menghayati pelajaran empati. Sering kali, di luar konteks bencana, rasa kemanusiaan beberapa elemen bangsa ini seperti tumpul berhadapan dengan kondisi sosial masyarakat yang mengenaskan.
Contoh yang paling mudah terkait dengan cara para pemimpin negeri ini menyikapi dan menyelesaikan kasus korban Lapindo. Lebih tiga tahun berlalu. Namun, masih banyak warga yang terlantar dan tidak jelas nasibnya. Argumen formal-prosedural yang kaku menempatkan kewajiban moral di luar prioritas dan pertimbangan.
Sementara itu, di sisi yang lain, cukup sering pula uang negera ini dihambur-hamburkan justru untuk mereka yang hidup lebih dari cukup, atau untuk seremoni yang tak substantif dan tak berhubungan langsung dengan kepedulian terhadap rakyat kecil.
Gagalnya pelajaran empati di era tragedi semacam ini pada level yang paling mendasar seharusnya dapat menggugah bangsa ini untuk kembali mempertanyakan makna kebangsaan yang telah lama dibangun bersama. Begitu sering diungkapkan bahwa sebuah bangsa dibangun dari imajinasi kolektif warga-warganya, dari sejumlah pengalaman masa lalu hingga terpatri dalam terang aktualitas masa kini. Sebuah bangsa yang baik akan mampu menghadirkan imajinasi konstruktif dalam kerangka upaya bersama mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih beradab.
Mengapa era tragedi ini hingga sekarang masih belum sepenuhnya bisa memberikan hikmah pelajaran empati untuk seluruh elemen bangsa ini? Mengapa yang mengemuka masih egoisme yang seperti menafikan kehadiran saudara setanah air? Mengapa para pemimpin negeri ini masih belum kunjung selalu memiliki kepekaan dan kepedulian yang cukup atas berbagai penderitaan yang dialami bangsa ini?
Semenjak era Orde Baru, kesewenangan penguasa telah mengikis dan menggerogoti perspektif kepedulian, rasa empati, dan rasa kebersamaan bangsa ini, hingga ke level yang cukup kritis. Nasionalisme hanya menjadi slogan, tak pernah berbekas dalam kenyataan. Jadilah, (aparat) negara tak mampu menjaga rasa kebangsaan para warganya, dan hanya menyemai benih disintegrasi. Kemudian era reformasi seperti memberi harapan baru untuk memulihkan luka berbagai elemen bangsa yang sebelumnya terinjak hak-haknya. Tapi penghayatan rasa empati yang sesungguhnya di era reformasi pun ternyata masih sering tak menemukan ruang perwujudannya.
Sekarang, marilah kita sedikit berspekulasi tentang episode tragedi yang kembali dirasakan bangsa ini. Tidakkah ini mungkin merupakan sebuah pelajaran buat seluruh elemen bangsa ini untuk menyalakan kembali imajinasi kolektif-konstruktif mereka, tentang komunitas bangsa yang betul-betul membutuhkan kebersamaan untuk menyelamatkannya dari puing kehancuran? Bila berbagai upaya berupa rekayasa sosial-politik selama era reformasi ini tak kunjung memperlihatkan hasil yang jelas untuk merekatkan kembali kebersamaan, membangkitkan empati tentang derita banyak warganya, dan betul-betul menggugah para elite untuk tak hanya berpesta dalam kuasa serta mempersembahkan yang terbaik untuk bangsanya, apakah tidak mungkin belakangan “alam” kemudian turun tangan untuk memberikan pelajarannya yang terakhir tentang empati, kepedulian, dan kebersamaan?
Mungkin dengan pembacaan subjektif-spekulatif semacam ini berbagai kisah sedih bencana alam yang menimpa bangsa ini dapat menjadi lebih bermakna bagi kelanjutan kehidupan masyarakat bangsa ini. Tentu saja perspektif pemaknaan seperti ini tidak boleh hanya berhenti pada level romantik saja, tetapi jelas harus dijangkarkan pada level objektif, dengan kerja-kerja konkret untuk terus menerjemahkan makna kebangsaan, kebersamaan, ketulusan, dan empati, dalam sebuah komunitas bangsa yang tak kunjung bisa keluar dari multibencana yang menamparnya.
Pada sisi yang lain, bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang religius. Islam, sebagai agama yang mayoritas dipeluk masyarakat Indonesia juga tak luput mengajarkan pelajaran empati semacam ini. Sesungguhnya, salah satu nilai moral puasa Ramadan, yang baru saja kita tunaikan, adalah pelajaran empati, selain pengendalian dan penyucian diri. Dalam berpuasa, umat Islam diajak untuk berempati dengan rasa lapar dan dahaga yang sehari-hari dirasakan oleh kaum papa. Ibadah puasa mendorong solidaritas manusia.
Bangsa Indonesia tak boleh selalu kehilangan momentum untuk menumbuhkan kesadaran solidaritas sosial semacam ini. Tak diragukan lagi, solidaritas dan empati saat ini amat dibutuhkan untuk menjadi nilai dasar bagi upaya bangsa ini keluar dari krisis multidimensi yang tak kunjung berhenti mendera.
Label: Social-Politics
Selasa, 06 Oktober 2009
Gempa itu Tak Datang di Malam Hari
Sebenarnya, di hari itu, Sabtu, 26 Mei 2006, saya bangun cukup awal, sebelum fajar tiba. Namun, setelah salat Subuh, saya memilih untuk tidur lagi. Maunya saya bersepeda keluar. Tapi, karena hari itu saya punya banyak agenda, saya memutuskan untuk tidur saja.
Saya mulai berbaring sekitar pukul lima. Tak sampai satu jam kemudian, tanpa saya bayangkan sebelumnya, saya dibangunkan oleh goncangan keras di lantai kamar saya. Seketika saya terbangun. Saya merasakan getaran keras dan suara yang mirip dengan deru kereta api yang melintas cepat. Masih dalam keadaan setengah sadar, di tengah penerangan kamar yang minim, ditambah lagi tak berkacamata sehingga pandangan saya agak kabur, dengan spontan saya berusaha keluar dari kamar.
Saya berusaha membuka pintu kamar secepatnya. Namun saya kesulitan. Goncangan yang masih tak berhenti itu membuat saya sulit menguasai keseimbangan. Di belakang saya, rak buku setinggi 180 cm tampak bergoyang dan mau roboh. Di dekat pintu, air mineral dalam galon berkapasitas 19 liter terdengar beriak. Setelah berusaha keras, akhirnya saya berhasil keluar dari kamar saya. Beruntung, kamar saya paling dekat ke pintu keluar rumah. Begitu keluar, saya langsung keluar, berlari ke jalan depan rumah.
Ternyata saya agak terlambat keluar. Begitu tiba di luar, orang-orang sudah tampak banyak berdiri dalam suasana yang masih penuh tanda tanya. Belum lama saya berdiri di pinggir jalan, dari arah gang tepat di barat rumah, seekor anjing putih yang cukup besar berlari cepat ke arah saya dan hampir saja menabrak saya. Saya pikir anjing itu juga panik dengan goncangan keras itu.
Goncangan masih sedikit terasa, sampai akhirnya pun mereda. Orang-orang pun saling bertanya tentang apa yang tengah terjadi. Beberapa tampak berusaha melihat lebih jelas ke arah utara, ke arah Gunung Merapi. Apakah Gunung Merapi meletus? Tapi tak ada yang tampak istimewa dari arah utara. Tak ada kepulan. Gunung Merapi, di pagi yang mulai terang itu, tampak menjulang biasa, tanpa tanda-tanda yang cukup berbeda.
Orang-orang pun kemudian tak ragu untuk menyimpulkan bahwa goncangan keras yang baru saja terjadi itu adalah gempa. Ya, gempa bumi.
Begitu merasa agak aman, saya mencoba kembali ke kamar untuk mengambil kacamata dan telepon seluler. Masuk ke kamar, saya mendapatkan kamar saya sudah berantakan. Rak buku di sisi barat kamar roboh ke arah timur. Buku-buku bertebaran. Galon air mineral juga tergeletak di lantai. Untung airnya sedang tidak penuh, sehingga air yang tumpah tidak seberapa. Saya segera mengambil kacamata, telepon seluler, dan dompet, dan kemudian segera kembali ke luar.
Di luar, orang-orang terus mencoba mencari informasi tentang kejadian di pagi itu. Namun, ternyata telepon seluler pun sulit digunakan. Listrik juga padam.
Saya berkumpul dengan teman-teman saya di kos seberang tempat saya. Adik saya juga di situ. Katanya, dia tak bisa keluar kamar sampai goncangan berakhir karena dia tak berhasil membuka kunci pintu kamarnya. Beruntung bahwa dinding dan atap kamarnya tak roboh. Ya, kami beruntung. Di perkampungan kami, Papringan, tak ada bangunan roboh. Hanya ada tembok rumah yang sebagian roboh, tepat di perempatan masuk ke jalan ke arah tempat saya.
Beberapa teman mengajak untuk melihat-lihat keadaan di sekitar Papringan. Mereka berencana ke Sapen. Saya pun mencoba menyusul mereka dengan naik sepeda. Namun, saya tak melanjutkan rencana saya begitu melihat lalu-lintas di Jalan Adisucipto yang tampak begitu kacau. Orang-orang seperti terlihat panik. Pada saat itulah saya berpikir bahwa gempa yang baru saja terjadi ini bisa jadi lebih parah dari yang saya bayangkan. Saya pun kembali ke kos.
Ternyata apa yang saya bayangkan itu memang benar. Beberapa saat kemudian, informasi yang lebih utuh berhasil didapatkan dari radio. Gempa telah terjadi. Gempa tektonik itu berkekuatan 5,9 skala Richter, terjadi pada pukul 05.55 WIB selama 57 detik. Episentrum gempa terletak di dekat pantai selatan.
Bersamaan dengan gempa susulan yang terjadi pada pukul 08.15 WIB, kepanikan bertambah karena isu tsunami menyebar di antara orang-orang yang masih kebingungan. Tentu, kata “tsunami” terdengar begitu menakutkan. Gambar-gambar tragedi Tsunami Aceh yang cukup untuk membuat orang-orang cemas masih belum hilang dari ingatan. Salah seorang teman yang pagi itu ikut berkumpul di tempat saya langsung meninggalkan saya dan teman-teman, bergegas membawa motornya tanpa mengajak saya atau teman-teman lainnya—bahkan dia lupa tak memakai alas kakinya. Begitulah. Orang-orang panik.
Semakin siang, saya semakin tahu bahwa gempa kali ini telah memakan banyak korban dan telah membuat Jogja menjadi tak lagi “berhati nyaman”. Makanan, air bersih, listrik, jelas akan menjadi masalah. Saat itu uang tunai di dompet saya cuma sekitar 25 ribu rupiah. ATM jelas tak bisa digunakan. Beruntung, tak lama setelah gempa, saya dengan adik saya sempat makan di warung sebelah yang buka sebentar.
Menyadari situasi ini, saya pun, bersama adik dan beberapa teman, memutuskan untuk pulang. Sebenarnya, sejak tengah hari, banyak mahasiswa dan orang-orang yang memutuskan untuk meninggalkan Jogja. Rupanya, pemberitaan di televisi yang memperlihatkan dahsyatnya gempa dan korban jiwa serta bangunan yang diruntuhkannya telah membuat keluarga mereka masing-masing di luar Jogja cemas, sehingga meminta mereka untuk pulang saja. Begitu pula yang terjadi dengan saya.
Dengan uang terbatas, saya pun meninggalkan Jogja sekitar pukul lima sore. Dengan uang tunai terbatas, saya naik bis sampai Solo, untuk kemudian mencari uang tunai di ATM, dan melanjutkan perjalanan ke Madura. Sepanjang perjalanan, orang-orang bercerita tentang gempa Jogja. Mereka bercerita tentang korban jiwa dan kerusakan yang terjadi di mana-mana. Sepanjang perjalanan Jogja-Solo, saya dapat menyaksikan bangunan-bangunan yang hancur, rusak, atau miring.
Dapat dikatakan bahwa saya tak mengalami kerugian material dari bencana alam ini. Meski begitu, gempa Jogja adalah satu pengalaman eksistensial yang memberi banyak hal buat saya. Saya berbincang dengan beberapa teman saya yang penduduk asli Jogja. Buat beberapa di antara mereka, gempa Jogja telah memaksa mereka untuk memulai segalanya dari awal. Tak hanya soal aspek duniawi—mereka pun akhirnya dipaksa untuk berefleksi, tentang banyak hal. Salah seorang di antaranya, yang seorang penulis dan pengamat pendidikan, mengatakan bahwa bencana ini telah menegaskan bahwa harta benda yang dikumpulkan bertahun-tahun bisa saja hilang seketika; dan yang sangat berguna ketika itu adalah para sahabat. Sungguh, ini pelajaran tentang kefanaan yang benar-benar nyata, tapi sering kali dilupakan—apakah itu berarti sebentuk pengingkaran diam-diam?
Saya kembali lagi ke Jogja tepat sepekan setelah musibah yang menewaskan lebih enam ribu korban jiwa itu terjadi. Saya bermaksud untuk membawa pulang buku-buku saya. Beruntung sekali, kamar kos saya tak roboh, karena setelah gempa terjadi, malam harinya hujan deras turun mengguyur Jogja. Salah seorang teman saya yang kamar kosnya roboh harus merelakan buku-bukunya hancur oleh hujan bercampur puing-puing bangunan.
Dua hari saya di Jogja, sebelum akhirnya pulang kembali ke Madura. Hari-hari itu saya tengah berusaha keras fokus untuk menyelesaikan tugas akhir saya yang baru saja dimulai. Dan saya berpikir bahwa situasi Jogja tak lagi kondusif untuk tugas yang harus segera saya tuntaskan itu. Dua hari di Jogja, saya sempat berkeliling melihat-lihat suasana. Ternyata, hari itu adalah hari pertama kota Jogja kembali beraktivitas, setelah selama seminggu sebelumnya dicekam sunyi akibat gempa.
Beberapa bulan setelah gempa Jogja, saya masih mendengar banyak cerita kemanusiaan yang mengundang empati, tentang bagaimana masyarakat korban gempa berusaha bangkit menyusun kehidupan baru mereka di antara harapan yang tersisa. Cerita yang agak detail saya dapatkan dari salah seorang teman kuliah saya yang akhirnya menunda urusan akademiknya dan berfokus mengorganisasi warga kampungnya untuk membangun kembali kehidupan mereka.
Kenangan tentang kejadian gempa Jogja ini serta merta muncul kembali ke benak saya beberapa hari yang lalu saat mendengar kabar bahwa gempa dahsyat terjadi meluluhlantakkan Sumatera Barat. Gempa yang terjadi pada hari Rabu, 30 September 2009 pukul 17.16 WIB itu berkekuatan 7,6 skala Richter. Dari berita yang berhasil saya ikuti, saya dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa bencana ini lebih parah daripada gempa Jogja. Korban jiwa mungkin bisa mencapai ribuan. Kekuatan gempa yang lebih besar mengakibatkan kisah-kisah tragis para korban akan terasa lebih mengiris hati. Orang-orang yang meninggal dalam reruntuhan bangunan. Dusun-dusun yang menjadi kuburan massal.
Seperti gempa Jogja, malam hari setelah gempa, hujan juga turun di sana. Saya dapat membayangkan suasana mencekam yang terjadi selama hujan turun. Bencana dahsyat baru saja terjadi. Tanpa penerangan. Suara hujan, yang mungkin bercampur guntur diiringi halilintar. Saya tak dapat membayangkan andaikan gempa itu datang di malam hari. Mungkin akan benar-benar serupa kiamat.
Malam ini, saya berjarak belasan ribu kilometer dengan mereka yang tengah dirundung duka. Dengan keterbatasan yang saya punya, saya berusaha menjangkau mereka, merasakan penderitaan mereka. Saya merasa saya punya keterbatasan untuk menunaikan kewajiban saya terhadap saudara-saudara saya yang tengah ditimpa musibah ini. Dari jauh, saya berdoa untuk mereka.
Label: Diary


.jpg)