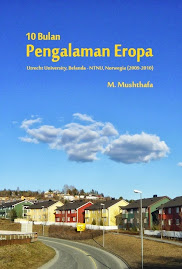Setelah Ujian Nasional (UN) SMA usai dilaksanakan selama 3 hari (22-25 April 2008), berbagai media kembali menurunkan berita tentang kebocoran dan atau kecurangan. Kasus di SMAN 2 Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, mungkin termasuk yang cukup dramatis. 16 orang guru dipergoki membetulkan lembar jawaban siswa saat ujian Bahasa Inggris di hari kedua UN. Keenam belas guru tersebut kini berstatus tersangka ditambah dengan seorang kepala sekolah.
Pro-kontra UN kembali mencuat. Perdebatan kembali mengemuka. Mereka yang membenarkan tindakan para guru yang membantu murid-muridnya seperti dalam kasus Lubuk Pakam itu berargumen bahwa para guru itu—juga murid—sebenarnya adalah korban kebijakan Depdiknas atas UN. Karena UN dijadikan tolok ukur keberhasilan pendidikan di daerah dan satu-satunya penentu kelulusan siswa, maka baik guru maupun siswa menjadi tertekan dan berupaya dengan segala cara untuk memenuhi target kelulusan yang ditetapkan.
Dari sisi positif, ketertekanan ini telah menjadikan UN sebagai pemacu semangat belajar (Fathurrofiq, Kompas, 7/1/2008). UN menuntut sekolah dan siswa untuk unjuk prestasi. Bimbingan belajar digalakkan, dan program-program pendukung serupa giat dilaksanakan. Senada dengan fenomena ini, demikianlah pendapat yang dinyatakan oleh kelompok pendukung UN, yakni bahwa UN diyakini akan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Namun demikian, aspek negatif dari tekanan target kelulusan UN juga telah banyak dikemukakan. Suparman, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia, di bulan November tahun lalu menyatakan bahwa UN telah menyebabkan proses belajar di dalam kelas bertambah kering (Kompas, 5/11/2007). Anak didik lebih hanya dilatih untuk menyiasati soal. Guru dan murid kemudian terperangkap dalam mentalitas instan, lebih mengutamakan hasil akhir dan mengabaikan proses.
Aktivitas pembelajaran kemudian diarahkan pada upaya agar siswa dapat menjawab soal-soal UN. Yang demikian ini pada gilirannya kemudian membuat arah pembelajaran rentan terlepas dari basis kebutuhan siswa yang sebenarnya. Pelajaran Bahasa Inggris di sebuah SMK jurusan perkapalan, misalnya, kemudian akan lebih difokuskan pada kisi-kisi soal seperti yang biasa muncul di dalam UN. Padahal, bisa jadi yang lebih dibutuhkan para siswa sebenarnya adalah pelajaran Bahasa Inggris dengan tema-tema yang berkaitan dengan dunia perkapalan.
Meski penolakan atas UN cukup gencar, nyatanya UN tetap dilaksanakan. Mungkin karena yang terjadi demikian, yakni UN tetap digelar, maka mereka yang menolak UN karena memandangnya sebagai “kekerasan” negara dalam dunia pendidikan— khususnya berkaitan dengan otorisasi evaluasi mutu pendidikan di tengah kesenjangan yang cukup kentara antara di kota-kota besar dan daerah—merasa menemukan semacam pembenaran untuk membantu siswa saat siswa dilihat tak mampu menjawab soal-soal ujian.
Sejauh ini, perdebatan tentang pro-kontra UN, yang kemudian juga cukup terkait dengan kasus pembocoran soal melalui sebuah upaya disengaja untuk membantu siswa, lebih banyak berfokus pada peranan negara dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, sebagaimana tergambar dalam pemaparan di atas. Kemudian, bagaimana jika kontroversi UN ini dilihat dari perspektif anak didik, terutama jika UN dilihat sebagai bagian dari seluruh proses evaluasi pendidikan?
Terlepas dari setuju atau tidak atas kasus pembocoran kunci jawaban UN dengan maksud untuk membantu siswa, jika dilihat dari perspektif anak didik, maka di balik kasus ini sebenarnya terjadi pencederaan atas hakikat pendidikan. Bagaimana para pendidik yang mestinya menjadi teladan pendidikan itu akan menjelaskan kepada para siswa dan masyarakat luas sehingga mereka harus melakukan tindakan pembocoran tersebut—bahkan jika, anggaplah, kita sepakat bahwa negara telah menerapkan kebijakan yang keliru dengan UN?
Pada titik ini, guru yang membantu siswa menjawab soal UN berhadapan dengan dilema etis: apakah dia akan membiarkan siswanya kesulitan menjawab soal-soal UN, dengan konsekuensi si anak didik kemungkinan akan tidak lulus dan kemudian frustrasi, atau dia akan membantu siswa dengan konsekuensi dia akan memperlihatkan teladan yang secara umum akan dipandang kurang baik?
Berdasarkan fakta kebocoran dan atau kecurangan yang terjadi di lapangan dan melibatkan unsur sekolah, sebagaimana dilansir berbagai media, dilema etis ini kemudian terjawab: bahwa lebih baik membantu siswa, agar mereka dapat melanjutkan proses pendidikan dengan lancar. Pilihan yang diambil semacam ini mungkin dapat dikatakan sebagai sikap pragmatis. Akan tetapi, dalam situasi yang dilematis, mereka yang memilih tindakan pembocoran ini mungkin beranggapan bahwa pemenuhan target kelulusan siswa adalah yang paling utama. Perlu digarisbawahi, fakta kebocoran yang terungkap di media boleh jadi hanyalah gunung es dari fakta yang lebih luas dan lebih memprihatinkan.
Sampai di sini, dilema etis dan pilihan sikap yang sepertinya relatif cukup banyak diambil oleh guru dan sekolah kembali menerbitkan implikasi lain yang cukup penting dikemukakan: dalam konteks proses pendidikan, UN ternyata tak cukup mampu meneguhkan sekolah sebagai tempat persemaian pendidikan karakter para siswa. Dalam konteks hasil akhir evaluasi, UN kemudian hanya menjadi semacam seremoni yang sarat dengan unsur formalitas belaka. Alih-alih meningkatkan mutu pendidikan, tekanan kuat UN malah menjadi semacam teror mental bagi sekolah dan anak didik. Di sisi yang lain, pembocoran jawaban seperti yang telah terjadi berpotensi untuk kurang menghargai siswa-siswa yang telah belajar dengan tekun dan cukup berprestasi, sehingga malah berpeluang untuk memupuk iklim malas belajar. Buat apa belajar, jika nanti saat UN akan ada tim sukses.
Sejalan dengan kerangka pemikiran Mochtar Buchori (2007: 178-180), evaluasi pendidikan melalui UN kemudian menjadi sangat simplistik dan sangat jauh untuk dapat memahami diri setiap murid secara utuh sebagai sosok pribadi (person), sehingga potensi masing-masing anak didik tak dapat dikenali dan dikembangkan secara baik di sekolah.
Implikasi dilema etis pembocoran kunci jawaban UN ini tidak hanya menjadi masalah bagi mereka yang terlibat dalam tindakan pembocoran tersebut. Ini adalah pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan oleh para pendidik di negeri ini. Arah akhirnya adalah bagaimana sistem evaluasi pendidikan di sekolah dapat membantu mendukung cita-cita pendidikan yang membebaskan, bahwa sekolah akhirnya dapat berfungsi sebagai tempat penanaman nilai-nilai dan keteladanan serta pola berpikir yang jernih bagi anak didik, untuk membentuk generasi yang berkarakter dan tangguh menghadapi tantangan zaman.
Senin, 28 April 2008
Dilema Etis Pembocoran UN
Label: Education, Ethics, Philosophy, School Corner
Selasa, 22 April 2008
Menyemai Pendidikan Lingkungan di Sekolah
Beberapa pekan terakhir, kasus penjarahan hutan kembali menguap ke media massa. Di Ketapang, puluhan tersangka ditangkap dan 12 ribu meter kubik kayu olahan disita. Di antara yang ditangkap termasuk juga aparat kepolisian,. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan bernilai triliunan rupiah. Sementara itu, sebuah data mengungkapkan bahwa laju perusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun.
Berita penjarahan hutan yang dilakukan secara berjamaah adalah salah satu tragedi lingkungan yang mengenaskan. Pembabatan hutan telah meminta ongkos sosial yang sangat mahal: perubahan iklim dan beragam bencana alam seperti longsor dan banjir pada gilirannya telah semakin sering terjadi, yang menyumbangkan kerugian tak terhingga pada masyarakat luas.
Yang menarik dicermati, kehancuran ekosistem yang mengganggu keseimbangan alam sejauh ini nyaris hanya menjadi perhatian para aktivis lingkungan saja, selain para aparat terkait. Masyarakat umum seperti tak terlalu berkepentingan dan merasa tak terhubung dengan isu-isu lingkungan. Isu-isu lingkungan oleh masyarakat umum dipersepsikan sebagai sesuatu yang hanya terkait dengan soal penebangan liar atau konservasi hutan, dan jauh dari kehidupan sehari-hari yang mereka jalani.
Pemahaman seperti ini semestinya harus diubah. Tanggung jawab untuk merawat bumi dengan segala isinya seharusnya menjadi tugas bersama, tak hanya para pejabat atau aktivis lingkungan. Menyelamatkan masa depan bumi bisa dilakukan oleh setiap orang. Kesadaran untuk peduli, memikirkan, dan ikut ambil bagian dalam upaya menjaga alam dan lingkungan semestinya ditanamkan sejak dini.
Selain di lingkungan keluarga, pendidikan lingkungan hidup akan baik jika dilakukan melalui jalur pendidikan formal atau sekolah. Isu-isu lingkungan dapat diperkenalkan secara integral dengan dipadukan ke dalam berbagai mata pelajaran yang relevan di sekolah. Anak didik sejak dini diperkenalkan dengan krisis lingkungan, seperti perubahan iklim dan pemanasan global.
Menjelaskan perubahan iklim dan pemanasan global dapat dilakukan dengan pendekatan yang sangat ilmiah. Dalam hal ini, mata pelajaran eksak (seperti fisika, kimia, atau biologi) bisa mengambil peran. Akan tetapi, isu perubahan iklim dan pemanasan global bisa juga dijelaskan dari hal-hal yang sederhana. Seperti bahwa sampah plastik turut memiliki andil terhadap perubahan iklim, bahwa sejak proses produksi hingga tahap pembuangan, sampah plastik mengemisikan gas rumah kaca ke atmosfer, bahwa kegiatan produksi plastik membutuhkan sekitar 12 juta barel minyak dan 14 juta pohon setiap tahunnya, bahwa proses produksinya sangat tidak hemat energi, dan bahwa pada tahap pembuangan di lahan penimbunan sampah (TPA), sampah plastik mengeluarkan gas rumah kaca.
Dewi Lestari, penulis novel laris Supernova yang juga seorang environmentalis, dalam weblognya (www.dee-idea.blogspot.com) menulis bahwa pelajaran ilmu alam di sekolah semestinya juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran kepada anak didik tentang hulu dan hilir dari benda-benda yang kita konsumsi sehari-hari; tentang bagaimana sumber daya alam dikuras untuk memproduksi barang-barang, dan bagaimana barang-barang yang dihasilkan itu pada akhirnya justru menjadi perusak keseimbangan alam itu.
Pendidikan lingkungan di sekolah yang bertolak dari hal-hal yang bersifat ilmiah dan dipadukan dengan contoh sehari-hari yang dekat dengan anak didik selanjutnya diarahkan pada perubahan perilaku anak didik yang lebih bersahabat dengan lingkungan. Penting untuk dicatat bahwa upaya pelestarian lingkungan dapat dilakukan dari hal yang paling sederhana, dari hal-hal yang kecil. Penangkapan para pembabat hutan mungkin merupakan salah satu contoh yang bisa jadi terasa jauh dan terlalu “besar” dari sudut pandang kehidupan sehari-hari anak didik. Sebaliknya, mengurangi penggunaan kantong plastik—atas dasar kesadaran betapa merusaknya sampah plastik bagi kelestarian alam—dapat dilakukan dari sekolah dan juga dari rumah langsung oleh anak didik.
Pada titik ini pendidikan lingkungan diharapkan dapat membiasakan anak didik untuk hidup dengan pola yang ramah lingkungan. Dengan mengambil contoh pengurangan sampah plastik misalnya, anak didik diajak untuk terbiasa menggunakan tas kain ketika berbelanja atau membawa kantong plastik bekas sendiri dari rumah. Tentu saja ini bukan langkah yang mudah—bahkan bagi seorang aktivis lingkungan sekali pun.
Menyemai pendidikan lingkungan hidup di sekolah telah menjadi perhatian para aktivis lingkungan. Pada Environmental Teachers’ International Convention (ETIC) 2008 yang diselenggarakan di Pasuruan akhir Maret lalu, penulis mendapatkan banyak pengalaman yang cukup berharga tentang beragam metode dan pendekatan yang mungkin dilakukan untuk menanamkan kesadaran lingkungan pada anak didik. Di antaranya dengan mengarusutamakan isu-isu lingkungan dalam kurikulum dan aktivitas sekolah. Juga dengan kegiatan-kegiatan lapangan yang mendekatkan anak didik dengan problem lingkungan sehari-hari.
Agenda penguatan pendidikan lingkungan di sekolah ini harus mendapatkan perhatian khusus bagi kalangan pendidik. Di kota-kota besar, lingkungan sekolah terbukti juga menjadi pusat penyumbang sampah yang tidak kecil. Seorang rekan penulis yang menjadi guru di sebuah sekolah swasta di Surabaya menyatakan bahwa di sekolahnya setiap hari rata-rata seluruh siswa membuang lebih dari 100 kemasan minuman berbahan plastik. Itu pun baru dari dua merek minuman dalam kemasan yang paling laku. Belum lagi bungkus makanan ringan yang semuanya berbahan plastik.
Data sederhana seperti ini tentu saja harus menjadi perhatian pihak sekolah untuk kemudian turut berpartisipasi menyalakan kembali kesadaran dan tanggung jawab siswa dan seluruh elemen sekolah tentang upaya pelestarian bumi. Ikhtiar ini akan sangat menantang karena pada dasarnya juga akan masuk pada soal penyadaran dan pengubahan gaya hidup kita yang kian hari nyaris semakin tak peduli dengan nasib dan masa depan bumi. Akan tetapi, jika tak kunjung dimulai, bahkan dari hal yang sangat sederhana sekali pun, nasib bumi akan semakin merana, dan itu juga berarti bahwa masa depan umat manusia juga akan suram dan nestapa.
Sabtu, 12 April 2008
Ganti Hati dan Renungan Menjemput Mati
 Judul buku : Ganti Hati
Judul buku : Ganti Hati
Penulis : Dahlan Iskan
Penerbit : JP Books, Surabaya
Cetakan : Pertama, Oktober 2007
Tebal : viii + 328 halaman
Saat pertama kali dimuat secara bersambung di Harian Jawa Pos bulan Ramadan lalu, saya tak terlalu tertarik untuk membaca tulisan Dahlan Iskan bertajuk Ganti Hati. Lagi pula, Ramadan lalu, setiap pagi, saya punya jadwal yang cukup padat sehingga saya hanya melihat-lihat headline Jawa Pos, dan membaca berita sekadarnya.
Saya baru tertarik untuk membaca buku Ganti Hati ketika saya berjumpa dengan sahabat saya di Jakarta, di sebuah acara di akhir November tahun lalu. Di sela-sela acara yang kami ikuti, teman saya yang populer dipanggil Pak Guru itu mengajak saya untuk berkunjung ke Ibu Listiana Srisanti, kepala editor fiksi Gramedia. Di sana, Pak Guru—yang nama aslinya J Sumardianta dan mengajar di SMU Kolese de Britto Yogyakarta—memperlihatkan dan bercerita buku Ganti Hati yang baru dibacanya.
Sepulang dari Jakarta, saya sempatkan membeli buku Ganti Hati itu di sebuah toko buku di Surabaya. Beberapa hari kemudian, saya membaca buku itu. Tak genap dua hari saya melahap buku setebal 300-an halaman itu (teman saya yang meminjamnya kemudian menuntaskannya tak lebih dari 7 jam!). Dan ternyata Pak Guru tak salah: Ganti Hati memang buku bagus.
Buku Ganti Hati pada dasarnya adalah semacam catatan harian Dahlan Iskan yang menceritakan pengalamannya di sekitar operasi ganti hati yang dijalaninya di sebuah rumah sakit terkemuka di Tianjin, Tiongkok. Dasar seorang wartawan, Dahlan merekam semua pengalamannya itu dengan cukup terperinci untuk kemudian disajikan dalam sebuah tulisan berseri selama 32 hari.
Karena keluasan wawasan dan pengalaman yang dimilikinya, selain mungkin juga karena teknik penulisannya yang cukup mengalir dan pintar mengelola alur, maka buku Ganti Hati ini kemudian menjadi lebih dari sekadar catatan pengalaman cangkok hati. Ia juga bisa bergerak ke sana kemari: bercerita tentang lika-liku kehidupan Dahlan yang kemudian mengantarkannya pada kesuksesan bisnis yang diraihnya saat ini, mengkritik berbagai fenomena sosial-politik, atau juga mengantar pada perenungan hidup yang mendalam di sekitar—meminjam istilahnya Pak Guru—zona sakaratul maut.
Dahlan menjalani operasi ganti hati karena livernya sudah rusak. Ada tiga kanker yang sudah berbiak dalam livernya itu, selain dua calon kanker yang lain yang siap bersarang. Secara medis, fungsi liver Dahlan sudah nyaris tak berfungsi karena mengalami sirosis. Kadar albuminnya juga rendah, yakni 2,7 (normalnya 3,2), selama lebih dari 10 tahun, sehingga Dahlan susah berkeringat dan sulit buang air kecil.
Liver Dahlan rusak akibat virus hepatitis B yang tak dapat diatasi. Karena sudah rutin disuntik, Dahlan mengira hepatitisnya sudah beres. Tapi ternyata tidak demikian. Dahlan baru sadar bahwa virus hepatitis yang mendekam dalam tubuhnya ternyata telah nyaris mengancam nyawanya pada Mei 2005, ketika dalam waktu delapan hari ia terbang ke 19 kota. Setibanya dari perjalanan maraton itu, Dahlan muntah darah di Surabaya.
Sadar bahwa penyakitnya cukup serius, Dahlan pun berobat dan berkonsultasi dengan dokter, yang akhirnya menuntunnya pada keputusan untuk melakukan operasi ganti hati. Mengapa di Tiongkok? Dalam sebuah liputan di Majalah Tempo Dahlan menjelaskan bahwa dia memilih Tiongkok karena di sana tingkat kecelakaan lalu-lintas cukup tinggi, yakni 300 orang setiap hari (sebagian pasti meninggal), sehingga kemungkinan untuk mendapatkan hati yang cocok lebih besar daripada di Singapura, misalnya—di Singapura, bisa-bisa Dahlan harus antre 10 tahun! Di Tiongkok, Dahlan menjalani operasi di Rumah Sakit Yi Zhong Xin Yi Yuan, di Tianjin. Dokter yang memimpin operasinya bernama Shen Zhong Yang. Dokter berumur 52 tahun ini sudah melakukan operasi cangkok liver lebih dari 800 kali dan mencatat berbagai rekor cangkok liver.
Dengan kepekaan insting kewartawanannya, Dahlan mencatat detik-detik proses operasi dan hal-hal penting lainnya dengan cermat, dan kemudian dituturkan dengan baik. Akan tetapi, dalam buku ini Dahlan tidak hanya bercerita aspek medis dan teknis dari operasi ganti hati yang mengharuskannya untuk dibius selama 18 jam di awal Agustus 2007 lalu. Dahlan juga menghadirkan refleksi mendalam tentang makna kesederhanaan, kesyukuran atas nikmat hidup dan kesehatan, penanganan kesehatan masyarakat oleh negara, kaitan ilmu (kedokteran) dan agama, dan sebagainya.
Salah satu yang cukup menarik adalah ketika Dahlan membandingkan keberhasilan proses operasi yang dijalaninya dengan operasi yang dijalani Nurcholish Madjid yang gagal, sehingga ketika meninggal wajah Cak Nur menghitam. Pada saat itu ada pihak-pihak yang berbicara di media mencoba menghubungkan wajah Cak Nur yang menghitam itu dengan kemurkaan Tuhan yang dikaitkan dengan almarhum Cak Nur. Dalam salah satu bagian buku ini, Dahlan membongkar mitos tak berdasar dan kadang terkesan mengada-ada itu. Dahlan menjelaskan bahwa secara medis penderita sirosis akan mengalami wajah yang menghitam. Jadi, wajah menghitam saat meninggal itu belum tentu karena kemurkaan Tuhan. Yang pasti, menurut ilmu kedokteran, karena sirosis.
Membaca utuh Ganti Hati pada akhirnya akan mengantarkan kita pada satu kesimpulan besar betapa nikmat kesehatan yang kita miliki sungguh amat mahal harganya. Ironisnya, kebanyakan kita jarang sekali memberi harga yang tepat untuk nikmat kesehatan kita itu. Sering kali kesadaran kita akan nikmat kesehatan itu baru muncul saat kita tak lagi sehat dan tak berdaya. Refleksi Dahlan di zona sakaratul maut ini menyimpan banyak hikmah yang dalam yang semakin menyadarkan kita akan makna hidup yang bergulir menuju kematian, untuk kemudian masuk ke alam keabadian.
Label: Book Review: Social
Selasa, 08 April 2008
Bulan Mei Tanpa Waktu Bumi
Akhir bulan ini, aku ingin berlibur ke bintang. Aku tak ingin berada di waktu bumi untuk sekitar enam pekan. Aku tak ingin melihat kalender, jam-jam yang berdetak, berita-berita, pesan pendek, notulensi rapat atau agenda kerja. Aku ingin rehat. Aku butuh jeda.
Aku tak akan memberitahumu ke bintang apa aku akan berlibur. Aku ingin melewati bulan Mei tidak di bumi. Lalu, setibanya kembali nanti, aku akan sangat merindukan hujan bulan Juni.
Label: Diary
Kamis, 03 April 2008
Sepekan di Kaliandra

Rombongan kami tiba di Kaliandra sekitar jam 9 malam di penghujung hari Minggu. Suasana cukup gelap. Tak banyak lampu penerangan yang menyala di halaman begitu kami masuk di gerbang yang terbuat dari bambu. Saat itu aku masih tak punya bayangan tentang tempat yang akan kami tinggali selama sepekan. Juga orang-orang yang akan bersama kami. Aku tak terlalu memikirkan itu. Perjalanan dari jelang tengah siang tadi agak melelahkan juga. Ditambah dengan udara dingin dan gerimis yang turun sejak dari Surabaya tadi.
Kami diantar ke kamar oleh seorang anak yang kira-kira seusia dengan adik bungsuku. Dia membawa payung. Kami melewati jalan menaik berbatu yang tertata rapi. Kanan-kirinya cukup rimbun. Sekilas dari beberapa bangunan yang kami lewati, aku melihat corak bangunan tradisional Jawa dengan penataan yang asri. Akhirnya kami tiba di bangunan yang disebut-sebut oleh salah seorang yang menyambut kami tadi di halaman sebagai “Rumah Anjasmara”.
Rumah Anjasmara dapat dikatakan sebagai sebuah pondokan. Sederhana, tapi bersih dan rapi tertata. Bentuknya kubus dan memiliki loteng. Pintu depan tepat ada di tengah. Begitu masuk, kita akan berada di ruang tengah yang tak begitu luas. Ada seperangkat meja kursi yang ditata di bawah tangga yang menaik ke arah loteng. Lurus dengan pintu masuk, berderet 8 kamar mandi yang memenuhi sepanjang satu sisi rumah. Sisi kanan kiri ruang tengah adalah kamar tidur yang kulihat sudah ditempati beberapa orang.
Kami dipersilakan naik ke loteng. Tepat di sisi tangga terbawah, tertempel nama-nama peserta yang akan menempati loteng. Kalau tak salah ingat, ada sekitar 15 nama lengkap dengan alamatnya. Setelah melewati tangga terakhir, kami tiba di atas. Ada sekitar lima orang yang sudah di loteng. Di loteng yang berbentuk huruf “U” itu berderet kasur-kasur yang pas untuk satu orang. Rombongan kami memilih di bagian terdekat dengan tangga untuk turun. Sebelum keluar, si anak yang mengantar kami mempersilakan kami untuk makan malam di tempat yang sudah disediakan di dekat dapur. Tapi kami sudah makan tadi di perjalanan. Kami pun menata barang-barang kami, untuk kemudian rebahan.
Pagi pertama di Kaliandra. Aku keluar dari rumah sekitar jam setengah enam. Udara masih terasa dingin sekali. Maklum, Kaliandra berada di ketinggian sekitar hampir 900 meter di atas permukaan laut. Cahaya matahari tak cukup memancarkan kehangatan. Sisa gerimis selama masih cukup terasa di rimbun dedaunan. Di luar, aku melihat-lihat keadaan, mencoba mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang tempat yang ditata menghijau ini. Akhirnya aku tiba di sebuah pendopo yang sepertinya akan menjadi tempat utama kegiatan kami selama hampir sepekan. Sebuah pendopo biasa. Ada spanduk panjang terpasang di dalam. Di depannya, halaman yang cukup luas membentang. Ada pohon beringin berdiri kokoh.
Sepertinya, halaman pendopo ini akan difungsikan sebagai tempat pameran. Kami pun menyiapkan poster sederhana dan barang-barang lainnya yang akan diikutsertakan di tempat pameran tersebut. Kesibukan kami di pagi pertama selesai saat sarapan sudah disiapkan di ruang makan terbuka yang sederet dengan rumah penginapan kami.
Setelah mandi dan sarapan, semua peserta melihat-lihat poster dan berbagai macam barang yang dipamerkan di halaman pendopo. Hampir semua menampilkan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup atau isu pemanasan global. Beberapa poster didesain dengan cukup serius.
Pembukaan resmi acara pertemuan guru lingkungan internasional ini dimulai agak siang—sekitar jam sepuluh. Selain sambutan-sambutan, kami juga disuguhi penampilan anak-anak Sekolah Ciputra yang membawakan beberapa lagu dan solo biola. Juga ada tarian tradisional Jawa. Prosesi pembukaan diakhiri dengan penyatuan tanah dan air yang dibawa oleh masing-masing tim peserta dari berbagai daerah dan penjuru dunia.
Selepas istirahat siang, acara dilanjutkan dengan pembicara utama. Seorang nenek tua yang tampak masih sangat energik. Profesor dari Universitas Negeri Malang bernama lengkap Radyastuti Suwarno. Dia berbicara dengan cukup mengalir, meyakinkan, dan tak membosankan. Namun begitu, hujan di luar yang cukup deras mengguyur cukup mengganggu konsentrasi kami mengikuti pemaparan pakar pendidikan lingkungan ini.
Selepas rehat sore, para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk diajak berkeliling di komplek Kaliandra. Selama berkeliling hingga matahari terbenam, kami mendapatkan banyak pemandangan indah di pusat pendidikan alam dan budaya yang luasnya 16 hektar ini. Masing-masing kelompok melewati jalur yang berbeda, sesuai dengan arahan pemandu. Kami naik turun bebukitan, beratus kelokan, menyeberangi semacam parit kecil, dan melewati beberapa bangunan dengan berbagai fungsi—rumah tinggal, kolam renang, pendopo, bengkel kerja, tempat pembibitan, kandang peternakan, pengolahan kompos, lumbung, dan sebagainya. Semuanya dalam lingkungan yang perdu menghijau dan penuh nuansa natural. Yang menarik, semua aktivitas dalam komplek Kaliandra ini seperti satu kesatuan yang saling menyokong, seperti sebuah sistem yang begitu menyatu padu.
Perjalanan berkeliling Kaliandra tak terasa cukup melelahkan. Udara dingin yang diselingi kabut menahan keringat di tubuh kami yang mungkin berjalan dalam jarak yang sebenarnya cukup jauh. Rehat malam berlangsung cukup singkat. Lalu dilanjutkan dengan sharing harapan dan kekhawatiran untuk kegiatan yang akan berlangsung hingga akhir pekan.
Hari kedua seharian diisi dengan presentasi. Dari pagi hingga siang, ada lanjutan presentasi dari pembicara utama, yakni dari Suko Widodo (Unair Surabaya). Selepas siang hingga malam, presentasi dilanjutkan dengan sesi paralel. Aku mengikuti sesi paralel presentasi dari utusan dari Polandia (Antoni Salamon), dan setelah itu dari Portugal (Fatima Matos Almeida).
Tim kami dari Annuqayah tampil sore harinya. Tak mengira presentasi kami cukup mencuri perhatian para peserta yang kebetulan memilih hadir di sesi kami. Seorang peserta dari Malaysia semalam memang sudah menaruh sedikit rasa takjub karena kami dari sebuah pesantren di Madura mau berbicara tentang lingkungan. Katanya, di Malaysia orang Madura memiliki citra yang kurang baik. Lagipula, pesantren di sana tak lebih dari hanya mengajar mengaji saja. Presentasi kami rupanya telah cukup mengubah citra dan kesan negatif tentang Madura—mungkin juga tentang pesantren.
Sesi malam diisi dengan pembicara utama yang tak bisa hadir tadi siang, yakni Richard Bachmann, seorang guru Sekolah Ciputra Surabaya. Dia mengantarkan diskusi pada bagaimana metode menumbuhkan kesadaran lingkungan melalui pendidikan—yang memang merupakan tajuk besar kegiatan ini.
Hari ketiga kami diajak jalan-jalan. Ada enam tempat tujuan yang disediakan panitia. Ke pantai (bakau) di Bangil, pusat industri di Pasuruan, hutan dan sawah (padi) di dekat komplek Kaliandra, sungai di Purwodadi, dan ekosistem urban di Malang. Semua peserta diminta untuk memilih tempat tujuan masing-masing. Aku memilih ikut ke sungai. Setengah sembilan keenam rombongan diberangkatkan. Perjalanan ke Sungai Kaliadem Purwodadi di belakang Kebun Raya ditempuh sekitar satu jam. Begitu tiba, kelompok kami yang terdiri dari delapan orang dibagi menjadi tiga kelompok kecil, dan diminta melakukan survei singkat lokasi. Setelah berkeliling setengah jam, kami berkumpul dan berbagi informasi tentang sungai tersebut. Setelah itu, kami pun diajak kembali ke sungai, melakukan beberapa percobaan sederhana, dan mendiskusikan isu-isu lingkungan yang terkait hingga tiba makan siang. Kami kemudian makan siang sambil melanjutkan diskusi. Kami kembali ke Kaliandra sekitar jam dua siang, ketika hujan mulai turun.
Setengah sembilan keenam rombongan diberangkatkan. Perjalanan ke Sungai Kaliadem Purwodadi di belakang Kebun Raya ditempuh sekitar satu jam. Begitu tiba, kelompok kami yang terdiri dari delapan orang dibagi menjadi tiga kelompok kecil, dan diminta melakukan survei singkat lokasi. Setelah berkeliling setengah jam, kami berkumpul dan berbagi informasi tentang sungai tersebut. Setelah itu, kami pun diajak kembali ke sungai, melakukan beberapa percobaan sederhana, dan mendiskusikan isu-isu lingkungan yang terkait hingga tiba makan siang. Kami kemudian makan siang sambil melanjutkan diskusi. Kami kembali ke Kaliandra sekitar jam dua siang, ketika hujan mulai turun.
Tiba di Kaliandra, ternyata rombongan yang lain masih banyak yang pulang datang. Tiba bersama kami, kelompok hutan dan sawah. Ditunggu-tunggu, kelompok yang lain cukup lama tiba, hingga waktu makan malam siap terhidang. Sesi malam yang mestinya sharing tentang pengalaman di lapangan tertunda. Tiap kelompok malam itu menyiapkan bahan presentasi besok.
Hari keempat seharian berupa presentasi hasil studi lapangan dari keenam kelompok. Masing-masing diminta berbagi apa yang sudah didapat, dengan penekanan pada metodologi apa yang mungkin dikembangkan untuk dapat dibawa ke sekolah atau komunitas dalam rangka penguatan kesadaran lingkungan. Sharing seharian telah cukup memberi banyak inspirasi, terutama menyangkut apa yang dapat dilakukan di masing-masing komunitas. Apa yang ada di sekitar kita ternyata dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk menyemaikan kesadaran lingkungan. Alam adalah laboratorium besar yang dapat dimanfaatkan untuk banyak hal.
Malam harinya adalah penampilan bertajuk “Cultural Night”. Masing-masing daerah diminta menampilkan kesenian tradisional. Dari Papua, Pak Faroka, Pak Sipri, dan Pak Frans tampil dengan koteka dan lagu daerah. Demikian pula dari Jawa, Bali, dan yang lain. Kami dari Madura tak punya cukup persiapan, dan tampil seadanya menyanyikan dua lagu Madura.
Hari kelima adalah hari terakhir acara resmi. Setelah sesi foto-foto di pagi hari, masing-masing kelompok diminta untuk menyusun rencana aksi. Sore harinya, rencana tindak lanjut dipajang dan disharing tanpa presentasi langsung, tapi dengan cara berkeliling saling melihat-lihat.
Malam harinya adalah malam penutupan. Malam itu kami dijamu makan malam di rumah megah Pak Bagoes, pendiri Yayasan Kaliandra. Jamuan makan malam berlangsung dengan protokoler yang cukup ketat dan resmi. Kami tiba di rumah Pak Bagoes sekitar jam tujuh lewat. Begitu tiba, kami menikmati hidangan makanan ringan, lalu tari topeng diiringi suara gamelan. Makan malam berakhir lewat jam sembilan.
Setelah makan malam, acara selanjutnya hiburan. Tapi sebelum penampilan hiburan oleh tim panitia, kami melewati acara yang cukup seru. Semua peserta diminta untuk berjalan di atas arang yang membara sepanjang tiga meter tanpa alas kaki. Saat itu waktu sudah menunjuk sekitar jam sepuluh. Sebagai persiapan, kami bermeditasi sebentar dengan dipandu panitia bernama Anam. Setelah bermeditasi, mental kami disiapkan untuk berjalan di atas arang membara. Ya, semacam latihan. Selain tip teknis saat melintas nanti, yang terpenting mental kami diperkuat dengan kata-kata penyemangat yang harus kami teriakkan keras-keras dan sepenuh hati nanti sebelum melintas arang: “Saya bisa! Saya harus bisa! Saya pasti bisa!” Kami berlatih atau bersimulasi dengan kata-kata itu dua kali.
Waktunya pun tiba. Satu per satu peserta berjalan di atas arang membara itu. Tak ada urutan yang ditentukan. Yang siap, langsung saja berangkat. Aku pun akhirnya mengambil giliran. Aku teriakkan kata-kata penyemangat itu sepenuh hati, dan aku pun berjalan di atas arang yang membara itu dengan pasti.
Malam semakin larut tanpa terasa. Setelah semua peserta melintas, kami disuguhi hiburan bermacam kesenian tradisional, sambil menikmati jajanan tradisional yang disediakan di pinggir halaman. Semua peserta menikmati semua sajian dengan penuh suka cita. Lewat tengah malam suasana masih penuh semangat. Aku dan beberapa kawan baru menuju Rumah Anjasmara setelah waktu menunjukkan jam satu dini hari lewat.
Hari keenam adalah hari terakhir di Kaliandra. Acaranya hanya penutupan resmi yang berlangsung singkat di pagi hari. Dalam acara penutupan juga ada pengumuman singkat dari panitia tentang rencana aksi terbaik yang disusun peserta. Ternyata, rencana aksi terbaik adalah milik tim kami dari Annuqayah.
Sekitar setengah sepuluh acara penutupan berakhir. Setelah itu kami berkemas untuk pulang. Mobil jemputan sudah menunggu satu jam sebelumnya. Menjelang jam sebelas siang, rombongan kami pun meluncur turun meninggalkan ketinggian Kaliandra bersama banyak hal yang kami dapatkan selama sepekan.
Tulisan terkait:
>> Inspirasi dari Kaliandra dan Malang
Label: Education, Environmental Issues, Journey




.jpg)
.jpg)