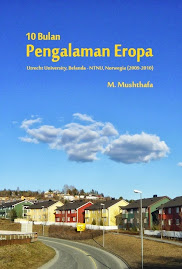Gemuruh perang Irak pelan-pelan mereda. Tapi orang-orang di sana tentu masih belum bisa mengusir sedih dan gelisah mereka: hilangnya sahabat dan kerabat tercinta, lantaknya bangunan tinggal dan tempat bersejarah, belum lagi masa depan yang masih dipenuhi jelaga. Kita yang berada di belahan dunia lain mestinya mampu berempati dengan kemanusiaan mereka yang tercederai semena-mena. Tapi sungguh, tragedi perang semacam di Irak itu bukan hanya sepenggal berita tentang direnggutnya nyawa atau harta. Bukan pula sekadar ajang permainan politik antar-negara-negara adidaya yang berebut kuasa. Sungguh, ini adalah kabar buruk tentang masa depan peradaban dunia. Di awal milenium baru ini, justru peradaban kita mengalami involusi ke titik yang cukup jauh.
Dalam film arahan Oliver Stone yang dirilis tahun 1986 berjudul Platoon, yang merefleksikan pengalaman Stone ketika terjun di perang Vietnam, Chris (diperankan oleh Charlie Sheen) berkata tentang suasana perang di Vietnam: “Konon seseorang menulis: Neraka adalah kemustahilan nalar. Aku merasakan tempat ini demikian. Ya, neraka.” Ungkapan ini dengan tepat mengungkapkan involusi peradaban yang baru saja berulang ini.
Makna involusi yang dimaksudkan di sini akan terlihat begitu benderang bila kita mencermati bagaimana Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman abad ke-18, mendefinisikan Pencerahan (Aufklärung). Pencerahan baginya adalah “jalan keluar” yang membebaskan manusia dari ketidakdewasaannya. Jalan menuju kedewasaan di sini diungkapkan Kant dengan keberanian menggunakan rasio sendiri, terangkum dalam semboyan: Sapere Aude! (Beranilah berpikir sendiri!).
Dari sini kita dapat memperoleh sebuah gambaran kontras, bagaimana perang yang dalam ungkapan Chris merenggut nalar kemanusiaan dan mencipta neraka di dunia itu pada dasarnya sungguh menggerogoti pencapaian keberhasilan manusia untuk senantiasa hidup dituntun oleh akal sehatnya. Periode Pencerahan di Barat adalah penegasan semangat Renaisans sekaligus anti-tesis pola pikir Abad Pertengahan. Etos Pencerahan di satu sisi telah mendorong banyak perkembangan pemikiran dan kemajuan peradaban, termasuk segenap hal yang diraih abad informasi sekarang ini. Tapi dari Chris, kita tersentak, bahwa ternyata kita masih bisa terjerembab ke jurang ketidakdewasaan itu.
Dalam kasus perang Irak, ketidakdewasaan itu bisa mewujud dalam cara berpikir berstandar ganda dalam memperlakukan sebuah negara. Bandingkanlah, misalnya, bagaimana Amerika memperlakukan Irak dan Israel. Ketidakdewasaan juga tercermin dalam egoisme dan kesombongan hegemonik yang dimiliki Amerika atas negara-negara yang lain.
Perang tidak saja mengoyak akal sehat, tapi juga nurani dan peradaban yang subjek utamanya adalah manusia. Perang adalah peninggalan peradaban biadab yang hanya mengedepankan kekuatan fisik. Sementara kualitas-kualitas kemanusiaan sejati diabaikan. Ironi sebuah perang memang benar-benar hanya menciptakan neraka! Dalam buku bagus berjudul Holy War, yang bercerita tentang perang suci agama, dengan lincah Karen Armstrong menyajikan gambaran ambigu dan paradoksal dari sebuah perang: betapa pada Perang Salib Keempat, tentara-tentara Kristen Eropa akhirnya malah memerangi saudara-saudara seiman mereka, yakni kaum Kristen Ortodoks Yunani, bukannya kaum muslim di Tanah Suci Yerusalem. Bukan hanya nalar yang dicampakkan, tapi bahkan iman keagamaan juga diinjak oleh adonan “kemustahilan nalar” yang menggumpal.
Kita yang hidup di tanah nusantara ini mungkin memang (semoga) tidak akan mengalami perang sedahsyat di Irak. Tapi ketidakdewasaan, sungguh masih menjadi momok yang kerap menguntit di belakang kita. Caranya bekerja memang selalu lihai, bergerak diam-diam menumpang di atas label-label pembenaran tertentu, atau bersembunyi di balik retorika dan pemutarbalikan fakta dan kata-kata, sehingga kerap sulit teridentifikasi.
Tidak perlu kita jauh-jauh membayangkan bahwa hal semacam ini terjadi pada level sosial dan bersifat massif, yang tentu saja akibatnya akan juga meluas. Seorang kepala keluarga bisa saja bertindak tidak dewasa dengan mengabaikan kemandirian berpikir anggota keluarganya dan hanya memaksa untuk menerima gagasannya, tapi tidak mengindahkan pengertian dan pengalaman kompleks anggota keluarganya atau justru bersikap apriori. Bila ini masih terjadi, elemen mendasar dalam masyarakat kita tentu akan sulit dididik berlaku dewasa.
Seusai perang, kita harus kembali mengingatkan semuanya untuk menabuh genderang perang melawan cara-cara tidak dewasa yang hanya akan menyurutkan keberadaban kita. Bahkan bila kita harus menghadapi lawan yang mungkin saja adalah diri kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa terus menjaga harkat kemanusiaan kita.
April 2003
Sabtu, 26 April 2003
Seusai Perang
Label: Cultural Issues
Jumat, 25 April 2003
Pendidikan Nilai dan Khazanah Lokal
Beberapa tahun yang lalu, dunia pendidikan kita diramaikan oleh diskusi soal format baru pendidikan moral di sekolah. Bila sebelumnya moral selalu dikaitkan dengan nilai-nilai dasar Pancasila (sebagai filosofi atau pandangan-dunia bangsa Indonesia) yang kemudian disajikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (sebelumnya disebut Pendidikan Moral Pancasila), maka diskusi tersebut berusaha memberi ruang yang lebih terbuka bagi pemaknaan moral bagi peserta didik. Gagasan yang melandasi usaha ini adalah bahwa pendidikan moral di sekolah yang berlangsung sebelumnya terlalu negara-sentris, kering, hambar, bahkan cenderung ideologis dan pro-status quo. Reformasi di bidang pendidikan moral di sekolah ini juga dipandang mendesak karena diduga salah satu biang terpuruknya bangsa ini dalam krisis multi-dimensi diakibatkan oleh kegagalan pendidikan moral di sekolah.
Formulasi substansi dan materi pengajaran pendidikan moral yang lama memang terlalu berpola deduktif, khas kebijakan politik Orde Baru yang ingin melakukan kontrol di semua bidang kehidupan. Pemaknaaan nasionalisme, misalnya, jarang sekali dikaitkan dari sudut pandang kelompok-kelompok masyarakat yang begitu beragam. Nasionalisme disajikan dalam bentuknya yang negara-sentris. Separatisme dimaknai secara hitam-putih tanpa dilihat dari perspektif yang lebih luas. Sementara itu, nilai-nilai seperti kejujuran, ketulusan, dan semacamnya, sering kali tampil sekadar semacam petuah tanpa eksplorasi mendalam dari segi raison d’être-nya, eksplisit maupun implisit.
Momentum lahirnya kebijakan otonomi daerah, yang diatur dalam UU No. 22/1999, seperti memberi nafas baru bagi dunia pendidikan kita yang terengah-engah. Berdasarkan undang-undang tersebut, wewenang terbesar bidang pendidikan berada di tangan pemerintah daerah, baik kebijakan menyangkut alokasi budget maupun kebijakan yang bersifat strategis di bidang kurikulum. Apalagi dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka perangkat pemulihan daya pendidikan semakin tersedia.
Dari perspektif otonomi pendidikan ini, menarik untuk didiskusikan peluang pengembangan pendidikan moral atau pendidikan nilai di sekolah yang berbasis pada sumber daya atau khazanah setempat, yakni yang bisa berupa sejarah atau pemikiran yang bersumber dari kearifan lokal. Asumsi dasarnya adalah bahwa dalam warisan sejarah dan pemikiran lokal itu terdapat sejumlah etos dan nilai moral yang inheren dan betul-betul hidup dalam masyarakat, sehingga ada keterjalinan yang cukup kuat antara peserta didik dengan kurikulum yang disajikan. Bahkan, khazanah yang juga bisa disebut tradisi ini pada titik tertentu dapat menjelma visi dan orientasi bersama yang dapat mengarahkan gerak maju masyarakat. Dalam ranah tersebut pula dimungkinkan terjadinya proses dialog-kreatif baik bersifat personal-eksistensial maupun sosial-kolektif dengan nilai-nilai keberadaban yang menjadi muasal akar hidup masyarakat itu sendiri.
Selain karena memang didukung oleh instrumen kebijakan yang cukup memungkinkan itu, peluang pengembangan ini menjadi cukup terbuka karena belakangan kita relatif semakin mudah mengakses khazanah lokal melalui buku-buku ilmiah populer. Beberapa penerbit seperti Kepustakaan Populer Gramedia (kelompok Penerbit Gramedia) cukup antusias menerbitkan buku bernuansa sejarah dan antropologi bertema budaya lokal, seperti Cilacap: 1830-1942 karya Susanto Zuhdi, Tapanuli: 1915-1940 karya Lance Castles, dan Makassar Abad XIX karya Edward L. Poelinggomang. Sementara Penerbit Mata Bangsa di Yogyakarta misalnya menerbitkan disertasi Prof. Kuntowijoyo berjudul Madura 1850-1940, dan penerbit LKiS menerbitkan buku Carok karya Dr. A. Latief Wiyata. Buku-buku tersebut setidaknya sudah bisa menjadi bahan awal untuk mengangkat khazanah lokal yang selama ini kurang diperhatikan untuk disajikan kepada siswa di sekolah. Belum lagi bila pemerintah daerah nantinya membaca peluang ini dan mengeksplorasi serta memberdayakan karya-karya putra daerah di seantero perguruan tinggi yang mengupas khazanah lokal tersebut. Karya-karya semacam ini yang bersifat ilmiah dan berbasis penelitian serius kemungkinan besar akan cukup banyak ditemukan di lingkungan akademik kita.
Dengan memberi ruang kepada khazanah dan sejarah lokal ini, berarti dunia pendidikan kita berusaha mempertautkan kembali keterputusan dunia pendidikan dengan proses pembudayaan yang menjadi titik akhir dari pendidikan moral itu sendiri. Proses internalisasi nilai-nilai moral tidak lagi akan bercorak terlalu deduktif, tetapi bisa lebih bersifat induktif sehingga secara perlahan dan mendalam dapat diturunkan ke lubuk pemahaman peserta didik. Alur induksi nilai-nilai tersebut menjadi mungkin karena nilai-nilai itu sendiri memang sudah terjangkarkan secara cukup baik dalam jalan panjang wawasan kebudayaan masyarakat.
Memang dalam proses penerapannya nanti kreativitas pemerintah (dalam hal ini terutama mungkin adalah Dewan Pendidikan di masing-masing kabupaten) akan banyak dituntut, terutama dalam meramu bahan-bahan untuk bidang studi ini. Demikian juga penyediaan fasilitas pendukung dan sistematisasi bahan mentah yang relatif masih belum terstruktur. Tantangan ini di sisi yang lain juga dapat meningkatkan kepedulian putra daerah bagi pengembangan pendidikan dan konservasi khazanah lokal yang belakangan terancam punah dilibat arus globalisasi.
Tulisan ini dimuat di Harian Kompas, 23 April 2003.
Kamis, 17 April 2003
Mengenali Diri dengan Cerdas Kata
Judul buku : Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza
Penulis : Hernowo
Penerbit : Kaifa, Bandung
Cetakan : Pertama, Februari 2003
Tebal : xxxii + 276 halaman
Masyarakat Indonesia pada umumnya masih memandang buku sebagai sesuatu yang mewah. Bahkan di kalangan insan pendidikan pun, buku belum mendarah-daging dalam proses pembelajaran. Kegiatan membaca dan menulis dirasakan sebagai aktivitas elitis yang memberatkan baik oleh siswa atau guru di sekolah dan dianggap sebagai kegemaran sekelompok orang yang biasa disebut orang-orang serius, intelektual, dan pemikir.
Padahal keterampilan membaca dan menulis adalah ruh proses pendidikan dan bisa menjadi basis pembelajaran. Lebih dari itu, menurut Hernowo, penulis buku ini, cerdas kata (word smart) memiliki rentang fungsi yang cukup luas, mulai dari manfaat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari (menulis surat, berbicara di depan publik), untuk memantapkan suatu profesi (wartawan, pembawa acara), hingga untuk pengembangan diri dan kepribadian.
Buku ini, yang seperti hendak mengulang sukses buku yang ditulis sebelumnya berjudul Mengikat Makna, diangkat dari pengalaman-pengalaman keseharian penulisnya bergulat dengan dunia pembelajaran dan tulis-menulis, baik sebagai seorang senior di Penerbit Mizan Bandung, guru di SMU Muthahhari, maupun sebagai dosen di STIKOM Bandung. Dari setumpuk pengalamannya itulah, Hernowo dalam buku ini berbagi pengalaman dan pemikiran perihal dunia buku dan kepenulisan.
Terhadap keprihatinan pada minimnya gairah membaca dan menulis khususnya di kalangan pendidikan sebagaimana disinggung di atas, Hernowo menyatakan bahwa kunci pendobraknya adalah revolusi paradigmatik: bahwa buku sebaiknya didorong untuk dipersepsikan sebagai makanan. Lebih tepatnya lagi, buku adalah makanan ruhani yang diperlukan untuk memupuk kepribadian sehingga mengantarkan seseorang pada kematangan diri. Tentu saja, dalam konteks ini, ada keterjalinan yang tak terhindarkan antara aktivitas membaca dan menulis itu sendiri, yang keduanya merupakan wujud dari cerdas kata.
Bertolak dari pemikiran Howard Gardner tentang multiple intelligences yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki delapan macam kecerdasan, Hernowo menduga kuat bahwa cerdas kata ini dapat menjadi gerbang pembuka pada puncak pengenalan dan revolusi diri. Dengan pengenalan diri ini, seseorang akan dapat mengembangkan dan mendewasakan kepribadian serta mendapatkan “mata baru” dalam menatap persoalan-persoalan hidup. Hernowo juga mengutip James W. Pennebaker, psikolog dari Universitas Texas, yang mengungkapkan bahwa seseorang yang dapat mengekspresikan dirinya secara sangat bebas secara tertulis akan tertolong dari serangan depresi.
Untuk tiba pada manfaat luar biasa dari aktivitas menulis itu, Hernowo dalam buku ini memberikan sejumlah trik menarik. Dalam konteks mempersepsikan buku sebagai makanan, Hernowo menganjurkan untuk memulai kegiatan membaca dan menulis dari tema-tema atau hal-hal yang kita sukai dan lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana kita memilih makanan yang kita gemari. Dalam hal menulis, menulis catatan harian menjadi sebuah aktivitas yang bisa menjadi ajang kita melumasi “mesin” menulis atau melemaskan “otot-otot” menulis kita sehingga terus terasah dengan baik. Ekspresi lepas tanpa keterikatan ketat pada pakem-pakem bahasa pada suatu titik dapat memunculkan daya kreatif yang luar biasa. Dalam hal membaca buku kita sudah cukup dibantu dengan adanya beragam bentuk penyajian buku yang dirancang untuk membantu mengenyahkan rasa bosan dan menangkap gagasan secara lebih menyenangkan. Seperti juga halnya makanan, mencicipi nikmatnya membaca dan menulis tidak perlu harus dilahap sekalian, bisa secara ngemil (sedikit demi sedikit).
Menghidupkan semangat membaca dan menulis di lingkungan keluarga dilakukan dengan menyediakan ruang kondusif bagi pembelajaran, dengan menempatkan ruang belajar yang mudah diakses dan mudah terlihat oleh anak-anak (sehingga mempertunjukkan keteladanan) dan membagikan pengalaman membaca dan menulis itu kepada keluarga dengan penyajian yang menarik. Ini juga berlaku di ruang kelas.
Rasa dan aroma bacaan yang sudah kita tangkap itu tidak boleh dibiarkan lenyap. Pengalaman membaca dan kehidupan kita sehari-hari bersifat acak, sampai kemudian ditata dalam sebuah komposisi tulisan yang membermaknakan dan menjalinnya sedemikian rupa sehingga dapat mengekspresikan kedalaman dan kesatuan emosi, gagasan, keinginan, dan harapan kita. Dalam wadah semacam itulah, seseorang mengasah seluruh potensi diri kemanusiaannya. Cerdas kata menggali potensi otak kiri manusia yang berkaitan dengan penalaran logis (ingat, tulisan menuntut struktur logis dan sistematis yang koheren) sekaligus otak kanan yang mengungkapkan kekayaan emosi (sebuah tulisan juga menggambarkan semangat, imajinasi, dan spontanitas).
Refleksi pengalaman dan pergulatan Hernowo dalam buku ini selain banyak menggagas beberapa hal untuk melembagakan kegemaran membaca dan menulis di lingkungan sekolah dan keluarga (dimensi sosial) juga berusaha merangsang optimalisasi potensi kecerdasan manusia dari sisi cerdas kata (dimensi personal-eksistensial). Kelebihan buku ini adalah gaya penyajiannya yang cukup menyenangkan, dilengkapi dengan ilustrasi dan kutipan-kutipan kata-kata menarik, dan memiliki variasi penyajian yang kaya, mulai dari tulisan bergaya makalah, esai ringan, surat, hingga berbentuk tanya-jawab. Hanya saja pemilihan simbol “pizza” sebagai makanan yang berusaha dikaitkan dengan aktivitas membaca mungkin akan terasa kurang akrab di kalangan kelas menengah ke bawah dalam masyarakat kita.
Label: Book Review: Social

.jpg)