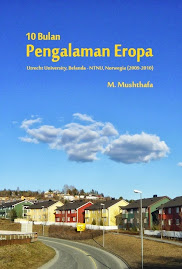Idulfitri adalah kisah perjalanan pulang menuju fitrah kemanusiaan. Berkelana di belantara dunia yang penuh karut-marut dan cenderung mencipta kegundahan, Idulfitri adalah momentum bagi kita untuk kembali pada karakter dasar manusia tanpa embel-embel identitas duniawi yang berbeda-beda yang kadang memecah belah dan dapat mengerdilkan nilai kemanusiaan.
Secara kebahasaan, kata “Idulfitri” yang berasal dari Bahasa Arab dapat berarti “kembali ke asal”. Asal yang dimaksud adalah asal penciptaan, yakni bahwa manusia terlahir suci. Berdasarkan teks kitab suci, dalam Islam diyakini bahwa fitrah manusia adalah naluri beragama (agama tauhid) dan kecenderungannya pada kebaikan. Karena itu, berbuat baik pada dasarnya menenteramkan, dan berbuat buruk harus dilakukan dengan susah payah, penuh keterpaksaaan, dan justru berujung pada kerisauan.
Fitrah untuk mengimani agama tauhid dibangun di atas keyakinan adanya perjanjian primordial antara roh manusia dengan Tuhan untuk beriman pada Tuhan Yang Maha Esa (Q.,s. Al-A’raf/7: 172). Tugas manusia adalah menjaga kesucian perjanjian iman ini dari kekufuran dan kelak harus dipertanggungjawabkan di akhirat.
Sementara itu, fitrah manusia untuk cenderung pada kebaikan dalam bahasa yang lain mungkin identik dengan pengakuan akan adanya nilai moral universal dalam konteks kemanusiaan dan peradaban. Nilai-nilai yang sama dalam semua kebudayaan ini dalam ungkapan James Rachels (2004: 60) adalah aturan moral yang diperlukan untuk menjamin kelestarian masyarakat.
Dalam perjalanannya, fitrah kemanusiaan ini, seperti juga fitrah keimanan yang sifatnya mendasar, dapat tercederai oleh kehidupan duniawi dengan berbagai godaannya. Perbuatan-perbuatan buruk, yang kadang juga bercampur dengan asumsi atau cara pandang yang kurang jernih, sekecil apapun bentuknya, lambat laun juga dapat menutupi potensi suci manusia yang cenderung pada kebajikan itu sehingga keimanan dan fitrahnya pun layu dan gugur.
Penjara Ego
Perjuangan untuk menjaga dan perjalanan untuk meraih kembali fitrah ini tentu bukan perjalanan yang mudah. Imam Jamal Rahman (2013: 174-176), praktisi dan ahli spiritualitas lintas agama dari Amerika, mencatat bahwa umat beragama kadang gagal merawat fitrah kemanusiaan ini akibat kungkungan ego yang belum berhasil dijinakkan. Wujudnya dapat berupa bias dan eksklusivitas kelembagaan serta perasaan superioritas moral atas kelompok yang lain.
Akibatnya, kita terjebak pada diri-kecil yang eksklusif dan menghalangi kita untuk menjalin ikatan kemanusiaan dalam makna yang lebih luas. Orientasi fitrah untuk berbuat kebajikan kemudian menyempit dalam lingkar kelompok tertentu. Dalam konteks kisah Adam, situasinya mungkin mirip dengan klaim iblis yang sombong dengan mengakui bahwa ia lebih baik ketimbang manusia.
Nalar eksklusif ini bertentangan dengan penjelasan al-Qur’an bahwa tujuan keberagaman dalam penciptaan manusia adalah agar manusia saling mengenal (Q., s. al-Hujurat/49: 13). Khaled Abou El Fadl (2005: 206-207), tokoh muslim moderat dari University of California Los Angeles, memaknai fakta keberagaman ini sebagai sebuah tantangan etis bagi seorang muslim untuk dapat bekerja sama dengan orang lain yang berbeda demi kebajikan bersama.
Daya tarik untuk berpikir secara eksklusif ini belakangan cenderung menguat seiring dengan semakin keruhnya lalu-lintas informasi yang mengganggu kejernihan pikiran dan kebeningan hati yang sejatinya merupakan perkakas penting dalam menjaga fitrah kemanusiaan tersebut. Berita-berita palsu (hoax) yang disebarkan sembarangan secara masif pada titik tertentu mengubah kebohongan sebagai kebenaran, dan kemudian mengotori pikiran dan hati manusia saat membuat keputusan tindakan.
Tempaan Puasa
Idulfitri dapat dilihat sebagai sebuah etape bagi perjuangan kembali kepada fitrah kemanusiaan tersebut setelah melewati fase olah tubuh dan olah batin sepanjang bulan Ramadan. Al-Qur’an menyebutkan bahwa tujuan diwajibkan puasa bagi umat Islam adalah agar kita bertakwa (Q.s, al-Baqarah/2: 183).
Menurut Fazlur Rahman (1999: 29), akar kata “taqwa” dalam Bahasa Arab berarti “menjaga atau melindungi diri dari sesuatu”. Jadi, takwa bermakna melindungi seseorang dari akibat-akibat perbuatan buruk yang dilakukannya. Dalam diri orang yang bertakwa tertanam rasa takut (kepada Allah) yang mengarahkannya pada kesadaran akan tanggung jawab di Hari Akhir sehingga ia selalu berpegang pada fitrah kemanusiaannya itu.
Meraih takwa dengan berpuasa tentu bukan perkara yang gampang. Nabi Muhammad saw telah mengingatkan bahwa tidak sedikit orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga—jauh dari capaian takwa. Tingkatan takwa ini hanya bisa diraih jika seseorang telah berpuasa menurut tingkatan ketiga sebagaimana yang dijelaskan al-Ghazali, yakni saat seseorang tidak hanya menahan lapar, dahaga, dan nafsu seksual, tetapi juga berhasil mempuasakan anggota badan dari perbuatan dosa, hati dan pikirannya dari urusan duniawi dan hal-hal yang bernilai rendah.
Menahan lapar dalam puasa menurut al-Ghazali dapat melunakkan dan menjernihkan hati dan meruntuhkan tabir yang menghalangi hati dari pancaran kebenaran sejati. Nafsu konsumsi, bahkan meski terarah pada yang halal, menurut al-Ghazali dapat menjerumuskan seseorang pada tindakan yang dapat mencederai hak orang lain.
Selain pengendalian nafsu tubuh, puasa juga adalah kesempatan untuk menajamkan refleksi dengan perenungan (tafakur) dan iktikaf yang sangat disarankan terutama pada 10 hari terakhir Ramadan. Aktivitas reflektif ini dilakukan untuk mengisi energi batin secara intensif (Chodjim, 2013: 97). Menarik diri dari keramaian dan kegaduhan hidup yang rutin dalam kerangka reflektif telah dilakukan oleh tokoh-tokoh revolusioner sebelum mendapatkan pencerahan. Buddha bermeditasi di bawah pohon Bodhi, dan Nabi Muhammad juga menyepi di Gua Hira di bulan Ramadan sebelum menerima wahyu.
Berdasarkan uraian singkat di atas, pada tingkatan yang paling tinggi, puasa memuat kekuatan penuh dari fitrah kemanusiaan untuk selalu terhubung dengan Sang Asal, untuk mematrikan kesadaran pada perjanjian primordial, dan menerjemahkannya dalam laku perbuatan.
Idulfitri dengan demikian adalah mudik rohani untuk meneguhkan kembali fitrah kemanusiaan kita. Umat Islam pada khususnya diajak untuk menyegarkan kembali makna perjanjian primordialnya dengan Allah, meneguhkan keimanan dan mengagungkan Allah, dan mengorientasikan visi keimanannya pada kebajikan untuk sesama.
Kerangka orientasi makna Idulfitri yang demikian ini tidak saja menguatkan filosofi manusia menurut perspektif Islam yang berpandangan terbuka dan menghormati keberagaman, tetapi juga menjadi pengingat bahwa sejatinya Islam adalah agama yang dapat menebarkan rahmat bagi semesta alam.
Versi lebih pendek dari tulisan ini dimuat di Koran Jakarta, 18 Juni 2018.




.jpg)