Konon, Orde Reformasi yang dimulai sejak tumbangnya kekuasaan Soeharto menandai permulaan era baru demokrasi di Indonesia. Orde Reformasi adalah saat ketika rakyat punya kesempatan untuk berbicara dan mengekspresikan aspirasinya. Lebih dari itu, Orde Reformasi menjanjikan perbaikan nasib rakyat dari berbagai hal yang mengungkung dan menyengsarakan mereka.
Di daerah, reformasi ditandai dengan munculnya wajah-wajah baru di elite kekuasaan, baik di pemerintahan maupun badan legislatif. Di daerah saya, Sumenep, atau Madura pada umumnya, hal serupa juga terjadi. Jabatan bupati bahkan dipegang oleh kalangan kiai. Banyak anggota badan legislatif yang juga berlatar belakang santri.
Setelah lebih 10 tahun bendera reformasi dikibarkan dengan penuh suka cita, perubahan apakah yang dapat terlihat di daerah saya? Yang cukup tampak adalah bahwa jalan-jalan pelosok yang dulu berbatu dan berdebu kini telah beraspal—meski kualitasnya kadang seperti murahan, lekas rusak dalam hitungan beberapa pekan. Juga, ada subsidi pendidikan untuk siswa tingkat menengah atas—meski terkesan kurang diiringi dengan rencana strategis yang matang.
Namun, jika berbicara soal pelayanan publik, saya rasa daerah saya masih berada jauh di belakang garis periode reformasi alias mengecewakan. Saya berani mengatakan demikian meski saya mendapat informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun ini menerima piagam penghargaan pelayanan publik Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Menurut laman Pemerintah Kabupaten Sumenep, penghargaan ini diberikan karena Pemkab “dinilai mempunyai komitmen kuat untuk meningkatkan pelayanan publik, dengan melahirkan berbagai kebijakan perbaikan di bidang pelayanan publik”. Banyak pengalaman dan cerita di sekitar saya yang menegaskan buruknya pelayanan publik di Sumenep. Hampir setahun yang lalu, saya mengalami sendiri bagaimana ribetnya mengurus salinan akta kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Sumenep. Pekan ini, saya kembali mendapat informasi yang semakin menguatkan pendapat saya bahwa dalam hal pelayanan publik, daerah saya sepertinya belum beranjak dari era kegelapan.
Banyak pengalaman dan cerita di sekitar saya yang menegaskan buruknya pelayanan publik di Sumenep. Hampir setahun yang lalu, saya mengalami sendiri bagaimana ribetnya mengurus salinan akta kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Sumenep. Pekan ini, saya kembali mendapat informasi yang semakin menguatkan pendapat saya bahwa dalam hal pelayanan publik, daerah saya sepertinya belum beranjak dari era kegelapan.
Melalui status Facebook seorang kawan, saya mendapat kabar bahwa ada seorang mahasiswa di Sumenep yang dijemput oleh dua orang ke rumahnya untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumenep. Masalahnya, si mahasiswa menulis surat pembaca di Jawa Pos tentang pungutan liar pembuatan KTP. Kabarnya, saat dipanggil menghadap, si mahasiswa diancam tidak akan pernah mendapat KTP selamanya kecuali ia meralat surat pembacanya itu.
Saya nyaris tak percaya mendengar kabar ini. Cara pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menanggapi surat pembaca itu sungguh tak elok sama sekali. Pungutan liar, atau apa pun namanya, dalam pembuatan KTP di Sumenep sudah jamak diketahui masyarakat. Menurut Perda No 9/2007, biaya pembuatan KTP di Sumenep Rp 6.000,-, tapi di lapangan hampir bisa dipastikan biayanya lebih besar berlipat-lipat.
Apa yang dialami si mahasiswa buat saya sungguh sangat berlebihan. Memanggilnya ke kantor dan memberinya ancaman? Wah, ini jelas bukan hal yang mestinya dilakukan seorang abdi rakyat. Bukannya melayani dan mawas diri, malah mengancam.
Tak lama setelah saya mendapat kabar ini, datang lagi kabar senada tetapi dari kantor instansi yang berbeda. Kali ini dari Dinas Pendidikan. Satu di antaranya mengabarkan tentang nasib salah seorang murid di sekolah tempat saya mengajar yang tengah meminta surat keterangan ke Dinas Pendidikan sebagai bagian dari persyaratan diterimanya ia di Institut Teknologi Bandung. Katanya, murid saya itu dimintai uang oleh salah satu staf di sana.
Kabar lainnya, masih dari sumber yang sama, menuturkan bahwa teman saya yang memberi kabar ini sudah tiga hari bolak-balik ke Dinas Pendidikan untuk semacam surat rekomendasi atau surat keterangan atas kegiatannya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Saya tidak terlalu mengerti konteks dan kronologinya. Tapi dia menceritakan tentang bagaimana ia dilempar ke sana kemari sehingga harus datang berkali-kali tanpa kejelasan yang pasti.
Saya sungguh tak mengerti dengan ini semua. Seperti yang saya rasakan tahun lalu, saya hanya bisa merasa kasihan kepada mereka. Para pejabat dan staf di kantor pemerintahan itu rasanya sungguh berada di tempat dan waktu yang salah. Jika tak mau melayani, jangan sekali-kali melamar jadi pegawai negeri. Mungkin mereka merasa bahwa mereka masih hidup di era Orde Baru, saat pemerintah bisa berbuat semena-mena dan rakyat hanyalah hamba yang mesti diam di hadapan penguasa.
Saya kira begitulah adanya. Mereka masih lelap dalam mimpi, bahwa mereka adalah penguasa, bukan abdi masyarakat. Bahwa mereka aman dalam kekuasaan negara yang menggurita dan bebas berbuat apa saja—termasuk mengancam orang yang mengusik kenyamanan mereka. Saya pikir, kita, rakyat atau masyarakat Sumenep, perlu membangunkan mereka.
Sebenarnya, saya ingin sekali mendengar kabar bahwa tokoh-tokoh masyarakat dan kalangan santri yang kini duduk di jajaran elite pemerintahan atau badan legislatif itu juga turut peduli untuk memperjuangkan perbaikan pelayanan publik di Sumenep. Mungkin memang tidak mudah melakukan perubahan dalam soal ini—apa juga karena sudah mengandung semacam unsur “mafia”? Tapi reformasi sudah lebih 10 tahun, dan belum terlihat perubahan yang berarti. Menyadari hal ini, kadang saya pesimis dan merasa bahwa sepertinya saya tak cukup tepat untuk berharap pada para elite itu.
Lalu kepada siapa saya bisa berharap? Oke, mungkin saya tak boleh terlalu apatis dengan para elite itu. Dalam kasus tertentu, memang terkadang ada di antara elite yang bisa membantu. Tapi yang saya harapkan adalah perubahan yang mendasar dan menyentuh hal-hal yang substansial, bukan hanya bantuan penyelesaian dalam kasus tertentu. Ya, mari kita mencoba sedikit berbaik sangka, bahwa di antara para elite itu masih ada yang bisa mendukung langkah perbaikan semacam ini.
Namun begitu, yang paling penting, untuk bisa ke sana, saya kira kitalah, para rakyat bawah, yang harus kompak dan konsisten bergerak bersama-sama—jangan terus menunggu para elite itu untuk berbuat sesuatu. Di tingkat paling awal, saya kira kita harus bisa memanfaatkan peluang yang diberikan oleh teknologi informasi saat ini, yakni internet, untuk bisa saling berbagi pengalaman dan pikiran guna memperbaiki semua ini. Ya, semacam langkah konsolidasi dan merintis upaya keterbukaan informasi, saat laman-laman instansi pemerintah daerah yang mungkin berbiaya tinggi itu tak cukup mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan transparansi, saat para elite kekuasaan daerah di dunia maya kadang hanya bermonolog, asyik dengan dunianya sendiri, dan kurang membuka diri dan peka atas permasalahan nyata yang dialami rakyat sehari-hari.
Jika pengalaman si mahasiswa yang diancam dan pengalaman murid saya yang dimintai uang itu dibagi bersama di ruang maya ini, mungkin kisah-kisah serupa akan bermunculan datang dari para korban dari tempat, waktu, dan instansi yang bermacam-macam. Lalu pikiran dan langkah ke arah perbaikan mungkin juga akan datang dan dapat disusun dengan lebih baik. Dan, itu semua saya pikir akan dapat menjadi suatu kekuatan besar yang tidak saja akan menjadi ironi bagi sederet penghargaan (formal) atau trofi yang didapat instansi-instansi itu, tetapi mungkin juga bisa mampu memberi efek kejut untuk membangunkan mereka yang tengah lelap dalam mimpi itu.
Ya, mungkin semacam memercikkan air ke wajah mereka yang tidur lelap atau pura-pura tidur. Agar mereka benar-benar mau bangun, lalu bersama-sama kita ajak shalat, mengaji, dan bertaubat. Bukankah konon kiamat sudah dekat—bisa jadi 2012?
Baca juga:
>> Arogansi, Mental-Tak-Mau-Melayani, ataukah Hidup-Salah-Zaman?
>> Orang Miskin Dilarang Sakit
Sabtu, 01 Mei 2010
Kisah Para Abdi yang Lelap dalam Mimpi
Label: Madura, Social-Politics
Langganan:
Posting Komentar (Atom)









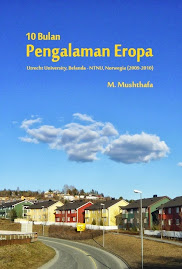




2 komentar:
KTP alais KraTo' Pae'
KTP alias Kartu Tanda Pungutan :D
Posting Komentar