Judul Buku: Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi
Penulis: Karen Armstrong
Penerbit: Serambi Jakarta bersama Mizan Bandung
Cetakan: Pertama, Agustus 2001
Tebal: xx + 641 halaman
Fundamentalisme seringkali dihubungkan dengan sikap dan pandangan keras atau militan dalam sikap keberagamaan. Orang juga sering mengaitkannya dengan terorisme dan aksi kekerasan berupa bom bunuh diri seperti kejadian tragedi gedung WTC di New York, membunuh para dokter di klinik aborsi, menembaki jamaah yang sedang beribadah, dan sebagainya.
Citra negatif yang dilekatkan pada kaum fundamentalis ini tak jarang malah berakibat memperluas medan konflik. Kaum fundamentalis menjadi semakin merasa dendam. Ditambah lagi bila solidaritas masyarakat lain yang merasa seideologi tumbuh diikuti dengan penyikapan yang mirip dengan cara-cara kaum fundamentalis.
Fenomena keberagamaan semacam itu menggejala tidak hanya pada agama-agama besar seperti Yahudi, Kristen, atau Islam, tapi juga terjadi pada agama Hindu, Budha, atau bahkan Kong Hu Cu.
* * *
Buku ini mencoba memberikan perspektif baru yang cukup menarik terhadap gejala fundamentalisme. Penulisnya, Karen Armstrong, yang juga penulis buku bestseller A History of God (yang telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Penerbit Mizan dengan judul Sejarah Tuhan) mengajukan suatu cara pandang yang berbeda dengan ilmuwan Barat pada umumnya. Bila Bassam Tibi dalam The Challenge of Fundamentalism misalnya mencoba menyorot fenomena fundamentalisme ini dari perspektif politis, sehingga akhirnya juga memberi rekomendasi yang bersifat politis berupa penguatan demokrasi (sekuler) dan hak-hak asasi manusia, maka Armstrong dalam buku ini mendekati fenomena fundamentalisme dari perspektif sosiologis dan kultural-eksistensial.
Dengan mengambil fokus pada tiga agama besar, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam, Armstrong melacak secara kronologis perkembangan fundamentalisme secara sosiologis. Kerangka yang digunakan lebih bersifat kultural-eksistensial. Artinya, fundamentalisme bagi Armstrong—terlepas dari aspek sosio-politis yang sering melekatinya—dipandang sebagai suatu eksprimen pemaknaan terhadap usaha untuk menjadi sosok yang religius ketika agama dihadapkan dalam sebuah masa transisi sosio-kultural berupa terjadinya gelombang modernisasi dan globalisasi.
Modernisme telah merombak tatanan sosial masyarakat sedemikian rupa yang bahkan menyelusup ke seluruh bidang kehidupan: ekonomi, atau sosial-politik-intelektual. Pola masyarakat yang berkembang bukan lagi masyarakat agrikultur, tetapi masyarakat industrial. Hal inilah yang menurut Armstrong dalam bidang keagamaan mendorong lahirnya berbagai ekspresi yang bersifat eksprimental sebagai bentuk budaya tanding bagi arus modernitas itu sendiri.
Secara historis hal ini sebenarnya pernah terjadi pada sekitar tahun 700-200 SM, ketika perkembangan teknologi agraria telah mendorong lahirnya kerajaan-kerajaan baru, muncul fenomena penolakan masyarakat terhadap corak teologi nenek moyang yang bersifat paganistik, beralih kepada pencarian zat agung yang bersifat tunggal, transenden, dan menjadi sumber kesakralan.
Dalam A History of God Armstrong juga menengarai bahwa pemikiran ateistik yang lahir di akhir abad ke-19 merupakan suatu reaksi terhadap ketidakcukupan konsep ketuhanan yang ada ketika itu dalam menghadapi tantangan perubahan sosial yang bersifat massif. Kelahiran fundamentalisme juga didorong oleh tuntutan pendefinisian ulang ajaran (spiritualitas) keagamaan ketika modernisasi—seperti pendapat Anthony Giddens—nyaris membunuh kultur-kultur lokal suatu masyarakat.
Uraian kronologis dalam buku ini dimulai dari tahun 1492, yang menurut Armstrong menjadi titik tolak lahirnya gejala fundamentalisme. Inilah periode yang selain dibarengi dengan lahirnya beberapa corak pemikiran filosofis yang amat berbeda dengan periode sebelumnya, juga diikuti oleh sebuah peristiwa penting yang memicu berkembangnya gejala fundamentalisme, yakni ketika Raja Ferdinand dan Ratu Isabella—dua penguasa Katolik yang pernikahannya pada waktu itu mampu menyatukan dua kerajaan Iberia kuno, Aragon dan Castile—berhasil menaklukkan negara-kota Granada.
Pendudukan ini mengakibatkan terusirnya penduduk muslim Spanyol kembali ke wilayah Timur Tengah, karena mereka diberi dua pilihan: pindah agama atau dideportasi. Demikian pula kaum Yahudi, sehingga tercatat ada sekitar 80.000 orang Yahudi yang menyeberang ke Portugal, dan 50.000 orang mengungsi ke kerajaan Utsmaniyah di Turki. Sementara itu, kaum Yahudi yang bertahan di Spanyol dan memeluk agama Kristen lambat-laun kembali ke kepercayaan semula, dan membentuk sebuah organisasi bawah tanah untuk mengajak para converso lainnya kembali ke agama asli mereka. Akan tetapi, Raja Ferdinand mencium aktivitas ini, sehingga ada 13.000 converso dibunuh oleh program Inkuisisi dalam dua belas tahun pertama program tersebut.
Memasuki abad ke-16 orang-orang Yahudi di Eropa sama sekali tidak menghirup udara bebas. Mereka tinggal dalam suatu komunitas tertutup bernama “ghetto”. Segregasi atau pemisahan ini pada akhirnya semakin meningkatkan prasangka anti-Semit, dan kaum Yahudi ini lalu memandang dunia non-Yahudi yang kejam itu dengan kepahitan dan mata penuh curiga.
Akumulasi pengalaman orang-orang Yahudi yang sedemikian pahit dan tragis inilah yang mengantarkan mereka pada suatu situasi disorientasi yang begitu dalam dan menjadikan mereka menjadi masyarakat terasing secara religius dan spiritual. Proses modernisasi yang dibawa Raja Ferdinand bagi mereka menunjukkan karakter agresif dari modernitas sehingga akhirnya mereka dituntut untuk mengembangkan suatu bentuk kepercayaan baru yang dapat membuat tradisi lama mereka tetap relevan dan berarti, di tengah-tengah situasi lingkungan yang berubah secara radikal.
Hal semacam ini pulalah yang dialami umat Islam ketika terusir dari Spanyol. Seperti diurai Armstrong di Bab 2, orang-orang Islam yang menjadi korban dari sebuah tatanan sosial baru ini lalu pindah membangun sebuah tatanan yang dalam bahasa Marshall G. S. Hodgson mengusung “semangat konservatif”. Semangat konservatif yang dibangun ini ditandai dengan diproklamasikannya pintu ijtihad yang telah tertutup, dan hanya mempersilahkan umat untuk taklid.
Konservatisme ini terus semakin menjadi-jadi ketika kawasan Timur Tengah mengalami periode imperalisme oleh bangsa Eropa pada akhir abad ke-18, sehingga memunculkan gerakan-gerakan bercorak fundamentalistik.
* * *
Cara pandang menarik yang dijadikan kerangka teoritik oleh Armstrong dalam buku ini semakin memperkokoh nilai penting buku ini dalam kondisi kekinian. Buku ini tidak saja memaparkan secara sosiologis perkembangan fundamentalisme dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Akan tetapi, perspektif Armstrong dalam menguraikan observasinya ini mengajak kita bersama untuk melihat fundamentalisme dari kacamata yang lebih bersifat positif.
Dari perspektif ini, fundamentalisme adalah sebuah kritik terhadap perkembangan modernitas yang nyaris bergerak tanpa kontrol. Modernisme yang sejak awal menjadikan manusia sebagai tolok ukur segalanya—yang secara epistemologis semula dimaksudkan untuk memperkokoh logos dan menggusur mitos dengan merayakan peran rasio—justru seringkali terjebak dalam kelemahan moral yang menganggap remeh martabat dan harga diri manusia. Acapkali ditemui sekelompok masyarakat yang dengan tega melakukan pembunuhan atas nama rasionalitas dan kemanusiaan. Ini terutama banyak dialami oleh kelompok masyarakat dunia ketiga yang terhegemoni oleh globalisasi hasil impor kelompok dunia pertama (negara-negara maju).
Buku ini menunjukkan bahwa citra negatif kaum fundamentalis bisa jadi memang merupakan suatu produk konstruksi struktural dunia modern yang hegemonik, invasif, agresif, dan destruktif. Karena itu, dengan mengangkat sisi lain fundamentalisme, buku ini kemudian memberikan suatu tawaran cara yang lebih arif dan bijak dalam menyikapi fenomena fundamentalisme. Agenda mendesak yang perlu dikedepankan adalah upaya mengatasi kekecewaan kelompok fundamentalis ini—yang sebenarnya juga dirasakan oleh kelompok lain—terhadap berbagai ekses modernisme yang tidak mengakomodasi kebutuhan spiritual manusia. Upaya-upaya untuk mencari titik kesepahaman menjadi amat penting untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik dan penuh kedamaian.
Dan buku ini dari suatu perspektif sebenarnya adalah suatu pintu masuk menuju ruang dialog yang dimaksudkan tersebut. Ditulis oleh seorang yang dibesarkan dalam tradisi dan kebudayaan Barat modern, maka buku ini tidak lain adalah suatu kritik internal masyarakat Barat terhadap produk kebudayaannya sendiri terutama dalam mempersepsikan sesuatu yang dinilai negatif dan dimiliki kelompok masyarakat lain. Buku ini adalah semacam oksidentalisme, studi ke-Barat-an yang justru dilakukan oleh orang Barat sendiri—seperti yang juga pernah dilakukan Michel Foucault ketika mengkritisi sejarah pembentukan identitas masyarakat kelas menengah Eropa. Buku ini adalah cerminan suatu sikap terbuka dan rendah hati untuk kebersediaan memahami pilihan sikap dan tindakan orang lain, dan merupakan benih dialog antar-peradaban yang selayaknya diikuti dengan sejumlah langkah bijak lainnya.
Tulisan ini dimuat di Majalah Gamma, 31 Oktober 2001.










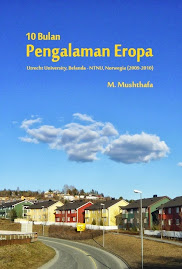




0 komentar:
Posting Komentar