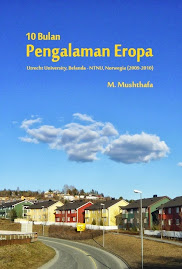Mengamati pemberitaan media tentang kasus ijazah Moh. Azhari, alumnus Madrasah Aliyah 2 Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, yang dianggap tak memenuhi persyaratan dalam penerimaan brigadir brimob dan dalmas oleh Kepolisian Resor Sumenep di bulan Juni hingga Juli 2012, saya menjadi prihatin. Saya prihatin dengan mutu pemberitaan di media yang beberapa di antaranya ternyata tak setia pada fakta.
Kasus ini menjadi cukup menghebohkan saat beberapa ribu alumnus Pondok Pesantren Annuqayah bersama unsur pondok pesantren lain di Sumenep mengadakan aksi turun jalan pada hari Selasa, 17 Juli 2012. Beberapa televisi nasional sempat menurunkan liputannya. Namun, sayangnya, beberapa bagian dalam berita itu sungguh jauh panggang dari api.
Headline news MetroTV pukul 16.00 WIB hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 memuat 3 kesalahan mendasar dalam memberitakan aksi turun jalan di Sumenep tersebut. Pertama, disebutkan bahwa pengunjuk rasa dalam aksi itu berjumlah ratusan. Kedua, kericuhan terjadi di Markas Kepolisian Resor Sumenep. Ketiga, kericuhan terjadi karena massa dihalangi petugas untuk masuk ke Mapolres Sumenep.
Ralph Tampubolon, pembaca berita pada acara tersebut tampil gagah dengan jas dan dasi serta rambut modis. Di saku jasnya, tampak saputangan menonjol sedikit keluar. Bagi yang tak tahu persis kejadian di lapangan, tentu dia akan berpikir bahwa ketiga fakta yang benar-benar tak berdasar itu benar adanya. Apalagi Ralph Tampubolon membacakan naskah beritanya dengan meyakinkan.
Faktanya, aksi turun jalan ini diikuti oleh ribuan orang. Saya sendiri tidak tahu persis jumlah peserta aksi karena tidak hadir pada kejadian tersebut. Namun beberapa sumber yang hadir menyebutkan angka paling sedikit 1.500 orang. Bahkan ada yang menyatakan mungkin sampai 3.000 orang. Sumber-sumber saya itu mungkin memang tak punya dasar teori penghitungan massa yang profesional. Tapi jika saya melihat foto-foto yang didokumentasikan dari aksi tersebut, angka ratusan itu jelas sangat jauh dari fakta.
Yang kedua, kericuhan tak terjadi di Mapolres Sumenep. Kejadian itu terjadi pada jarak sekitar 1,5 kilometer dari Mapolres, yakni di Kantor DPRD Sumenep. Gedung DPRD Sumenep berbeda dengan Mapolres. Ada patung kuda terbang di halaman DPRD, dan di Mapolres tak ada patung yang diambil dari lambang Kabupaten Sumenep itu.
Ketiga, penyebab kericuhan jelas tidak seperti itu. K. A. Dardiri Zubairi, seorang jurnalis warga produktif di Sumenep yang juga hadir pada aksi tersebut, menuliskan laporannya bahwa kericuhan terjadi saat Wakapolres yang hendak dibawa ke Guluk-Guluk tiba-tiba diambil paksa oleh sejumlah petugas. Padahal Wakapolres sebelumnya sudah menyatakan kesediaannya pada massa. Pada titik inilah massa merasa dikhianati. Apalagi kemudian ada saksi mata yang melihat bahwa petugas memukul beberapa demonstran.
Titik kejadian yang penting ini saya tanyakan ke beberapa sumber utama lainnya. Dan mereka menegaskan fakta serupa.
Atas semua ini, saya sungguh prihatin dan bertanya-tanya: dari manakah sumber berita MetroTV itu berasal sehingga ia melaporkan fakta-fakta yang boleh dibilang, maaf, asli ngawur?
Aksi hari Selasa tanggal 17 Juli itu memang menarik perhatian karena dari segi jumlah massa yang sangat banyak. Media televisi lain yang menurunkan beritanya adalah SCTV. Namun sayang, urutan kejadian yang dipaparkan pada Liputan 6 Malam itu sangat berpotensi untuk membelokkan fakta.
Ini dia kutipan berita yang dilaporkan oleh Salli Nawali itu:
“Unjuk rasa ribuan santri asal Sumenep Madura di Jawa Timur di gedung DPRD setempat berakhir rusuh. Mereka melempari polisi, merusak pos penjagaan serta pot-pot bunga lantaran merasa dilecehkan oleh Kapolres Sumenep setelah rekan mereka ditolak mendaftar dalam rekrutmen bintara Polri.”
Pemirsa yang tak mengikuti rangkaian kejadian kasus yang bermula satu bulan sebelum aksi turun jalan tersebut akan membuat kesimpulan rekaan peristiwa sederhana: ada santri ditolak mendaftar di Kepolisian, lalu teman-temannya unjuk rasa dan rusuh.
Pembawa berita menuturkan dengan penuh percaya diri sambil memainkan intonasinya saat tiba di bagian yang memaparkan tentang aksi rusuh. Dia tampak yakin dengan apa yang dia bacakan.
Saya sudah menjelaskan titik kejadian terkait penyebab kericuhan pada aksi tersebut. Yang terpenting, dalam berita ini tak dijelaskan sejumlah langkah dialog yang diambil oleh beberapa pihak untuk menjelaskan kesalahan Polres Sumenep—yang akhirnya diakui sendiri secara resmi pada tanggal 24 Juli yang lalu.
Pihak Madrasah Aliyah 2 Annuqayah pada tanggal 18 Juni sudah mendatangi Polres untuk menjelaskan status ijazah yang mereka keluarkan—bahwa MA 2 Annuqayah mengikuti sistem pendidikan nasional di bawah Kementerian Agama RI, dan seterusnya. Pada tanggal 21 Juni, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep mendatangi Polres Sumenep untuk menjelaskan hal yang sama. Tapi Polres bersikukuh bahwa keputusan mereka sudah sesuai dengan petunjuk Polda Jawa Timur.
Pada tanggal 5 Juli, Annuqayah bersama sebuah LSM bernama LKP2M mendatangi DPRD Sumenep menjelaskan duduk perkara kasus ini dan meminta DPRD Sumenep untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kapolres Sumenep, Dinas Pendidikan Sumenep, Kantor Kementerian Agama Sumenep, dan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep. Pada acara ini, Annuqayah mengeluarkan pernyataan sikap yang juga disampaikan ke Polres Sumenep.
Pada tanggal 16 Juli, Wakapolres Sumenep bersama rombongan menemui pengasuh Annuqayah. Mereka membawa alasan yang sama sebagaimana sudah diungkapkan kepada pihak MA 2 Annuqayah dan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep. Bedanya, kali ini mereka diperkuat dengan surat dari Polda Jawa Timur.
Urutan peristiwa ini, dalam pandangan saya sebagai pengurus Annuqayah yang ikut mengawal penyelesaian masalah ini, di satu sisi memperlihatkan sikap keras kepala aparat dan lembaga kepolisian untuk mengubah cara pandangnya yang nyata-nyata salah. Semua peristiwa ini juga tersiar di beberapa media setempat, termasuk juga melalui media jejaring sosial seperti Facebook atau Twitter. Dengan kata lain, masyarakat yang bisa memahami urutan kejadiannya dengan nalar sehat secara gamblang juga menyaksikan sikap keras kepala aparat dan lembaga kepolisian ini.
Proses yang panjang ini menjadi hilang dalam pemberitaan SCTV. Saya paham bahwa ada keterbatasan durasi dalam menyiarkan berita ini. Tapi menghilangkan fakta yang sangat terkait dan bernilai penting sangat berpotensi membelokkan fakta yang dipaparkan. Dan itulah yang menurut saya terjadi.
Pemberitaan dari media setempat juga ada yang memuat fakta tak berdasar. Pada terbitan 6 Juli 2012, sehari setelah Annuqayah dan LKP2M mendatangi DPRD Sumenep, harian Radar Madura dan Kabar Madura menurunkan berita pertemuan ini. Namun sayang, berita itu memuat fakta tak berdasar.
Radar Madura, yang pertama kali terbit pada 27 Juli 1999, menurunkan beritanya di halaman “Radar Sumenep” dengan judul “Ayah Azhari Ngadu ke Dewan”. Judul berita ini jelas tak berdasar. Yang hadir ke DPRD Sumenep itu adalah rombongan pengurus Annuqayah dan LKP2M. Tak ada ayah Azhari. Di dalam berita ini, dijelaskan bahwa ayah Azhari datang ke DPRD Sumenep ditemani salah seorang pimpinan MA 2 Annuqayah. Waktu kedatangannya pun salah. Di situ ditulis sekitar pukul 13.00 WIB. Padahal, 40 menit sebelum jam yang disebutkan itu, pertemuan di gedung DPRD Sumenep sudah berakhir. Pun, dalam berita itu, sama sekali tak disebutkan kutipan dari juru bicara Annuqayah pada pertemuan tersebut, K. Moh. Naqib Hasan.
Dugaan saya: tampaknya wartawan Radar Madura tak mendapatkan informasi peristiwa ini dari sumber pertama atau dari lapangan. Tapi dia dengan penuh percaya diri menulis berita ini untuk kemudian disiarkan.
Kabar Madura memuat berita pertemuan di DPRD Sumenep tanggal 5 Juli itu keesokan harinya di halaman pertama. Dalam berita berjudul “Tuntut Panitia Lokal Minta Maaf”, kalimat pertama langsung memuat fakta yang salah. Ini kutipannya:
“Aktivis Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LKP2M) Pondok Pesantren (Ponpes) Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, akan menuntut Polres Sumenep agar meminta maaf.”
Kesalahan fakta dalam kalimat ini adalah ketika penulisnya memasukkan LKP2M sebagai bagian dari Annuqayah. Padahal, LKP2M itu lembaga di luar Annuqayah. Di berita pelengkap dengan judul lainnya di halaman yang sama, Kabar Madura, yang mulai terbit sejak 1 Juni 2012 lalu, juga memuat kesalahan penyebutan rombongan Annuqayah yang hadir ke DPRD Sumenep. Di situ disebutkan ada Kepala MA 1 Putri Annuqayah. Padahal, Kepala MA 1 Annuqayah Putri sama sekali tidak terlibat dalam penanganan kasus ini dari awal sampai akhir.
Apakah pemberitaan yang tidak berdasar fakta ini hanya terjadi pada kasus ijazah Madrasah Aliyah 2 Annuqayah? Saya tidak bisa menjawab secara pasti dan ilmiah. Perlu penelitian yang lebih cermat. Tapi, sependek pengetahuan saya, tampaknya soal ketepatan fakta ini memang masih menjadi masalah utama untuk media cetak lokal di Madura.
Pada tanggal 5 Mei 2012 lalu, misalnya, Radar Madura menurunkan berita perampokan di Ketapang, Sampang. Korbannya seorang janda kaya. Namun ada beberapa fakta penting yang keliru, yakni penyebutan usia korban perampokan dan foto korban. Pada edisi keesokan harinya, Radar Madura memberi pembetulan.
 |
| Radar Madura edisi 5 Mei dan 6 Mei. Bandingkan foto yang salah dan foto yang benar. |
Saya sungguh prihatin dengan fakta bahwa ternyata baik media nasional maupun media lokal masih belum benar-benar berpegang pada ketepatan fakta yang mereka angkat sebagai prinsip mendasar jurnalisme. Saya jadi teringat tulisan Andreas Harsono dalam mengantar buku Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat (KPG, 2008) yang menuturkan bahwa Majalah The New Yorker sejak terbit tahun 1925 memperkenalkan jabatan fact checker (pemeriksa fakta) yang bertugas memeriksa ketepatan fakta yang diangkat di setiap naskah.
Apakah yang demikian ini mungkin masih terlalu ideal bagi media di Indonesia?
Dalam pandangan awam saya, ketepatan fakta adalah sesuatu yang tak bisa ditawar. Bila media tak mau setia pada fakta, dampaknya bisa panjang. Bahkan mungkin bisa fatal. Informasi yang sesat bisa menghasilkan sikap dan tindakan yang juga sesat. Tujuan utama jurnalisme, sebagaimana ditulis oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam The Elements of Journalism, “menyediakan informasi yang diperlukan agar orang bebas dan bisa mengatur diri sendiri”, akan sulit—bahkan mungkin mustahil—tercapai bila dibangun di atas dasar fakta yang tidak tepat.
Pertanyaan berikutnya: apa kita hanya bisa prihatin? Adakah sesuatu yang bisa kita lakukan?
Bagi saya, masalah ini menghadirkan dua tantangan. Pertama, kita perlu mendidik diri kita sendiri dan masyarakat pada umumnya untuk melek media, yakni untuk bisa memiliki bekal yang cukup (dan kritis) dalam mencerna informasi. Tujuannya agar sebagai pembaca kita dapat melihat celah-celah dan kemungkinan pembelokan informasi—baik disengaja atau tidak—yang mungkin terjadi.
Kedua, secara aktif kita juga ditantang untuk menghidupkan jurnalisme warga. Dahulu, saat pemerintah Orde Baru menekan dan membatasi ruang gerak media massa, Seno Gumira Ajidarma menulis sebuah esai berjudul “Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara”. Kini, ketika era kebebasan justru ternyata kadang menghadirkan media yang tidak teliti mengangkat fakta, saya bisa mengatakan: “Ketika Jurnalisme Tak Setia pada Fakta, Jurnalis Warga Harus Bicara”.
Menurut saya, kedua butir tantangan ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama. Sebuah pekerjaan yang tidak kecil, sehingga harus dikerjakan bersama-sama. Jika ini tak dilakukan, ruang publik kita bisa jadi akan terus disesaki dengan informasi-informasi palsu yang kotor dan menyesatkan.
Wallahualam.
Baca juga:
>> Melek Informasi Read More..