Setiap komunitas masyarakat tak bisa melarikan diri dari perubahan. Demikian pula pesantren. Jika dahulu pesantren dikesankan sebagai komunitas yang kolot dan ketinggalan zaman, perubahan sosial yang berlangsung saat ini perlahan memupuskan citra-citra negatif semacam itu. Hampir semua pesantren kini telah bergabung ke dalam komunitas global dan menjadi bagian dari komunitas dunia. Yang berbeda mungkin cuma takarannya saja, yakni seberapa banyak pesantren mengadopsi dan memodifikasi berbagai kecenderungan global dalam komunitasnya.
Perempuan adalah bagian dari
komunitas pesantren yang juga terlibat dalam proses perubahan tersebut. Jika
diasumsikan bahwa ruang gerak perempuan di pesantren relatif lebih kurang leluasa
dibandingkan laki-laki, maka saat ini ruang gerak tersebut semakin lega.
Perempuan pesantren tak hanya bergerak di sektor privat saja. Banyak penelitian
yang mencatat peran perempuan pesantren di ranah yang lebih luas.1
Dalam situasi seperti itu, kita
dapat menyaksikan berbagai dampak yang dirasakan kaum perempuan pesantren. Arus
perjumpaan dan interaksi mereka dengan dunia luar yang semakin intens
menghasilkan dinamika yang beragam. Tulisan ini ingin mencoba melihat secara
lebih dekat salah satu segi dinamika tersebut, yakni interaksi perempuan
pesantren dengan dunia kesusastraan.
Sastra dalam
Komunitas Pesantren
Sastra adalah bagian yang tak dapat
dipisahkan dengan pesantren. Sebagai sebuah lembaga keilmuan, pesantren
memiliki kekhasan tersendiri yang unik dan tak dimiliki oleh lembaga keilmuan
yang lain. Keunikan itu berakar pada tradisi bersastra dalam masyarakat Arab
yang kemudian dirawat dalam komunitas pesantren.
Di pesantren, ilmu-ilmu keagamaan
tradisional pada khususnya dipelajari dengan media kitab-kitab karya ulama klasik yang di antaranya ditulis dalam
bentuk puisi. Di lingkungan komunitas intelektual yang lain, bisa dikatakan
bahwa tak ada model transmisi keilmuan dengan media puisi seperti di pesantren.
Berbagai disiplin keilmuan keagamaan, mulai dari tawhid, fikih, tafsir, hadis, tata
bahasa Arab, dan yang lainnya, semuanya pasti memiliki rujukan kitab yang
ditulis dengan gaya syi’ir atau nazham.2
Dalam komunitas pesantren, ada satu
kitab yang paling masyhur yang disebut Alfiyah
karya Ibnu Malik dari Andalusia, yang memuat seribu bait puisi tentang ilmu
tata bahasa Arab. Di pesantren-pesantren tradisional atau pesantren yang masih
mempertahankan teks utuh kitab Alfiyah
tersebut sebagai bahan ajar, tak jarang ditemukan santri yang menghafalkan
larik-larik di dalamnya. Bahkan, seringkali penguasaan kitab tersebut di luar
kepala dijadikan sebagai ukuran
kealiman seorang santri atau juga menjadi bentuk kebanggaan
diri.
Tak hanya dalam transmisi keilmuan,
tradisi sastra dalam bentuk puisi juga hadir secara cukup intens dalam
kehidupan sehari-hari para santri. Kehidupan sehari-hari di pesantren banyak
menampilkan puji-pujian dan zikir keagamaan yang berbentuk puisi. Biasanya
dibacakan menjelang atau di sekitar waktu shalat. Secara khusus, syair berisi
puji-pujian kepada Nabi Muhammad saw. memiliki bentuk ekspresi yang begitu kaya
dalam Islam dan banyak diapresiasi dan hidup dalam keseharian dunia pesantren.
Bahkan, beberapa puisi tersebut dianggap memiliki kekuatan magis sehingga tak
jarang juga dibacakan sebagai doa untuk keperluan tertentu.3
Meski tidak dengan upaya yang cukup
kuat, padu, dan sistematis, tradisi syair di pesantren ini terus dipertahankan
oleh komunitasnya. Beberapa ulama lokal hingga kini masih aktif menulis
materi-materi keilmuan keagamaan dengan gaya nazham. Di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep (Madura),
K.H. Moh. Mahfoudh Husainy menulis Manzhûmat
al-Nuqâyah, yakni nazham untuk
kitab Itmâm al-Dirâyah li Qurrâ’
al-Nuqâyah karya Jalâluddîn ‘Abdurrahmân al-Suyûthî—kitab yang
menjadi muasal penamaan pesantren yang berdiri pada tahun 1887 ini. Kitab al-Nuqâyah ini merupakan sebuah kitab
tipis yang memuat 14 cabang ilmu meliputi berbagai disiplin, mulai dari ushuluddin,
ilmu tafsir, ilmu hadis, hingga anatomi, kedokteran, dan tasawuf. Hingga akhir
2003, beliau telah menuliskan hampir 1400-an larik, dan tersisa 3 disiplin ilmu
lagi yang belum diselesaikan. Pada tahun 2006, dalam perbincangan pribadi dengan
penulis, beliau mengatakan bahwa sebenarnya ketiga disiplin ilmu tersebut sudah
ditulis, tapi naskahnya tak ditemukan setelah di-tashhîh kepada salah seorang ulama terkemuka di
Madura. Sayangnya, semenjak itu, beliau sendiri tidak bisa melacak langsung
sisa naskah tersebut karena kondisi kesehatan beliau yang menurun.
Dalam bentuk yang lebih sederhana,
tradisi syiir ini kemudian menguat pula dalam bentuk ekspresi bahasa daerah. Di
Madura, banyak sekali orator yang menggunakan syiir sebagai wahana menyampaikan
pesan moral keagamaan.
“Sastra
Pesantren” dan “Sastra Islam”
Tradisi kesusastraan dalam bentuk
puisi (nazham) baik dalam rangka transmisi keilmuan dan ritual keagamaan di
pesantren masih terus bertahan hingga saat ini. Namun demikian, seiring dengan
perubahan sosial, belakangan ini muncul istilah “sastra pesantren” di dunia
kesusastraan Indonesia. Hingga saat ini, istilah tersebut memang masih belum
memiliki acuan yang baku dan ketat. Jamal D. Rahman mencatat bahwa paling tidak
ada tiga pengertian dari istilah tersebut: pertama, sastra yang
hidup di pesantren, antara lain seperti disinggung di atas; kedua, sastra yang ditulis oleh orang-orang pesantren (kiai, santri, alumni); dan ketiga, sastra yang bertema pesantren,
seperti karya Djamil Suherman, dan sebagainya. 4
Pengertian kedua dan ketiga dari
definisi sastra pesantren tersebut di atas dapat kita lihat sebagai fenomena
mutakhir perjumpaan sastra dengan dunia pesantren. Sastra pesantren dalam dua
pengertian tersebut merupakan produk perubahan zaman, ketika pesantren
berinteraksi semakin luas dengan dunia luar, saat pesantren tak lagi hanya
menggunakan aksara Arab pegon, tapi mulai intens masuk dan berkreasi dengan
dunia aksara/sastra
Indonesia, ketika industri perbukuan juga merambah ke segmen pesantren (juga
karena keterlibatan orang-orang pesantren dengan dunia penerbitan profesional,
khususnya kesusastraan). Dari kedua pengertian tersebut, muncullah banyak nama,
mulai dari K.H. A. Mustofa Bisri, H.D. Zawawi Imron, Ahmad Tohari, Acep Zamzam
Noor, Jamal D. Rahman, Hamdi Salad, Abidah El-Khalieqy, dan sebagainya.
Contoh paling mutakhir dari sastra pesantren adalah
penerbitan novel-novel populer remaja oleh Matapena, salah satu divisi
penerbitan LKiS Yogyakarta, sebuah lembaga penerbitan yang dikelola oleh
anak-anak muda NU—yakni, berlatar pesantren. Di tengah booming novel-novel populer remaja, kehadiran novel-novel Matapena
mempertegas kehadiran sastra pesantren dalam dua pengertian terakhir
sebagaimana disebut di atas.
Pembicaraan tentang sastra pesantren dalam
perkembangan kesusastraan Indonesia saat ini tak bisa dilepaskan dengan apa
yang belakangan muncul dan disebut sebagai sastra Islam atau sastra islami. Seperti halnya sastra pesantren, definisi
sastra Islam masih tak cukup terang benderang.
Sastra Islam atau sastra islami kadang
dipersamakan maknanya dengan sastra religius. Secara khusus, label sastra
Islam atau sastra islami ini tak bisa dilepaskan dari Forum Lingkar Pena (FLP),
sebuah komunitas penulis yang didirikan oleh Helvy Tiana Rosa pada 1997, karena
dari komunitas inilah karya berlabel sastra Islam banyak muncul. Helvy, alumnus
Fakultas Sastra UI yang telah menulis puluhan karya fiksi, mendefinisikan
sastra Islam sebagai
“sastra ketakterhinggaan yang berusaha mencerahkan diri sendiri, orang lain,
dan membawa menuju jalan beribadah kepada Allah”.5 Di tempat yang
lain, dijelaskan bahwa Helvy memberi gambaran seperti berikut ini:
…sebuah puisi, cerpen, atau novel Islam tidak akan
melalaikan pembacanya dari dzikrullah. Ada unsur ammar ma'ruf nahyi mungkar
dengan tanpa menggurui. Selain itu karya sastra Islam tidak akan
mendeskripsikan hubungan badani, kemolekan tubuh perempuan atau betapa indahnya
kemaksiatan, secara vulgar dengan mengatasnamakan seni atau aliran sastra apa
pun.6
Kehadiran genre sastra Islam ini
sebenarnya lebih awal daripada populernya
sastra pesantren yang disinggung tadi. Jika Matapena
lahir pada tahun 2005, maka fiksi-fiksi Islam ini bisa dikatakan secara khusus
menjadi semakin populer sejak tahun 2000. Novel Aisyah Putri (2000) karya Asma Nadia mungkin bisa disebut sebagai salah satu karya yang populer. Buku
fiksi Islam ini mengalami masa puncak kejayaannya sepanjang 2004-2005. Salah
satu tonggaknya adalah novel Ayat-Ayat
Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. Di sepanjang tahun 2005, novel yang
terbit di penghujung 2004 ini cetak ulang sebanyak sembilan kali. Di awal 2008,
saat diangkat ke layar lebar, novel ini tembus hingga cetakan ke-36 dan terjual
lebih dari 500 ribu eksemplar.7
Sukses di pasaran yang diraih
novel-novel berlabel sastra Islam atau sastra islami ini pada gilirannya memicu
lahirnya polemik-polemik di media massa tentang karya-karya jenis ini. Pro
kontra muncul. Muhidin M. Dahlan menyebutkan bahwa sisi positif dari pelabelan
ini adalah adanya ikatan emosi antarkomunitas Islam karena mampu memberi
penanda identitas yang jelas dan tuntas. Di sisi yang lain, ada kesadaran bahwa
ini adalah bagian dari gerakan dakwah. Sedang sisi negatifnya, pelabelan ini
dapat berpotensi meminggirkan karya-karya lain yang mengangkat isu kemanusiaan,
keadilan, dan semacamnya (yang merupakan elemen substantif agama), sebagai
karya yang bukan sastra bernapaskan Islam.8
Yang menarik untuk dicermati lebih
mendalam sebenarnya berkaitan dengan muatan nilai dan bahkan mungkin muatan
ideologis yang berada di balik debat label sastra Islam tersebut. Hal ini menjadi
penting dibicarakan secara lebih mendalam karena faktanya buku-buku fiksi
berlabel sastra Islam atau sastra islami inilah yang justru banyak diminati
oleh kaum (santri) perempuan di pesantren dan menjadi bacaan mereka sehari-hari (paling
tidak dalam hampir satu dekade terakhir), jauh sebelum munculnya sastra
pesantren ala Matapena. Tentu saja, sebelum muncul apa yang disebut sastra
Islam, orang-orang pesantren juga membaca karya-karya sastra Indonesia pada
umumnya, dengan intensitas perjumpaan yang beragam.
Muatan Nilai dan Ideologi
Di akhir April 2008 yang lalu, saat
Koran Tempo mengangkat ulasan cukup
panjang bertema fiksi Islam di suplemen Ruang Baca-nya, Jonru, salah seorang
penulis dan pengelola
Sekolah Menulis Online yang dikutip di reportase tersebut, memposting sebuah
tulisan di blognya dengan judul yang cukup menarik: “Beginilah Cara Koran Tempo
Menyerang Sastra Islam”. Dari judulnya saja pembaca sudah dapat menduga nuansa
yang cukup panas dari tulisan tersebut. Sebagai semacam kesimpulan, dalam
tulisan itu, Jonru memberikan catatan:
Koran Tempo
SEPERTINYA sedang membuat sebuah skenario besar untuk melawan sastra Islam.
Untuk itu, mereka membutuhkan ucapan seorang tokoh yang akan melakukan
penyerangan secara langsung. Mereka mungkin mempertimbangkan nama Ayu Utami
atau Sapardi Joko Damono atau nama-nama sastrawan lain yang selama ini
berseberangan secara aliran dan ideologi dengan Sastra Islam.
Tapi secara
jurnalistik, isu “Ayu Utami menyerang Sastra Islam”(misalnya) sama sekali tidak
menarik.
Karena itu, Koran
Tempo mungkin mencoba mencari jalan yang lebih “cerdik”. Maka profil seperti
berikut ini tentu amat menarik bagi mereka:
Seorang penulis
yang selama ini sering berkomentar kritis seputar karya-karya Sastra Islam,
kebetulan dia adalah ORANG DALAM Forum Lingkar Pena (sebuah organisasi penulis
yang giat memperjuangkan keberadaan sastra Islam), dan ia berpotensi besar
untuk diperlakukan seperti tokoh Silas pada novel The Da Vinci Code.
“Hm… ini adalah
tokoh yang paling tepat untuk kita manfaatkan dalam menyerang Sastra Islam. Ayo
lakukan! Tentu SANGAT MENARIK bila Sastra Islam diserang oleh sesama pegiat
Sastra Islam sendiri. INI BARU BERITA!!!” 9
Membaca
teks komentar ini, kita dapat merasakan suasana yang terbangun di dalamnya:
atmosfer ideologis yang cukup panas. Seakan-akan sastra Islam telah dipojokkan
dan duduk di kursi pesakitan tanpa sebuah forum pengadilan yang imbang—dan ada sebuah konspirasi di balik itu.
Seperti disinggung di atas,
popularitas istilah sastra Islam ini tak dapat dipisahkan dengan FLP. Bila
diamati secara lebih dekat, komunitas FLP itu sendiri—yang menurut Wikipedia
kini beranggotakan sekitar 5000 orang dan memiliki cabang di hampir 30 propinsi,
termasuk beberapa di luar negeri—sepertinya tidak memiliki pemahaman yang persis sama tentang apa
itu sastra Islam. Kalaupun arus utama ideologi mereka dapat digambarkan seperti
dari kutipan penjelasan Helvy di atas, anggota komunitas mereka yang begitu beragam itu
mungkin memiliki spektrum ideologis yang merentang cukup lebar.
Jonru, misalnya, di milis pasarbuku
tak ragu untuk menyebut Laskar Pelangi
karya Andrea Hirata sebagai sastra Islam. Jonru tak mau terjebak pada
simbol-simbol, bahwa yang disebut sastra Islam hanyalah sastra yang mengadopsi
simbol-simbol Islam. Jika dihadapkan dengan penjelasan Helvy di atas, bahwa “sastra
Islam tidak akan mendeskripsikan hubungan badani, kemolekan tubuh perempuan
atau betapa indahnya kemaksiatan”, Jonru memberi toleransi atas penggalan cerita yang
mengisahkan “hubungan
cinta monyet” antara Ikal dan A Ling dalam Laskar
Pelangi. Di situ Jonru menulis bahwa “dalam
konteks kemanusiaan, hal-hal seperti ini sangat manusiawi dan hampir semua
orang pernah mengalaminya, terutama ketika kita masih berada di usia pancaroba
atau pubertas.”10
Dalam konteks ini, tampaklah bahwa
salah satu norma penting dalam kategori sastra Islam atau sastra islami adalah
bahwa ia menolak ekspos seksualitas yang vulgar dalam karya sastra. Dan, bagi Jonru, penggambaran hubungan Ikan dengan
A Ling masih cukup wajar dan bisa dimaafkan. Di titik
inilah, sastra Islam kemudian tampak terlibat masuk ke dalam perdebatan soal
moralitas dalam sastra, yang di antaranya pernah cukup ramai dimuat di berbagai
media massa.
Topik Mulyana, pegiat FLP Bandung dan
editor Penerbit Syaamil Cipta Media, menegaskan bahwa FLP melawan karya-karya
serupa chiklit dan teenlit. Novel-novel semacam itu perlu
"dilawan" karena dipandang memuat nilai-nilai yang dianggap merusak
akhlak, seperti hedonisme dan sekularisme. Dalam kemasan populer, FLP tampil
sebagai chiklit dan teenlit yang menawarkan nilai-nilai
Islam.11 Nah, salah satu
simbol hedonisme dan sekularisme itu adalah masalah seksualitas.
Dengan ilustrasi singkat di atas,
sampai di sini kita dapat memiliki gambaran bahwa perempuan pesantren yang faktanya
memang banyak membaca karya-karya yang disebut sastra Islam atau sastra islami
itu, disadari atau tidak, sebenarnya tengah terlibat dalam sebuah arus
perdebatan ideologis yang sarat dengan muatan nilai dan kecenderungan
penafsiran keagamaan tertentu.
Problem yang banyak disorot atas
genre sastra Islam adalah kecenderungan penggunaan simbol yang berlebihan
sehingga ia kadang terjatuh pada pola keagamaan yang formalistik. Kalangan pendukung sastra Islam sendiri mengakui
kecenderungan semacam ini—keterjebakan pada simbol-simbol. Benny Rhamdani,
Manajer Redaksi Anak dan Remaja Mizan, menyebutkan banyaknya novel yang sekadar
mengutip ayat-ayat suci Alquran, atau penggunaan salam dan ungkapan-ungkapan
simbol Islam yang lain, sehingga label Islam hanya menjadi tempelan.12 Meskipun begitu, dari sikap Jonru
atas Laskar Pelangi tersebut di atas
tampak bahwa komposisi simbol dan substansi ini dalam karya sastra Islam dalam
pikiran komunitas pegiat sastra Islam sendiri masih menjadi wilayah yang
terbuka untuk didiskusikan.
Sampai di sini,
kita akan kembali ke titik awal, tentang bagaimana sastra Islam, sastra islami,
termasuk juga sastra pesantren, dimaknai dan diperdebatkan. Jika kita telah
membaca beberapa uraian tentang hal itu dari kelompok yang secara khusus banyak
bergiat di sastra Islam, yang diwakili oleh forum FLP, maka ada baiknya kita
juga mengemukakan suara-suara dari pesantren. Ahmad
Tohari, misalnya, mengemukakan bahwa sastra pesantren adalah “pengejawantahan ‘mâ’ dalam ayat lillâhi mâ fissamâwâti wa mâ fil ardh dan dikemas dengan kualitas
sastra yang ‘horison’ yang lalu membinarkan
kekuasan Tuhan atas ‘mâ’ di langit dan bumi”. Dalam pengertian ini, Islam muncul sebagai nilai yang universal dan melampaui simbol. Sastra pesantren harus
membawa misi “pembebasan”.13
Suara Ahmad
Tohari ini jelas menunjukkan visi yang amat terbuka tentang apa itu sastra
pesantren. Dia jelas memberi titik tekan yang substantif, bukan simbolis.
Setali tiga uang dengan Tohari, Abdurrahman Wahid dalam sebuah wawancaranya
memaparkan bahwa sastra Islam itu merupakan bagian dari
peradaban Islam. Ia memiliki watak eklektik: mampu menyerap secara terbuka hal-hal yang berasal dari kebudayaan
lain. Gus Dur menyebutkan contoh Kitabulhayawân karya al-Zais yang merupakan kumpulan fabel yang banyak mengambil unsur dari peradaban Yunani,
Romawi, India. Karena mampu menyerap, maka sastra Islam bukan hanya milik orang
Islam, tapi juga milik orang lain yang hidup dalam masyarakat Islam. Sastra
Islam menjadi bagian dari humanisme universal, karena peradaban Islam adalah peradaban yang
mampu mengayomi semua orang.14
Meski memang
masih membutuhkan pengamatan yang lebih mendalam, sampai di sini dapat
disimpulkan bahwa nilai dan muatan ideologi dalam sastra Islam maupun sastra
pesantren salah satunya sangat terkait dengan dialektika materi dan bentuk,
atau substansi dan kemasan, yang ada dalam karya-karya itu. Sementara di satu
sisi ada yang lebih menekankan pada nilai substantif yang diusung karya-karya
itu serta watak inklusif yang mendunia, di sisi lain ada yang justru memberi
tekanan yang lebih pada nilai-nilai Islam formal—dengan takaran yang masih
beragam.
Perempuan dan “Sastra Pesantren”/”Sastra Islam”
Secara lebih
khusus, kita dapat mengamati lebih dekat, bagaimana perempuan masuk dalam ruang
diskursus sastra Islam atau sastra pesantren. Pada titik awal dapat dikemukakan
bahwa perempuan dalam konteks ini menjadi stakeholder
yang cukup menarik dan penting. Jika kita melihat FLP sebagai pemain penting di
wilayah sastra Islam, maka informasi yang menjelaskan bahwa 70% anggota FLP
adalah perempuan akan dapat menjelaskan makna signifikansi perempuan dalam
sastra Islam. Jadi, tak heran bila karya-karya sastra Islam cukup banyak
bertutur tentang tema-tema perempuan. Karya semacam inilah yang banyak diapresiasi
oleh kaum perempuan
di pesantren.
Di samping itu, media-media yang serumpun dengan FLP juga banyak dikonsumsi
oleh perempuan pesantren, seperti Majalah Annida
(Helvy aktif sebagai redaktur dan pemimpin redaksi pada
1991-2001) dan Majalah Ummi, yang memang dikhususkan pada
segmen pembaca perempuan.15
Nah, dengan
proporsi partisipasi perempuan yang cukup besar di wilayah tersebut,
bagaimanakah
perempuan digambarkan dalam sastra Islam atau sastra pesantren? Yang menarik,
pengamatan selintas penulis menemukan bahwa ada nuansa yang cukup berbeda
tentang bagaimana perempuan diceritakan antara dalam sastra Islam dan sastra
pesantren. Di sini kita dapat mengangkat contoh dua novel karya Abidah
El-Khalieqy, yakni Perempuan
Berkalung Sorban (2001) dan Geni Jora
(2004).
Jika kita sepakat dengan asumsi bahwa sastra
pesantren sewajarnya menjadi bagian dari khazanah sastra Islam,
kita akan dihadapkan dengan kenyataan bahwa Geni
Jora ternyata tak disinggung secara cukup mendalam pada
pembicaraan-pembicaraan bertajuk sastra Islam.16 Ia kalah fenomenal dengan Ayat-Ayat
Cinta. Tak hanya itu, jika Kang Abik—nama akrab Habiburrahman El Shirazy,
penulis Ayat-Ayat Cinta—begitu
dikenal oleh banyak perempuan pesantren, setidaknya sejauh
pengamatan penulis di beberapa komplek pesantren, mengapa Abidah, yang jelas-jelas berlatar pendidikan pesantren, kalah populer
di dunia pesantren? Ataukah ini cukup terkait dengan fakta bahwa
basis massa pendukung sastra Islam kebanyakan berasal dari muslim kelas
menengah perkotaan, dan mereka punya media yang ampuh untuk melakukan penetrasi
ke kelompok masyarakat lainnya, termasuk perempuan di pesantren? Ataukah ini semata terkait dengan
strategi pemasaran (sosial-ekonomi), atau juga terkait dengan aspek nilai dan
ideologi?
Jelaslah bahwa sosok perempuan
yang digambarkan Abidah dalam kedua novelnya itu sungguh berbeda, bahkan
mungkin berseberangan, dengan perempuan dalam
novel-novel berlabel sastra Islam itu. Perempuan dalam karya Abidah adalah
perempuan dengan semangat pembebasan—pembebasan dari patriarki. Dalam Perempuan Berkalung Sorban, Abidah
bercerita tentang Anissa, seorang perempuan pesantren, dan ketersudutannya di
antara doktrin misoginis agama di pesantren. Sementara Geni Jora berkisah tentang Kejora yang terpasung dalam tradisi
pesantren, kultur Jawa, dan budaya Arab. Kedua karya ini dapat dibilang cukup
subversif dan, sebagaimana Maman S. Mahayana mengomentari Geni Jora di Koran Tempo,
seperti hendak menawarkan paradigma baru dalam menempatkan perempuan dalam
Islam. Citra ideal sosok muslimah dalam novel Abidah memuat semangat pembebasan—bahkan
mungkin juga perlawanan.
Bandingkanlah
gambaran perempuan semacam ini dengan perempuan dalam Ayat-Ayat Cinta atau novel berlabel sastra Islam lainnya. Salah
satu yang cukup tampak dan agak vulgar dalam novel best-seller itu adalah sikapnya terhadap poligami. Jelaslah bahwa
novel semacam Ayat-Ayat Cinta tampak
seperti tidak secara mendalam mengeksplorasi lebih jauh problem psikologis
perempuan dalam lembaga keluarga atau pernikahan atau lingkungan sosial pada
umumnya. Yang lebih banyak tergambar adalah citraan-citraan ideal—dalam hal Ayat-Ayat Cinta mungkin lebih tepat
dikatakan bahwa yang menjadi fokus adalah citra pemuda muslim ideal. Jadinya, novel semacam itu seperti kurang
mampu mengangkat realitas-realitas sosial-keagamaan di masyarakat yang masih
bermasalah—termasuk juga yang menyangkut perempuan.
Dalam masalah
poligami, pembaca Ayat-Ayat Cinta
akan cukup mudah untuk menyimpulkan bahwa alur cerita yang disajikan tampak
begitu ingin memberikan pembenaran atas pilihan tindakan Fahri untuk
berpoligami dengan menikahi Maria. Nyaris seperti sebuah rekayasa. Maria yang
sakit keras dan sekarat, yang benar-benar mengharap Fahri, dan juga Aisyah yang
begitu ikhlas. Pilihan poligami Fahri seperti menjadi satu keharusan, karena di
situ tersirat tujuan untuk menyelamatkan hidup Maria.
Ayat-Ayat Cinta—yang di sampul bukunya diberi keterangan sebagai “novel pembangun
jiwa”—bukan satu-satunya novel
berlabel sastra Islam yang bersikap demikian. Novel Asma Nadia berjudul Istana Kedua (2007) secara khusus juga
mengangkat tema masalah poligami. Alur yang dibuatnya pun nyaris tak berbeda
dengan Ayat-Ayat Cinta, yakni dalam
konteks kecenderungan untuk memberikan justifikasi atas pilihan poligami tokoh
utamanya, Pras, atas seorang perempuan bernama Mei. Mei yang mualaf, Mei yang tak
punya siapa-siapa, Mei yang memilukan, seperti ingin mengarahkan pembaca untuk
berkesimpulan bahwa kasus
poligami Pras adalah “aturan main yang ditetapkan Tuhan”, atau sebuah “takdir”. Kesimpulan ini yang cukup menguat, meski—berbeda dengan Ayat-Ayat Cinta—Asma Nadia dalam novel
ini juga mampu menghadirkan pergulatan psikologis perempuan menghadapi masalah poligami.
Bahkan, Asma menyodorkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang alasan laki-laki
berpoligami, dengan merujuk kepada teladan kehidupan Nabi.17
Dari gambaran
ini, sepertinya cukup mudah dipahami mengapa karya yang terbilang sebagai
sastra pesantren sampai sekarang masih belum sepenuhnya bisa menyatu dalam
wacana sastra Islam. Memang, batas-batas kedua kelompok ini sulit dijelaskan secara
cukup gamblang—bahwa keduanya memiliki paradigma yang
jelas berseberangan. Di lapangan,
beberapa penulis fiksi yang berasal dari pesantren tradisional bergabung dengan
komunitas
FLP. Di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep (Madura) misalnya, sejak tahun
2000 berdiri komunitas FLP yang memiliki anggota sekitar 50 orang—semuanya
perempuan. Akan tetapi, di antara anggota komunitas FLP di sana, kadang muncul
“suara lain” yang sepertinya akan terkesan aneh untuk dikatakan bahwa suara
seperti itu lahir dari anggota FLP.
Hanna
al-Ithriyah, misalnya, seorang penulis fiksi dari komunitas FLP Annuqayah,
pernah menerbitkan kumpulan cerpen berjudul My
Valentine (2006) di Penerbit Gema Insani Press. Dia menuturkan bahwa ada
salah satu cerpennya yang terelimenasi dari antologi tersebut. Cerpen yang
dimaksud berjudul “Senja di Notredame”. Cerpen itu berkisah tentang
persahabatan dua orang perempuan di Perancis yang sama-sama bergiat di
pergerakan yang memperjuangkan kebebasan untuk memakai atribut-atribut
keagamaan. Dua perempuan itu berbeda iman—salah satunya muslim. Ada nuansa
toleransi dalam persahabatan dua orang ini yang digambarkan Hanna. Menurut
Hanna, penerbit tidak memuat cerpen ini dalam kumpulan cerpennya karena
khawatir menyinggung masalah SARA.
Apakah dari kasus
ini kita dapat menambahkan bahwa nilai lain yang dibawa oleh sastra Islam
terkait dengan pemaknaan tertentu tentang makna toleransi—dan itu cukup berbeda
dengan pandangan orang semacam Tohari atau Gus Dur atau orang-orang pesantren
pada umumnya? Ini, sekali lagi, masih membutuhkan pengamatan yang lebih serius.
Perempuan Pesantren sebagai Subjek: Catatan Penutup
Dari beberapa
uraian singkat di atas, ada beberapa catatan yang penting digarisbawahi berkaitan
dengan perjumpaan perempuan pesantren dengan karya-karya sastra Indonesia
kontemporer, terutama yang berlabel sastra Islam, sastra islami, atau sastra
pesantren. Pertama, bahwa ternyata selama ini pesantren, terutama
pesantren-pesantren tradisional, kurang memberi perhatian terhadap
muatan-muatan ideologis yang terdapat dalam karya-karya fiksi semacam itu.
Padahal, dari uraian singkat di atas, tampaklah bahwa nilai-nilai dan muatan
ideologis dalam karya-karya tersebut memiliki nuansa
yang berbeda, bahkan bisa cukup bertolak belakang. Lebih
dari itu, akar komunitas pendukung utama kelompok sastra Islam relatif berbeda
dengan komunitas sastra pesantren. Apalagi jika dikaitkan dengan semacam gosip
yang menghubung-hubungkan FLP dengan Partai Keadilan Sejahtera. Meski rumor ini
ditampik secara tegas oleh orang-orang FLP, fakta yang sulit dibantah adalah
bahwa banyak anggota komunitas FLP, terutama di kota-kota besar, yang berasal
dari para aktivis dakwah kampus yang memang merupakan salah satu basis massa partai
tersebut.
Para pengelola pesantren hingga
sejauh ini tampak kurang begitu menyadari makna dan signifikansi arus
perdebatan tersebut, termasuk konteks politik kebudayaan yang mungkin menjadi
latarnya, dan menganggap bahwa itu hanyalah sekadar perdebatan antara kelompok
muslim yang mendukung moral-moral agama dan kelompok sekuler yang anti
moralitas agama. Saat berbincang
dengan beberapa alumni pesantren, terutama dari komplek perempuan, penulis
mendapatkan informasi bahwa di banyak pesantren yang muncul adalah aturan soal
larangan membaca novel-novel remaja selain yang berlabel novel islami. Semua karya berlabel sastra
islami dipandang memiliki muatan nilai yang tak berbeda dan tak memiliki
problem nilai atau ideologi tertentu.
Pada titik ini, komunitas pesantren
pada umumnya terkesan tampak sebagai konsumen yang tidak kritis. Akan tetapi, sebenarnya,
jika kita mengamati lebih mendalam, muncul hipotesis bahwa cara konsumsi
komunitas pesantren terhadap produk budaya yang seperti itu tak hanya terjadi
pada karya sastra, yakni sastra Islam, tetapi juga pada produk budaya lainnya.
Di bidang kesenian, misalnya, saat ini pesantren yang notabene kebanyakan
berbasis masyarakat tradisional mulai lebih banyak mengadopsi atau mengadaptasi
kesenian yang berbasis masyarakat perkotaan. Jika kesenian lokal pada umumnya kadang
diberi label-label yang kurang baik (secara keagamaan), maka komunitas
pesantren terkesan lebih mudah menoleransi kesenian baru dari kota—semacam
lagu-lagu nasyid, misalnya. Hal serupa juga tampak dalam cara komunitas
pesantren mengonsumsi kebutuhan sehari-hari, model pakaian, dan juga “idola”. Apakah
ini berarti komunitas pesantren larut dalam budaya massa, atau, katakanlah,
kultur monolitik peradaban modern?
Dalam wilayah
yang lebih luas, pembicaraan mengenai kaum perempuan
dan sastra Islam dapat mengantarkan pada agenda penguatan orang-orang pesantren untuk bermain lebih aktif dalam
dunia kesusastraan. Pesantren juga harus menjadi subjek penting dalam
menyuarakan karakter kultural dan pandangan dunia kesusastraannya. Pesantren memberikan warna baru yang berbeda dalam dunia
kesusastraan Indonesia dengan karya-karya yang lebih mengakar.
Jamal D. Rahman
dalam salah satu tulisannya memaparkan tentang salah satu aspek penting dari
karakter sastra pada umumnya dalam kaitannya dengan pesantren. Bahwa sastra itu membebaskan manusia dari kejumudan dan kecupetan
perasaan, mempertajam kepekaan hati dan perasaan, dan sebagainya, yang
kesemuanya itu—dalam kaitannya dengan penghayatan keagamaan—dapat mengontrol kecenderungan
destruktif, yang mungkin muncul dari amarah akibat perasaan tertekan, psikologi
kekalahan, dan ketakberdayaan menghadapi hal yang sangat tak diinginkan.18
Ekspresi teduh dan sejuk dari model penghayatan keagamaan semacam inilah yang
penting untuk dipromosikan oleh karya sastra pesantren.
Sampai saat ini,
harus diakui bahwa orang-orang di pesantren, termasuk juga kaum perempuan
pesantren, masih belum bisa menjadi subjek yang signifikan dalam sastra Islam
dan kesusastraan pada umumnya. Selain mungkin faktor yang bisa terkait dengan
politik kebudayaan, harus diakui bahwa secara intrinsik karya-karya sastra dari
pesantren masih belum cukup mampu untuk menggambarkan realitas dan pengalaman
yang unik dan sangat kaya di dunia pesantren—termasuk, secara khusus, dunia
perempuan. Salah seorang kritikus sastra, Faruk HT, mencatat bahwa sastra
pesantren yang ada cenderung “menampilkan dunia pesantren sebagai latar, tanpa deskripsi
yang rinci dan hidup, dan menjelmakan nilai keislaman secara formalistik serupa
khotbah. Selain itu, juga cenderung minim realitas kejiwaan dan teknik
berceritanya konvensionil. Akibatnya, dunia santri dan pesantren dalam karya
sastra hadir tak utuh dan tanpa gema.”19
Kita belum
menemukan suara yang khas pesantren, yang dapat memberikan gambaran subtil
kehidupan pesantren yang khas, dengan nilai-nilai seperti yang digambarkan oleh
Jamal D. Rahman di atas—Islam yang sejuk dan damai. Kita masih menunggu karya-karya semacam itu.
Karya yang, baik dari kemasan maupun substansi, mirip karya-karya Orhan Pamuk yang mampu memberikan gambaran
muram kehidupan di Turki, atau misalnya Istambul secara khusus, di tengah
peralihan sosio-kultural masyarakatnya. Jika masyarakat dunia menjadi lebih
kenal dengan Turki melalui karya-karya Pamuk, maka orang-orang pesantren
mestinya menjadi orang pertama yang paling berhak dan
paling tepat memperkenalkan kehidupan
dan nilai-nilai pesantren kepada dunia.
Secara khusus,
bagi perempuan proyek kebudayaan semacam ini memberi peluang kepada mereka untuk
dapat terlibat secara lebih intens dengan dunia luar, baik itu dalam konteks
pengembangan literasi atau kontribusi sosio-kultural yang lain—tak hanya
menjadi objek yang mengonsumsi produk budaya lainnya.
Wallahualam.
Catatan:
1.
Di antaranya seperti yang terdokumentasikan dalam
penelitian yang dikoordinasikan oleh PPIM IAIN Jakarta, yakni dalam Jajat
Burhanuddin (ed.), Ulama Perempuan Indonesia,
Gramedia, Jakarta, 2002.
2.
M. Faizi, “Silsilah Intelektualisme dan Sastra di
Pesantren”, Jurnal ‘Anil Islam, LP2M
STIK Annuqayah Sumenep, Nomor 1, Volume 1, 2008, hlm. 115-118.
3.
Lihat, Annemarie Schimmel, Dan Muhammad adalah Utusan Allah: Penghormatan terhadap Nabi saw. dalam
Islam, penerjemah: Rahmani Astuti dan Ilyas Hasan, Mizan, Bandung, Cet.
VIII, September 2001, hlm. 239-287.
4.
Tulisan Jamal D. Rahman dalam weblog pribadinya
berjudul “Sastra, Pesantren, dan Radikalisme Islam”, URL: http://jamaldrahman.wordpress.com/2008/10/25/sastra-pesantren-dan-radikalisme-islam/,
diakses pada 30 November 2008.
5.
Efri Ritonga, “Sastra yang Menuju Tuhan”, Suplemen Ruang
Baca Koran Tempo, 28 April 2008, URL:
http://www.ruangbaca.com/ruangbaca/?doky=MjAwOA==&dokm=MDQ=&dokd=Mjg=&dig=YXJjaGl2ZXM=&on=Q1JT&uniq=Njcw,
diakses pada 30 November 2008.
6.
Muhidin M. Dahlan, “Mengapa ‘Kita’ Menolak Sastra
(Berlabel) Islam”, URL: http://akubuku.blogspot.com/2007/04/mengapa-kita-menolak-sastra-berlabel.html,
diakses pada 30 November 2008.
7.
Paparan tentang tren sastra Islam ini diulas cukup
panjang di Suplemen Ruang Baca Koran
Tempo, 28 April 2008. Dapat diakses di www.ruangbaca.com.
8.
Muhidin M. Dahlan, Op.
Cit..
9.
Tulisan selengkapnya dapat diakses di URL http://www.jonru.net/beginilah-cara-koran-tempo-menyerang-sastra-islam.
Perdebatan yang lain tentang sastra Islam ini juga dapat dibaca dalam polemik
Kurniasih dengan Topik Mulyana, pegiat FLP Bandung, di Harian Pikiran Rakyat. Kurniasih menulis di Pikiran Rakyat 3 November 2007 berjudul
“Wajah Sastra Islam”, yang kemudian ditanggapi oleh Topik Mulyana pada 15
Desember 2007 di harian yang sama dalam tulisan berjudul “FLP, Sastra Islam,
dan Seni Tinggi”. Polemik ini berlanjut hingga awal 2008. Arsip-arsip polemik ini dapat diakses di www.cabiklunik.blogspot.com.
10. Milis pasarbuku, pesan
#50160. URL: http://groups.yahoo.com/group/pasarbuku/message/50160.
11. Topik Mulyana, “FLP,
Sastra Islam, dan Seni Tinggi”, Harian Pikiran
Rakyat, 15 Desember 2007.
12. Suplemen
Ruang Baca Koran Tempo, 28 April
2008. Sakti Wibowo, seorang pegiat sastra Islam, juga berbicara tentang hal
yang serupa. Lihat http://www.wedangjae.com/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=40.
13. Sebagaimana
dijelaskan oleh M. Faizi, Op. Cit.,
hlm. 132. Jika kita
mengamati karya-karya Ahmad Tohari, nyaris tak ditemukan yang secara eksplisit
berlatar pesantren. Yang lebih terlihat justru memang aspek nilai dan
substansinya.
14. M. Saleh Isre (ed.), Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak
Minoritas, Reformasi Kultural, LKiS, Yogyakarta, Cet. II, Agustus 1998, hlm. 129-134.
15. Dari beberapa
informan, penulis mendapatkan data bahwa Majalah Annida yang beredar di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep setiap
edisinya bisa mencapai sekitar 40-50 eksemplar. Jumlah ini belakangan cenderung
menurun karena harga jualnya yang kurang dapat dijangkau oleh santri yang
kebanyakan berasal dari lapisan kelas menengah ke bawah. Sementara itu, Majalah
Ummi di Annuqayah lebih sedikit
diminati daripada Annida. Informasi tentang popularitas Annida di lingkungan komplek pesantren
perempuan lainnya juga penulis temukan.
16. Lebih jauh,
baca Maman S. Mahayana, “Fenomena Novel Islami”, dalam Suplemen Ruang Baca Koran Tempo, 28 April 2008.
17. Lihat, M.
Mushthafa, “Asma Nadia dan Dilema Poligami”, resensi novel Istana Kedua di Harian Sinar
Harapan, Sabtu, 15 November 2008. Yang cukup menarik, dalam buku yang lain
berjudul Catatan Hati Seorang Istri
(2007), Asma Nadia juga mampu memotret kehidupan sehari-hari perempuan dan
bahkan mengangkat suara perempuan dalam kaitannya dengan poligami dan masalah
keluarga yang lain. Meski begitu, pembaca tetap dapat memahami dan membaca secara implisit
“batas-batas wacana” yang hendak ditegaskan Asma dalam masalah poligami dalam kedua karyanya ini. Ulasan atas Catatan Hati Seorang Istri ditulis oleh
M. Mushthafa, “Asma Nadia tentang Poligami dan Perselingkuhan”, Jurnal
Perempuan, No. 56, November
2007, hlm. 143-146.
Secara khusus, Harian Jawa Pos pernah menurunkan tulisan menarik tentang novel Ayat-Ayat Cinta kaitannya dengan
keberpihakannya pada perempuan. Yaitu, tulisan Khotimatul Husna, “Ayat-Ayat Cinta: Pro atau
Anti-Perempuan?” (Jawa Pos, 20 April
2008), dan Beni Setia, “Patriarki Islam dalam Ayat-Ayat Cinta” (Jawa Pos,
27 April 2008).
18. Jamal D.
Rahman, Op. Cit..
19. Sebagaimana
dipaparkan oleh Binhad Nurrohmat, “Gincu Merah Sastra Pesantren”, Harian Suara Karya, 24 Maret 2007, diakses dari
URL: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=169288 pada 30 November 2008.
Tulisan ini dimuat di Jurnal Srinthil Nomor 17/2009.










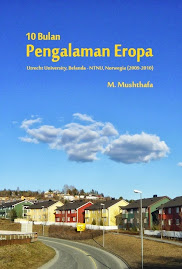




0 komentar:
Posting Komentar