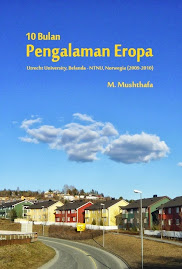Pagi ini, Sapardi kembali datang mengetuk pintu kamarku, menyelipkan larik-larik puisinya di antara isi tas ransel yang siap kubawa ke kantor. Di luar rintik belum reda. Biru langit bertumpuk awan. Kabut semalam belum pupus. Kalut masih menggayut. Kabut, kalut, masih tak sanggup kulawan dengan hanya berbekal selimut yang sudah terasa usang.
Hari ini aku hanya sempat mencatatkan ketakberdayaan, meski mungkin sebenarnya itu adalah sebentuk kekuatan. Biarlah, hanya hening yang mengetahui maknanya, karena kupikir dalam bilik hati yang hening, ketulusan dan kejujuran lebih menemukan tempatnya yang lapang. Karena terkadang di suatu perempatan, diam-diam ada yang dipertemukan.
Bapak Sapardi, kapankah puisi yang lain akan diantarkan buatku?
PADA SUATU PAGI HARI
Maka pada suatu pagi hari ia ingin sekali menangis
sambil berjalan tunduk sepanjang lorong itu. Ia ingin pagi itu
hujan turun rintik-rintik dan lorong sepi agar ia bisa berjalan
sendiri saja sambil menangis dan tak ada orang bertanya
kenapa.
Ia tidak ingin menjerit-jerit berteriak-teriak mengamuk
memecahkan cermin membakar tempat tidur. Ia hanya ingin
menangis lirih saja sambil berjalan sendiri dalam hujan rintik-
rintik di lorong sepi pada suatu pagi.
(1973)
(Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni, Jakarta: Gramedia, Cet. II, 2003, hlm. 66)
Kamis, 23 Desember 2004
Sapardi, Suatu Pagi
Label: Diary
Senin, 18 Oktober 2004
Sketsa Kaum Muda NU
Judul buku : NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru
Penulis : Laode Ida
Pengantar : Martin van Bruinessen
Penerbit : Erlangga, Jakarta
Cetakan : Pertama, 2004
Tebal : xviii + 248 halaman
Dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang pemikiran yang menyatakan bahwa dikotomi modernis dan tradisionalis sudah tak lagi relevan digunakan dalam konteks komunitas Islam Indonesia, terutama bila dirujukkan pada dua organisasi besar kaum muslim, NU dan Muhammadiyah. NU, kaum sarungan yang selama ini dipandang mewakili kelompok tradisional, belakangan ternyata memperlihatkan suatu gerak metamorfosis yang tidak saja terjadi dalam level epistemologis, tapi juga dalam konteks orientasi. Mitos tradisional kalangan NU pelan-pelan terpatahkan oleh berbagai fenomena yang kian hari kian menarik itu.
Buku ini berusaha mencermati gugus-gugus komunitas yang oleh penulisnya, Laode Ida, disebut “Kelompok NU Progresif”, dalam menggalang perubahan di tubuh NU dan berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya. Di bagian awal, Laode menggambarkan bagaimana sebenarnya dalam kultur NU perubahan itu cukup sulit dilakukan. Laode misalnya memaparkan tiga segi basis komunitas NU, yakni pesantren, yang pada tingkat tertentu cukup menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Ketiga hal itu adalah otonomi kiai yang menjadi sumber legitimasi kaum pesantren dengan berbagai perangkat sosial yang semakin mendukung tingkat otoritasnya, stratifikasi dalam struktur kiai NU yang tidak hanya ditentukan posisi dan peran sosialnya di masyarakat tapi juga oleh faktor genealogis, dan ajaran-ajaran yang dikembangkan dan seringkali dipertahankan sebagai dogma. Selain itu, karena secara historis kemunculan NU sebagai sebuah organisasi cukup bercorak reaktif-defensif—lahir sebagai reaksi terhadap eksistensi kaum pembaharu yang mendirikan organisasi Muhammadiyah—maka secara teoritik ia menjadi kurang memungkinkan menerima agenda-agenda perubahan.
Namun demikian, dengan berbagai kondisi internal yang sedemikian rupa, ternyata anak-anak muda NU terbukti telah melakukan kiprah perubahan, baik ke arah internal maupun eksternal. Tentu saja ada sejumlah latar historis yang memungkinkan terjadinya perubahan tersebut. Dalam buku ini Laode mencatat ada empat hal yang menjadi konteks historis struktural bagi munculnya kelompok NU Progresif. Pertama, dinamika internal dan benturan tradisi yang muncul di tubuh NU sendiri, ketika di satu sisi muncul kelompok-kelompok NU yang memasuki wilayah gerakan yang sebelumnya belum pernah disentuh, yakni gerakan yang cenderung aktif dalam partisipasi sosial yang searah dengan proyek pembangunan Negara melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat, sementara di sisi yang lain muncul kritik terhadap realitas internal NU yang kurang responsif menyikapi kebutuhan dan tuntutan sosial yang saat itu terhitung baru. Kedua, tuntutan modernisasi untuk semakin memapankan pola manajerial intern NU sehingga berbagai sumber daya yang dimilikinya dapat berfungsi efektif dan maksimal.
Latar ketiga yang oleh Laode diuraikan dengan lebih panjang ketimbang latar historis lainnya adalah terjadinya kerisauan—terutama—kalangan muda NU terhadap perjalanan politik NU. Memang harus diakui bahwa kelompok mana pun mesti dan perlu bersentuhan dengan proses politik di level negara. Akan tetapi, secara intern, muncul kecenderungan bahwa keterlibatan NU dalam politik justru membuat program pengembangan masyarakat yang diembannya melalui pesantren menjadi stagnan. Sementara di satu sisi perhatian mereka pada dunia pesantren menjadi sangat terabaikan, di sisi yang lain sumber daya NU di dunia politik kadang mengalami kesulitan untuk memainkan perannya secara cantik, karena faktor pendidikan yang hanya terbatas di bidang keagamaan. Akibatnya, efektivitas keterlibatan NU di ranah politik menjadi dipertanyakan.
Belum lagi jika kalangan elit NU yang terjun di wilayah politik itu mengeksploitasi hak-hak politik warga NU, dengan terus memanfaatkan “kebodohan” massa NU yang masih terjebak dalam sistem budaya sosial patron-klien. Variabel kepentingan politis ini juga berlaku ketika pada titik tertentu tokoh-tokoh politik NU dimanfaatkan oleh Negara untuk menjadi semacam alat legitimasi bagi kebijakan-kebijakan Negara yang pada era Orde Baru sering bercorak represif dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini kemudian menjadikan independensi NU dari elemen-elemen kekuasaan (Negara) menjadi menghadapi tantangan besar.
Latar keempat yang menjadi titik tolak lahirnya kelompok NU Progresif adalah perkembangan gerakan HAM dan demokrasi di Indonesia. Merebaknya isu-isu HAM dan demokratisasi secara tak terelakkan juga diapresiasi oleh kelompok-kelompok muda NU. Untuk hal-hal tertentu sebenarnya isu HAM sudah merupakan bagian dari agenda-agenda kerakyatan NU, tapi dalam konteks atmosfer politik Orde Baru, persoalan ini menjadi semakin meluas ke level politik nasional.
Inilah yang oleh Laode kemudian dikatakan bahwa pola gerakan perubahan yang dilancarkan kaum NU progresif ini tidak saja bersifat sentripetal, yaitu dilakukan di basis komunitas NU itu sendiri dengan pelan-pelan masuk ke jajaran struktural NU, tapi juga bersifat sentrifugal, ketika kelompok NU progresif ini berupaya memengaruhi ke luar NU dengan pemikiran dan gerakan demokratisasi dan HAM melalui jaringan sosial yang dirajutnya. Kelompok inilah yang oleh Laode tipologinya disebut progresif-radikal dalam peta kelompok NU progresif. Laode mengidentifikasi bahwa kelompok ini diperankan oleh kelompok muda NU yang kritis terhadap kemapanan yang umumnya berbasis di perkotaan. Pemikiran dan kegiatan mereka dipandang radikal, bahkan kekiri-kirian. Gerakan mereka bisa berbentuk penyebaran pemikiran kritis maupun aliansi strategis lintas komunitas untuk mendorong perubahan yang lebih bersifat struktural dalam konteks sosial dan kenegaraan. Untuk kelompok ini Laode menyebut contoh kaum muda NU yang tergabung dalam Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta dan aktivis pergerakan yang tergabung di FORKOT dan FAMRED Jakarta.
Selain kelompok progresif-radikal ini, terdapat kelompok yang masuk dalam tipologi progresif-transformis, yaitu tokoh-tokoh muda NU yang secara intern mengupayakan penyadaran terhadap orang-orang NU sendiri dengan harapan mereka ini yang kelak akan dapat mengubah dirinya dan melakukan perubahan untuk lingkup komunitas yang lebih luas. Kelompok ini lebih banyak berkonsentrasi pada agenda-agenda internal NU dengan melakukan pembenahan pola manajerial dan pengembangan sumber daya manusia. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU yang pertama kali didirikan di Jakarta pada 1983 dan kemudian diikuti di daerah-daerah menjadi salah satu pusat kelompok transformis ini dalam menggarap komunitas NU untuk bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.
Selain kedua tipologi radikal dan transformis tersebut, terdapat juga tipologi progresif-moderat, yaitu mereka yang memiliki ide-ide perubahan tapi tidak memiliki basis ideologi yang jelas yang secara konsisten bisa diperjuangkan. Berbeda dengan kelompok transformis yang cenderung persuasif dan kelompok radikal yang acap kali cenderung frontal, kelompok moderat ini cukup kooperatif baik dengan kekuatan intern NU maupun dengan kekuatan di luar NU.
Ketiga tipologi ini pada dasarnya tidak bersifat kaku dan dapat dipisahkan secara tegas. Dalam interaksinya pun terjadi tumpang tindih, dan secara operasional ketiga tipologi ini dapat dilihat lebih sebagai sub komunitas NU yang berangkat dari titik ideologi liberalisme yang mengupayakan revitalisasi tradisi sekaligus penemuan kembali jati diri dan kepribadian NU.
Berbagai sub komunitas ini mulai muncul dan berkiprah sejak tahun 1970-an dan hingga kini terus semakin subur seiring dengan arus perubahan politik Indonesia. Di awal kemunculannya, kelompok NU progresif ini banyak mempersoalkan kiprah NU dalam politik. Bagi kelompok NU progresif ini, gerakan politik Islam formal yang didukung oleh sejumlah politisi NU mengandung bahaya yang sangat mendasar, yaitu ketergantungan kejayaan Islam yang sangat kuat pada situasi politik formal-struktural, dan dapat mencengkeramkan benih eksklusivisme di kalangan umat.
Dari sinilah kemudian terlihat bahwa salah satu arah perubahan yang diupayakan kelompok NU progresif ini adalah dari eksklusivisme ke inklusivisme. Mereka meneguhkan kembali nilai dan sikap tasamuh, menekankan bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta, menghargai komunitas lain, dan mendudukkan persoalan-persoalan sosial dalam bingkai kemanusiaan. Ideologi negara, yaitu Pancasila, dipandang sebagai wadah yang cukup representatif untuk konteks pluralitas masyarakat Indonesia.
Dalam tataran internal, kelompok NU progresif ini juga mencoba membongkar kejumudan berpikir masyarakat NU untuk dicerahkan dan diberdayakan. Bentuk-bentuknya bisa berupa mendorong kemandirian berpolitik warga NU yang sebelumnya sering dikooptasi oleh politisi elit NU sendiri, atau menghidupkan pikiran-pikiran kritis dan tradisi dialog. Selain arah perubahan semacam ini, juga diupayakan langkah-langkah untuk memperkuat tradisi demokrasi dan pembebasan dalam tubuh NU, terutama saat berhadapan dengan elemen-elemen kekuasaan Negara.
Berbagai aksi kelompok muda NU ditanggapi secara beragam oleh masyarakat NU pada umumnya. Ada yang terpengaruh sekaligus memberikan dukungan, ada yang bercorak defensif dan mencap bahwa beberapa perubahan yang dilakukan sudah keluar dari jalur tradisi, dan ada yang bersikap netral dan cukup akomodatif terhadap dua corak respons tersebut.
Pada saat kebebasan politik dan euforia menjadi ciri utama Orde Reformasi, berbagai elemen dari kelompok NU progresif ini seperti menghadapi situasi yang kembali sulit dan membingungkan. Sementara di awal pergerakannya mereka begitu mencurigai politik formal struktural sebagai suatu ancaman bagi ruh demokrasi dan masyarakat sipil, Orde Reformasi menawarkan sebuah ruang politis yang cukup terbuka untuk melakukan aksi yang cukup berbeda dengan yang telah diambil sebelumnya, sehingga NU sendiri akhirnya memutuskan untuk membentuk partai, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tak terelakkan, respons yang muncul pun dari kalangan muda ini cukup beragam, baik yang pada akhirnya turut bergabung di jalur politis, tetap mengambil jalur perjuangan seperti yang dipilih sebelumnya, atau melontarkan pikiran-pikiran kritis terhadap kalangan internal NU sendiri.
Buku ini memang tidak mengulas secara mendalam situasi dan perkembangan terkini yang dalam konteks politis dan dari sudut kepentingan NU saat ini memperlihatkan interaksi dan dinamika yang semakin menarik. Majunya Ketua PBNU, KH Hasyim Muzadi sebagai cawapres yang dipasangkan dengan Megawati, dukungan PKB pada pasangan Wiranto-Shalahuddin Wahid, dan, yang paling mutakhir, manuver sejumlah kaum muda NU dalam menyelenggarakan Musyawarah Besar Warga NU di Cirebon di bulan Oktober yang lalu, memperlihatkan bahwa tarik menarik antara elemen-elemen progresif yang bersikap kritis terhadap posisi politis NU terus terjadi—malah mungkin cenderung semakin menguat. Dalam konteks paradigmatis, ini membuat perdebatan menyangkut pemaknaan Khittah 1926 NU terus terbuka dan dilangsungkan.
Seperti yang ditulis dalam kerangka acuan yang dibuat dalam acara Mubes Warga NU di Cirebon tersebut, sejumlah kalangan muda NU tersebut memandang bahwa telah terjadi degradasi makna dan tujuan NU, ketika elit-elit NU menjadikan organisasi tersebut sebagai kendaraan politik berjangka pendek sehingga “memperlemah keberdayaan dirinya, yang kemudian berdampak pada memudarnya eksistensi keulamaan dan NU di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan.”
Pemaknaan-pemaknaan yang berbeda dalam membaca sebuah pilihan langkah “politis” tertentu dan respons warga NU pada umumnya sepertinya akan terus menjadi faktor kunci dalam menentukan bagaimana arah perubahan yang akan terjadi dalam tubuh NU itu sendiri. Tentu saja faktor eksternal yang saat ini juga memperlihatkan arah perkembangan yang dinamis dan kadang mengejutkan akan juga menjadi faktor yang menentukan. Yang jelas, dinamika internal yang begitu kaya ini pada satu sisi sebenarnya dapat menjadi sebuah modal yang besar bagi langkah NU ke depan, asalkan semua warga NU dapat menyikapinya dengan arif dan terbuka.
Meski tidak secara spesifik membicarakan persoalan relasi NU dan dunia politik, buku yang semula merupakan disertasi di jurusan Sosiologi Universitas Indonesia ini memberikan data dan analisis yang cukup berharga bagi warga NU, terutama untuk menjadi bahan diskusi bagi perbincangan tentang bagaimana sebaiknya mendudukkan elemen sayap politik di tubuh NU itu sendiri dalam hubungannya dengan cita-cita dan tujuan NU itu sendiri. Memang, pemaparan dan pemetaan yang disajikan Laode Ida atas peta pergerakan kelompok NU progresif masih bersifat umum. Karena itu, dalam konteks otonomi daerah dan semakin dinamisnya kaum muda NU di daerah-daerah, cukup menarik kiranya jika selanjutnya dicermati bagaimana proses interaksi dan tarik-menarik itu terjadi di daerah.
Tulisan ini dimuat di Jurnal Tashwirul Afkar Edisi 17/2004.
Minggu, 05 September 2004
Reposisi Agenda Sayap Politik NU
Keputusan Mukernas PKB baru-baru ini untuk bersikap netral dalam pemilihan presiden putaran kedua menarik untuk dicermati, terutama dalam konteks masa depan politik masyarakat NU. Pilihan untuk netral ini di satu sisi sepertinya merupakan hasil dari refleksi para elit PKB sendiri atas mulai melemahnya kontrol para elit partai terhadap keragaman pendapat
Jika salah satu landasan berpikir elit PKB dalam memutuskan sikap netral pada pilpres putaran kedua memang demikian adanya, dari satu sisi ini sebenarnya akan cukup memberi ruang yang lebih besar bagi proses demokratisasi dan penguatan daya tawar masyarakat vis-à-vis para elit partai. Artinya, ke depan nanti para pengurus atau pemegang otoritas dalam partai politik harus berpikir lebih kreatif dan cerdas untuk menarik simpati massanya, tidak cukup hanya dengan memanfaatkan instruksi partai, preferensi subjektif, ketokohan, atau kedekatan emosional saja. Perkembangan internal komunitas NU belakangan menunjukkan semakin kayanya perspektif, terutama di lapis kaum muda NU, yang mengarah pada semakin dibutuhkannya pendekatan-pendekatan yang bersifat objektif-rasional dalam bergaul dengan komunitas NU itu sendiri.
Adapun persoalan yang menarik untuk dicermati dalam konteks PKB adalah, sejauh mana pilihan sikap PKB untuk bersikap netral dalam pilpres putaran kedua tersebut memberi warna dan memengaruhi arah politik masyarakat NU pada umumnya. Kecenderungan pertama yang menarik untuk disorot, yang lebih bersifat temporer dan berjangka pendek, adalah mulai ramainya arus-arus dukungan dari berbagai elemen NU kepada salah satu pasangan capres. Beberapa DPW PKB misalnya menyatakan dukungan kepada pasangan Megawati-Hasyim, beberapa kepada pasangan SBY-Kalla.
Sejauh ini memang aksi dukung-mendukung itu belum memperlihatkan tingkat konflik internal yang cukup mengganggu. Kenyataan ini dapat cukup dimaklumi karena sebenarnya warga NU sendiri selama ini memang telah menyebar ke berbagai kekuatan politik di luar PKB. Selain itu, elemen-elemen NU juga memiliki tingkat independensi yang bersifat relatif kuat, sehingga ketika ada satu kelompok yang menyatakan dukungan untuk pasangan tertentu, relatif cukup sulit kiranya untuk mengintervensi keputusan dukungan pihak yang lainnya.
Perbedaan pilihan dukungan politik untuk pemilu presiden memang sudah terlihat pada pemilu presiden putaran pertama, dan memang terbukti tidak cukup melahirkan konflik yang berarti di kalangan NU.
Hal kedua yang menarik dicermati adalah pola relasi antara komunitas NU pada umumnya dengan PKB, sebagai organ politik resmi NU. Sebagaimana diketahui, PKB adalah partai politik yang kelahirannya secara resmi dibidani oleh para elit NU untuk menjadi saluran politik dan untuk mengakomodasi aspirasi politik warga NU. Dari perspektif yang lain, lahirnya PKB juga berarti bahwa para elit NU sebenarnya bermaksud untuk “melokalisasi” sayap politik warga NU ke dalam PKB, sehingga agenda-agenda pemberdayaan masyarakat sipil yang selama ini telah dikerjakan NU sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan dapat terus berlanjut tanpa harus terpecah fokusnya pada soal-soal politik kekuasaan.
Realitas yang menunjukkan adanya keragaman aspirasi politik dalam tubuh NU, seperti diulas tadi memang tidak terlalu menimbulkan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kader-kader NU yang aktif di organisasi NU (NU struktural) itu sendiri juga ikut terjun dalam kancah politik praktis, utamanya dalam ajang pemilu presiden.
Bagaimanapun juga harus diakui bahwa kasus-kasus semacam ini di beberapa daerah berbasis NU seperti di Jawa Timur betul-betul terjadi, dan pada satu titik tertentu akan dapat menghasilkan hal-hal yang kontraproduktif bagi NU itu sendiri. Pada pilpres putaran pertama yang lalu, misalnya, ketika secara resmi PKB menyerukan untuk memilih pasangan pilpres Wiranto-Shalahuddin Wahid, di beberapa daerah terjadi fenomena pengurus-pengurus NU (NU struktural) yang malah menjadi tim sukses pasangan pilpres yang lain. Dalam konteks proses demokrasi yang menjunjung kebebasan hak-hak politik warga negara, itu sah-sah saja dilakukan. Tak salah jika dikatakan bahwa setiap warga negara, termasuk yang aktif sebagai pengurus NU, punya hak politik yang dapat disalurkan ke mana saja.
Tapi pertanyaannya adalah, apakah pilihan untuk secara terbuka masuk ke dalam blok-blok politik tertentu dalam konteks perebutan kursi kekuasaan akan memberikan efek yang baik kepada agenda-agenda NU sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan? Ataukah justru itu akan membuat NU menjadi semacam kekuatan politik tandingan bagi PKB yang pada tingkat tertentu dapat memicu konflik internal di kalangan NU dalam konteks perebutan kekuasaan? Bila ini yang terjadi, ada kemungkinan bahwa institusi NU akan lebih berfungsi sebagai kendaraan politik atau batu loncatan untuk kepentingan kekuasaan tertentu, dan menelantarkan agenda-agenda pemberdayaan masyarakat yang sejatinya menjadi concern utamanya. Dalam konteks otonomi daerah, kecenderungan semacam ini dapat semakin marak terjadi mengingat besarnya tingkat otonomi relatif kelompok-kelompok NU di daerah.
Dari dua hal tersebut di atas, terlihat bahwa sebenarnya pilihan politik PKB untuk bersikap netral pada pilpres putaran kedua merupakan suatu pilihan yang terbaik untuk masyarakat NU pada umumnya, karena dengan begitu, keragaman aspirasi politik warga NU dapat tersalurkan. Namun demikian, ada satu agenda besar yang harus segera dituntaskan oleh warga NU ke depan, yakni menyangkut pola relasi antara PKB sebagai sayap politik NU yang bekerja dalam kerangka agenda politik kekuasaan, dan institusi NU yang lebih bergerak pada agenda-agenda peradaban.
Memang harus diakui bahwa semenjak reformasi digulirkan, kekuasaan menjadi semacam titik perhatian yang diperebutkan banyak elemen-elemen politik bangsa ini, setelah gumpalan kekuasaan yang memusat pada rezim Orde Baru meledak dan menyebar tak menentu. Realitas semacam ini sebenarnya terjadi karena cara pandang masyarakat kita terhadap kekuasaan cenderung berdasar pada paradigma modernisme (Marxian dan Weberian), yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang terlokalisasi dan terpusat, yakni terutama pada negara. Padahal, jika kita mau mencermati pemikiran seorang filsuf Prancis, Michel Foucault (1926-1984), terungkap bahwa kekuasaan itu sebenarnya bersifat menyebar dan bergerak secara dinamis.
Ini berarti bahwa dengan bekerja pada wilayah-wilayah yang bisa disebut mikro-politik, pada titik tertentu NU sebenarnya dapat menjadi suatu kekuatan “politik” yang layak diperhitungkan berhadapan dengan berbagai kekuatan di area makro-politik. Tentu bergerak dalam wilayah mikro-politik tidak menjanjikan kursi kekuasaan yang memang menggiurkan itu, tapi itu akan menjadi sebuah investasi kekuatan politik masa depan yang amat berharga nilainya.
Berbagai sumber daya yang dimiliki NU sampai saat ini telah cukup kaya, beragam, dan cukup memiliki akar di masyarakat bawah. Jika semua elemen dan sumber daya NU tersebut terjebak ke dalam ajang politik kekuasaan, maka mungkin saja energi produktif NU akan terkuras habis, dan NU kemudian pelan-pelan meninggalkan kerja-kerja pemberdayaan yang sebenarnya lebih bersentuhan dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Label: Social-Politics
Selasa, 17 Agustus 2004
Kemerdekaan dan Kebersamaan
Perjalanan bangsa Indonesia setelah memasuki gerbang kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 hingga saat ini telah menapaki tahun yang ke-59. Untuk seorang manusia angka itu menunjukkan sesuatu yang sudah cukup lama, tetapi untuk sebuah bangsa angka itu mungkin ibarat beberapa tapak jejak dalam sebuah rentang perjalanan yang entah akan berakhir kapan. Tentu saja bangsa ini mengalami pasang-surut perjalanannya, terutama bila dilihat dari sisi kemerdekaan itu sendiri. Hengkangnya kaum penjajah di tahun 1945 baru merupakan pintu gerbang. Tapi selanjutnya, di saat-saat tertentu bangsa ini tersadar bahwa ternyata rintangan untuk terpenuhinya kemerdekaan yang sesungguhnya kadang masih kerap dijumpai dalam suasana yang bebas dari kaum penjajah asing.
Dalam sebuah tulisannya di Jurnal Prisma edisi Agustus 1985, Adnan Buyung Nasution mencatat bahwa esensi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah cita-cita luhur para pendiri bangsa ‘untuk memperjuangkan suatu derajat, kedudukan, martabat yang sama dengan manusia lainnya di seluruh dunia’, yang berarti ‘suatu perjuangan membela harkat dan martabat kemanusiaan, atau dengan kata umum, perjuangan hak asasi manusia.’ Kutipan ini sepertinya cukup bisa menjadi panduan untuk menilai apakah bangsa ini memang sudah benar-benar merdeka.
Tentu kita tidak boleh merasa kecewa bila yang didapat ternyata adalah jawaban negatif: bahwa masih banyak segi-segi hak kemanusiaan kita yang tercederai. Hak untuk mendapat pendidikan terbentur dengan gejala kapitalisasi pendidikan yang membuat rakyat miskin tidak terdidik dengan baik. Hak untuk mendapat penghidupan yang layak berhadapan dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan yang mempersempit peluang perbaikan taraf kehidupan. Hak-hak politik rakyat juga menghadapi kesulitan karena para pemimpin dan partai politik lebih suka memanfaatkan rakyat dan tidak terlalu mendengar aspirasi mereka. Belum lagi rasa aman yang cukup sering terteror dengan peristiwa pengeboman yang membuat rakyat tidak tenang dan kadang menciptakan suasana yang tidak menentu.
Apa yang hilang dari terlanggarnya hak-hak kemanusiaan warga negara ini dari sudut pandang historis juga menunjukkan runtuhnya rasa kebersamaan yang sesungguhnya menjadi ciri dan modal perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Dengan merujuk pada tulisan Adnan Buyung tersebut di atas, ditunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, terutama menjelang proklamasi Agustus 1945, melibatkan para pemimpin nasional seperti Soekarno, Hatta, Soepomo, A.A. Maramis, Soebardjo, dan yang lain, yang berjuang melalui sistem, dengan berkolaborasi dengan Jepang yang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tapi ada pula gerakan-gerakan rakyat yang dipimpin oleh Sjahrir, Soekarni, Chairul Saleh, Adam Malik, dan sebagainya yang juga berjuang untuk kemerdekaan.
Fakta sejarah menunjukkan bahwa dalam perjuangan yang betul-betul habis-habisan itu kebersamaan dan visi yang terbuka menjadi kekuatan tersendiri yang mampu mengatasi segala keterbatasan yang dimiliki saat itu. Pada akhirnya kemerdekaan justru didapat oleh gerakan rakyat yang menculik dan memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Peneguhan terhadap pentingnya kebersamaan ini bisa didapat dengan mengundang seorang filsuf Prancis terkemuka, Gabriel Marcel (1889-1973). Tokoh yang bisa ditempatkan dalam jajaran filsuf eksistensialis ini menyatakan bahwa “Ada” itu selalu berarti “Ada-bersama” (esse adalah co-esse). Ini berarti bahwa relasi antar-manusia yang diistilahkan Marcel “Aku-Engkau” dalam tataran yang tinggi selalu mengandaikan adanya kehadiran (bahasa Prancis: présence). Kehadiran di sini bukanlah dalam pengertian yang lazim dan objektif, tetapi lebih sebagai suatu wujud komunikasi yang melibatkan rasa kemanusiaan dalam suatu perjumpaan (rencontre) yang hangat. Itulah makna kebersamaan yang akan menyatukan “Aku-Engkau” dalam “Kita”, suatu kebersamaan yang betul-betul komunikatif.
Kebersamaan dalam model ini mensyaratkan adanya komitmen untuk tidak hanya memperlakukan orang lain dalam aspek-aspek fungsionalnya saja, seperti dalam relasi manusia dengan benda-benda (“Aku-Ia”). Kebersamaan di sini selalu berusaha meniupkan ruh kemanusiaan yang sesungguhnya, yang saat ini rentan diciutkan maknanya oleh proses birokratisasi dan pandangan-pandangan positivistik yang hanya mengedepankan aspek fungsi sesaat.
Untuk itulah, cara baca terhadap momentum kemerdekaan harus selalu dikaitkan yang proses pemerdekaan, yang menurut Ignas Kleden (Kompas, 16 Agustus 1999) merupakan bagian dari pemaknaan terhadap kemerdekaan sebagai proses serta sebagai tugas kesejarahan yang tak pernah berhenti. Praksis pemerdekaan ini kemudian bisa mendapatkan sudut pandang yang signifikan dari cermin kebersamaan yang begitu indah yang terentang dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Kebersamaan ini tidak saja terlihat dalam ikhtiar-ikhtiar menuju proklamasi, tapi juga tampak setelah proklamasi itu sendiri, dalam proses perumusan sila pertama yang menggambarkan semangat kebersamaan dan saling pengertian yang mendalam.
Proses-proses sosial-politik yang saat ini berada dalam kerangka reformasi sepertinya kurang memerhatikan kearifan aspek kebersamaan yang sebenarnya begitu gamblang dalam sejarah bangsa ini. Salah satu tandanya adalah gejala depolitisasi massa yang masih belum terkikis di tubuh partai-partai. Kesibukan partai berhubungan dengan masyarakat bawah hanya terlihat menjelang dan pada saat pemilu seperti saat ini. Sementara di lain waktu, partai-partai kurang memberi porsi perhatiannya untuk membawa rakyat berpartisipasi dalam proses politik atau membantu mereka untuk dapat memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada. Masyarakat tidak didorong untuk mewujudkan ekspresi kebersamaannya untuk turut serta dalam proses pemerdekaan negeri ini dari nalar-nalar sempit dan kehendak untuk menimbun kuasa. Malah tidak jarang partai hanya difungsikan sebagai penyekat antar-golongan yang semakin mengikis dan menumpulkan rasa kebersamaan.
Seluruh elemen bangsa ini harus diseru untuk terus berupaya menyalakan kembali semangat kebersamaan dalam memperjuangkan pemerdekaan sebagai tindak lanjut dari tercapainya kemerdekaan bangsa ini dari tangan penjajah asing. Gerakan rakyat selama perjuangan kemerdekaan negeri ini harus selalu diingat dan terus dihidupkan kembali dalam memori kolektif bangsa. Karena dari situ kita semua akan tersadar bahwa para rakyat itu juga memiliki kedaulatan yang sama untuk membawa negeri ini ke alam kemerdekaan sejati yang menghargai martabat kemanusiaan dan keberagaman.
Tulisan ini dimuat di Harian Surya, 16 Agustus 2004.
Senin, 02 Agustus 2004
Ruang Partisipasi Pemuda di Daerah
Sabtu, 24 Juli 2004. Pagi itu saya membaca berita ringan di Jawa Pos Online, tepatnya di Radar Madura, tentang sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam FKMS (Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep) yang kecewa karena gagal bertemu untuk beraudiensi dengan anggota Komisi A DPRD Sumenep dan Bappeda. Para mahasiswa itu bermaksud akan memperbincangkan soal beasiswa pemerintah untuk mahasiswa. Menurut Ketua FKMS, Moh. Yunus, seperti dikutip oleh harian ini, pemberian beasiswa itu tidak tepat sasaran. Data mahasiswa penerima beasiswa pun tidak jelas, hanya tercantum nama dan universitasnya.
Terlepas dari fakta bahwa akhirnya, pada hari Senin 26 Juli 2004, para mahasiswa itu berhasil melangsungkan dialog seperti yang mereka inginkan, saya tertarik dengan berita tersebut terutama untuk masuk ke soal ruang partisipasi para pemuda daerah bagi pembangunan dan kemajuan tanah kelahirannya. Saya memiliki hipotesis bahwa pemerintah daerah kita selama ini terkesan kurang memberi ruang partisipasi yang cukup aktif untuk para pemuda, dan lebih melihat para pemuda itu sebagai objek.
Dalam kasus pemberian beasiswa untuk mahasiswa di Sumenep, sejauh pengamatan saya di Yogyakarta, saya memang mencatat setidaknya ada dua kejanggalan. Pertama, sebagaimana terungkap dalam dialog pada 26 Juli tersebut, penyebaran informasinya (sosialisasi) yang relatif cukup terbatas. Hanya beberapa kelompok mahasiswa Sumenep tertentu saja yang mengetahui adanya pemberian beasiswa ini. Dalam beberapa hal saya menilai ini sebagai sesuatu yang wajar, dalam arti bahwa hanya mahasiswa-mahasiswa yang aktif mencari informasi atau dekat dengan sumber informasi di Sumenep sajalah yang paling mungkin mendapatkan informasi tentang beasiswa ini. Ketika itu saya sempat berpikiran siapa tahu berita tentang seleksi pemberian beasiswa ini termuat di situs resmi Pemda Sumenep. Ternyata nihil. Keterbatasan informasi seleksi pemberian beasiswa ini saya kira dapat memperkecil peluang pemberian beasiswa secara merata kepada mahasiswa Sumenep yang dipandang memang membutuhkan dan membuat prosesnya menjadi kurang selektif dan kompetitif.
Kejanggalan kedua, dari informasi yang saya dapatkan, persyaratan untuk seleksi penerimaan beasiswa ini saya kira terlalu minimal. Yang ada hanya persyaratan administratif formal yang sangat biasa: transkrip IPK, surat keterangan tidak mampu, keterangan dari kampus, dan semacamnya. Saya tak menemukan item persyaratan yang dapat menjadi pengikat formal atau emosional antara mahasiswa penerima beasiswa dengan kepentingan Pemda untuk pengembangan dan pembangunan daerah.
Menurut saya, beasiswa yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah daerah sebenarnya dapat memiliki fungsi ganda. Pertama, untuk membantu mereka yang memang kurang mampu tetapi cukup memiliki potensi dan prestasi, dan kedua, untuk lebih menumbuhkan dan memperkuat sense of belonging para mahasiswa terhadap proses pembangunan dan pengembangan tanah kelahirannya. Untuk fungsi yang kedua ini pemerintah sebagai pemberi beasiswa, misalnya, dapat menugaskan para mahasiswa calon penerima beasiswa ini untuk menuangkan gagasan-gagasannya tentang suatu tema tertentu mengenai pembangunan di daerah. Atau, lebih jauh lagi, para penerima beasiswa yang sudah terpilih nantinya ditugasi untuk mendiskusikan tema-tema tertentu oleh Pemda (melalui forum mailing list, misalnya) yang dikoordinasi oleh pihak Pemda yang secara institusional berhubungan dengan fungsi humas dan atau kepemudaan. Atau bisa dengan menawari mereka untuk mengadakan penelitian yang dibutuhkan pemerintah untuk bahan pertimbangan kebijakan pembangunan.
Agak keluar dari konteks beasiswa tersebut, dalam konteks pemberian dana dari Pemda untuk mahasiswa dan konteks ruang partisipasi yang bersifat interaktif, cukup menarik misalnya untuk dipertimbangkan jika Pemda dapat memberikan bantuan dana untuk para mahasiswa daerah yang sedang meneliti (baik dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi) sesuatu hal tentang problem di daerah. Selain sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah terhadap kreativitas dan kepedulian kaum muda, ini juga dapat lebih menyemarakkan penggalian data dan analisis tentang segi-segi kedaerahan, yang selama ini sepertinya kurang cukup diminati.
Dengan landasan pola pandang dua fungsi seperti tersebut di atas, saya pikir seleksi pemberian beasiswa untuk mahasiswa dengan hanya menggunakan seleksi administrasi, seperti diakui oleh Kabid Kesra Bappeda, Sustono, S.E. (Radar Madura, 27 Juli 2004), menjadi sangat tidak memadai. Pemberian beasiswa tersebut mestinya sekaligus bermakna sebagai ruang yang bisa dimanfaatkan untuk ajang partisipasi para pemuda bagi pembangunan daerahnya. Yang terjadi selama ini seolah-olah Pemda “hanya” berperan sebagai pengucur dana yang memandang para mahasiswa itu sebagai kelompok yang diberi saja—lebih sebagai objek. Padahal saya kira para mahasiswa itu pada dasarnya juga memiliki sejumlah kepedulian dan mungkin pemikiran tertentu dalam konteks pembangunan daerah, yang siapa tahu cukup berguna dan berharga. Seorang kawan yang kebetulan juga mahasiswa kelahiran Sumenep dalam beberapa email pribadinya ke saya sempat mendiskusikan masalah pemilihan Bupati Sumenep yang tak lama lagi akan digelar. Beberapa kawan mahasiswa di Yogyakarta juga sempat aktif membicarakan isu PLTN di Madura. Bahkan Forum Silaturahim Keluarga Mahasiswa Madura Yogyakarta (FS-KMMY) beberapa hari yang lalu juga telah mengadakan acara seminar di Madura tentang berbagai tema, seperti telah diberitakan oleh harian ini.
Hal-hal semacam ini saya kira adalah bentuk kepedulian para pemuda kita terhadap peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi di tanah kelahirannya, yang menurut saya juga perlu direspons dan diapresiasi secara positif oleh pemerintah daerah di Madura. Saya memang masih belum terlalu jelas menemukan format pemberian ruang partisipasi untuk kaum muda ini. Tapi saya kira pemerintah harus dapat memanfaatkan momen-momen interaksi yang terjadi antara pemerintah dan para pemuda daerah ini (seperti kasus beasiswa) untuk dimaksimalkan dalam konteks ruang partisipasi tersebut.
Sebelum mengakhiri tulisan ini, sebagai perbandingan, saya ingin sedikit bercerita tentang aktivitas dan kreativitas mahasiswa Jember di Yogyakarta yang dalam pengamatan sekilas saya cukup diperhatikan oleh Pemda Jember. Di Yogyakarta, Pemda Jember mendirikan Asrama Jember yang digunakan sebagai tempat tinggal dan pusat kegiatan mahasiswa Jember. Yang menarik, Asrama Jember, yang aktivitas dan kreativitasnya selalu didukung oleh Pemda, saat ini juga menjadi cukup dikenal karena dari sana muncul kelompok kesenian Patrol yang dalam beberapa ajang kesenian baik di tingkat Yogyakarta maupun nasional cukup mendapat apresiasi yang baik dari komunitas kesenian dan masyarakat seni pada umumnya.
Apresiasi dan dukungan untuk memberi ruang partisipasi terhadap kaum muda daerah ini tentu saja di sisi yang lain menuntut kesediaan dan keseriusan kaum muda itu sendiri untuk lebih peduli dengan perkembangan dan pembangunan di tanah kelahirannya. Artinya, jika ada suatu ruang partisipasi yang terbuka lebar, kaum muda harus betul-betul memanfaatkannya dengan baik. Dari sinilah kemudian terlihat bahwa ruang partisipasi yang saya bicarakan ini pada dasarnya adalah sebentuk jalinan kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak sekaligus, pemerintah dan kaum muda.
Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa jika soal ruang partisipasi kaum muda ini terus diabaikan, saya khawatir para pemuda kita nantinya akan (dianggap) menjadi “Si Malin Kundang”. Bila sudah demikian, mungkin sekali tanah airnya tidak akan dapat menerimanya dan menampiknya untuk kembali. Padahal, “Si Malin Kundang” itu punya banyak cerita tentang perasaan-perasaan yang digelisahkannya selama ini—tentang tanah airnya yang masih dilanda epidemi korupsi, kaum elit sosial yang tak punya empati, rakyat yang masih sering dibodohi, atau tentang petani tembakau yang masih sering dikibuli.
Tulisan ini dimuat di Harian Radar Madura, Minggu, 1 Agustus 2004.
Minggu, 27 Juni 2004
Biara Spiritual Karen Armstrong
 Judul buku : Menerobos Kegelapan: Sebuah Autobiografi Spiritual
Judul buku : Menerobos Kegelapan: Sebuah Autobiografi Spiritual
Penulis : Karen Armstrong
Penerbit : Mizan, Bandung
Cetakan : Pertama, Mei 2004
Tebal : 558 halaman
Merefleksikan perjalanan hidup adalah bagian dari pertanggungjawaban kita dalam menjalani hidup itu sendiri. Ketika alur hidup yang telah lalu dibiarkan tidak direfleksikan, tapak-tapak kita menjadi semakin rapuh dan tak bermakna.
Buku ini mengisahkan perjalanan spiritual Karen Armstrong, seorang pemikir lintas agama yang intens mengkaji soal-soal spiritualitas dan studi agama. Buku ini merupakan kelanjutan dari autobiografinya yang terbit pada 1981, Through the Narrow Gate, yang bertutur panjang lebar tentang kehidupannya di biara (1962-1969).
Sebagai sebuah sekuel, buku ini menjadi semakin menarik karena perkembangan kehidupan spiritual Armstrong dan karier intelektualnya sejak penulisan buku itu menjadi semakin kaya dan mengagumkan. Dari tangannya lahir karya-karya besar, di antaranya A History of God, Holy War, Muhammad, dan Buddha.
Di bagian prakata, Armstrong meringkas pengalamannya ketika hidup sebagai biarawati Katolik Roma selama tujuh tahun. Armstrong menggambarkan bagaimana pilihannya itu pada waktu itu tergolong radikal dan berani, di tengah-tengah latar keluarganya yang bukan tergolong keluarga yang saleh, serta dalam latar perubahan sosial di Inggris pasca Perang Dunia Kedua.
Sialnya, kehidupan Armstrong di biara justru tidak bisa memberikan apa yang dicarinya. Di satu sisi, biara pada tahun 1960-an masih berada dalam kendali rezim tradisional yang berada pada titik terburuknya, sebelum kemudian mendapat pembaruan dari Konsili Vatikan Kedua. Armstrong merasakan kesulitan yang cukup menekan ketika dalam ritual dan doa-doa yang dijalaninya dia ternyata cukup sering tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan yang diharapkan datang menyapanya. Akhirnya, pada 1969, setelah melalui pergulatan hebat, Armstrong memilih untuk keluar dari biara.
Sekitar separuh dari bagian awal buku ini Armstrong menuturkan kegelisahannya ketika ia kembali ke kehidupan awam. Pada tahun-tahun itu Armstrong menjalani kehidupan awamnya dengan sulit, mengalami semacam kejutan budaya, yang bahkan menjadi traumatis. Perlu penyesuaian yang cukup menuntut ketegaran untuk dapat berintegrasi kembali dengan suasana hidup yang berbeda. Armstrong merasa seperti terlunta di kamp pengasingan setelah meninggalkan rumah spiritualnya di biara, terkurung dalam dirinya sendiri, tak mampu melarikan diri, atau menjangkau orang lain.
Tapi kemudian datanglah sebuah momen berkah. Di tahun 1972, dalam salah satu kuliahnya, Armstrong tersentuh dengan puisi T.S. Elliot berjudul Ash Wednesday. Puisi yang menggambarkan perjalanan hidup dengan menggunakan ibarat pendakian sebuah tangga spiral inilah yang kemudian menginspirasikan Armstrong untuk terus bertahan, bertawakal, dan memaknai momen kegelisahannya itu secara lebih positif. Namun tekanan kembali datang. Pada tahun 1975 tesisnya di universitas ditolak dan kemudian pada tahun 1976 dia didiagnosis menderita epilepsi. Armstrong semakin kehilangan momentum kebangkitannya kembali. Beruntunglah bahwa pada masa-masa sulit itu Armstrong masih bisa beraktivitas, mengajar di Bedford College dan kemudian menjadi guru di sebuah sekolah menengah.
Pada akhirnya, ketika menulis Through the Narrow Gate (1981), Armstrong tersentak dan ditarik kembali ke dalam suatu perasaan rindu akan yang sakral, seperti yang dulu pernah mengantarnya ke biara. Tak lama berselang, Armstrong kemudian terlibat kerja sama dengan British Channel 4 dalam sebuah pembuatan serial televisi berjudul Opinions. Di situlah kemudian gagasan-gagasan orisinal Armstrong tersemai. Tahun 1983 Armstrong kemudian menjalin kontrak untuk membuat serial dokumenter tentang kehidupan St. Paulus. Dalam riset yang berpusat di Yerusalem itu, Armstrong menemukan banyak hal yang jauh melampaui dari apa yang didapatnya di biara, tentang peran St. Paulus dan perkembangan Kristen awal. Selain itu, riset yang oleh Armstrong pertama diyakini akan dapat membongkar intoleransi dogmatis gereja itu juga telah mengantarkannya untuk berkenalan dengan agama Yahudi. Dari situ terbitlah buku The First Christian (1983).
Persentuhan Armstrong dengan agama Yahudi dan Islam, selain dalam kunjungannya ke Yerusalem selama melakukan riset tentang St. Paulus itu, semakin intens ketika di tahun 1985 dia mendapat kesempatan untuk meneliti tentang Perang Salib, yang meski gagal ditayangkan tapi menghasilkan sebuah karya memukau berjudul Holy War (1988). Pada kesempatan inilah ketertarikannya pada Islam khususnya menjadi semakin bertambah. Armstrong merasa malu bahwa selama ini dia dibesarkan dalam ketidaktahuan tentang Yudaisme dan Islam.
Penjelajahan Armstrong ketika menulis buku A History of God (1993) yang dimulai pada tahun 1989 semakin memperkaya perspektif spiritualitas yang telah didapatnya. Pada saat penulisan buku tersebut Armstrong juga sempat menerbitkan buku Muhammad (1992) yang mendapat sambutan baik di kalangan muslim. Dari situ Armstrong kemudian semakin yakin bahwa perspektif empati akan sangat berguna untuk mempelajari tradisi agama lainnya. Bahwa hal penting yang harus diingat dalam mempelajari teologi adalah kesiapan untuk menyediakan sebuah ruang kosong dalam pikiran kita sehingga dalam keheningan kesadaran akan Wujud Ilahiah itu akan mengungkapkan dirinya, hingga akhirnya menjadi bagian dari kita sendiri.
Pengisahan Armstrong yang jujur, berani, dan lugas sungguh sayang dilewatkan. Kisah perjuangannya menerobos kegelapan dan meniti tangga menuju taman cahaya spiritualitas yang menyejukkan dari biara Katolik Roma hingga ke biara spiritual yang dibangunnya sendiri secara perlahan dan sabar ini pada satu sisi semakin menegaskan makna penting refleksi diri agar orientasi hidup dan transformasi diri kita tetap terjaga. Yang paling penting, buku ini menuturkan pesan kepada kita tentang bagaimana menghayati dan memaknai keberagamaan dan spiritualitas dalam tatanan zaman yang seperti tak menyediakan ruang bagi yang transenden di satu sisi, dan fakta pluralitas dan pergaulan lintas sosial yang semakin terbuka di sisi lain. Melalui kisah pengembaraan Armstrong ini kita diingatkan kembali bahwa keberagamaan dengan dasar empati dapat membimbing kita ke suatu kesadaran teologis yang dapat menghadirkan sikap yang lebih manusiawi dan bermoral.
Tulisan ini dimuat di Harian Jawa Pos. 11 Juli 2004.
Senin, 21 Juni 2004
Merengkuh Kembali Makna Keimanan Sejati
Judul buku : The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan
Penulis : Seyyed Hossein Nasr
Penerbit : Mizan, Bandung
Cetakan : Pertama, November 2003
Tebal : lviii + 406 halaman
Keberagamaan setiap saat selalu tertantang oleh gerak kemajuan zaman. Pada Abad Pertengahan dan Modern, agama digempur oleh berbagai argumentasi filsafat rasional untuk dijungkalkan ke alam ketakbermaknaan dan nihilisme, sehingga muncul wacana tentang wahyu dan akal (agama dan filsafat). Pada era global ini, tantangan agama-agama adalah picu kekerasan dan konflik, kehidupan pluralistik, dan tanggung jawab merawat kedamaian dunia.
Belakangan ini, Islam sering kali dituding sebagai biang yang berperan penting dalam aksi-aksi teror dan kekerasan, seperti dalam peristiwa 11 September atau ledakan bom di Bali. Ini membuat Islam menjadi tertekan oleh serentetan stigma negatif. Akibatnya, salah paham semakin menjadi-jadi, dan partisipasi Islam sebagai sebuah agama dan gugus peradaban bagi keberlangsungan dunia yang lebih baik menjadi terhambat.
Dalam konteks dan formasi sosial yang demikian, Seyyed Hossein Nasr melalui karya terbarunya yang berjudul The Heart of Islam ini menyajikan sebuah paparan yang tidak saja bersifat apologis atau reaktif terhadap situasi tersebut, tetapi juga menegaskan spirit universal Islam yang terpendam sedemikian rupa dalam ajaran-ajarannya. Yang dilakukan Nasr dalam buku ini tidak saja upaya klarifikasi bagi orang di luar Islam atas salah tafsir yang terjadi, tapi juga kontekstualisasi dan refleksi atas sejumlah ajaran Islam menghadapi tantangan global yang begitu menantang.
Nasr membuka uraiannya dalam buku ini dengan dimensi teologis Islam. Dalam bagian ini Nasr menekankan keterhubungan Islam dengan gugus agama besar lainnya, yakni Yahudi dan Kristen. Nasr menegaskan bahwa Islam mengimani Tuhan Yang Esa (monoteis) dan juga mengakui nabi-nabi sebelum Muhammad (nabi kaum muslim). Ini berarti bahwa Islam adalah bagian tak terpisahkan dari rumpun agama Ibrahim dan memandang dirinya terkait erat dengan kedua agama tersebut. Meski begitu, Islam mengklaim sebagai pelengkap kedua agama itu dan sebagai bentuk terakhir dari pesan monoteisme Ibrahim. Islam adalah agama primordial sekaligus agama terakhir, sehingga ini menggambarkan karakter universal Islam serta kemampuannya untuk menyerap secara intelektual dan kultural berbagai hal dari tradisi sebelumnya.
Universalitas keimanan yang diakui Islam ini selanjutnya mendapatkan dukungan dari pengalaman historis Islam itu sendiri, manakala Islam mengalami kontak langsung dengan hampir semua agama mayoritas yang ada: Yahudi dan Kristen di Arab, agama Zoroaster dan Manichaeisme di Persia, Hindu dan Buddha di India, dan juga agama-agama Cina. Ini menjadikan budaya Islam berkembang ke arah perspektif keagamaan yang mendunia dan kosmopolitan.
Salah satu wujud keterbukaan ini terlihat dalam beragam corak keberislaman yang berkembang di seantero dunia: ada Sunni, Syi’ah, Wahhabi, dan sebagainya. Yang menarik, kekayaan spektrum Islam ini menjadi kompleks saat Islam berhadapan dengan hegemoni Barat dalam bentuk kolonialisme, yang dimulai dari penyerangan Napoleon atas Mesir pada tahun 1798. Bermunculanlah beragam respons terhadap kemunduran posisi umat Islam dalam kancah dunia. Nasr mencatat tiga sikap umat Islam yang berkembang. Ada kelompok yang berpandangan bahwa kaum muslim menjadi lemah karena penyimpangan yang terjadi dari ajaran keimanan yang murni, ada kelompok yang meyakini Mahdiisme, dan ada kelompok yang mendukung proses modernisasi Islam.
Meski demikian, Nasr mencatat bahwa ketiga sikap tersebut bukanlah yang dipilih oleh kebanyakan umat Islam. Menurut Nasr, “muslim tradisional” lebih memilih untuk merawat keberlangsungan tata cara hidup dan pemikiran Islam tradisional, bukannya mengedepankan reaksi dan apologi. Tentu saja ini tidak menafikan perlunya langkah pembaruan. Kelompok ini bukannya menentang apa saja yang datang dari Barat, tetapi lebih kepada penolakan atas pengaruh merusak dari budaya modern Barat yang mengancam nilai-nilai Islam—sama halnya juga bahwa ada sejumlah hal yang mengancam nilai-nilai Kristen dan Yahudi di Barat.
Pada bagian ini Nasr menggarisbawahi bahwa muslim tradisional ini tidak mengenal aksi-aksi kekerasan dalam menjaga keberlangsungan Islam. Tindakan yang islami adalah mempertahankan dan melakukan pembelaan diri. Kekerasan, bila bukan untuk pembelaan diri, dengan dalih apa pun tidak dibenarkan Alquran dan syariat.
Mengenai fenomena “fundamentalisme” yang kerap melancarkan aksi kekerasan atas nama agama, Nasr memberi catatan bahwa kita perlu melihat konteks terjadinya tindakan-tindakan kekerasan yang dimotori kaum fundamentalis itu dengan cara yang sama yang dengannya Barat mampu meletakkan peristiwa semacam pembersihan etnis oleh Serbia dalam konteksnya, dengan tidak mengidentifikasi kejadian tersebut sebagai tindakan yang hanya terkait dengan agama semata. Artinya, harus diklarifikasi latar belakang kejadian tersebut, dan jangan langsung secara apriori dikaitkan dengan agama. Nasr juga melancarkan kritis yang pedas bahwa sebenarnya tidak cuma fundamentalisme dalam agama yang berpotensi dogmatis, ekstrem, dan fanatik, tetapi juga fundamentalisme sekuler yang juga mampu mendatangkan agresi terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Di bagian yang lain, Nasr juga berbicara tentang Hukum Tuhan, dan menegaskan bahwa syariat tidak hanya suatu hukum positif yang konkret, tapi juga suatu kumpulan nilai dan kerangka bagi kehidupan keagamaan kaum muslim yang mengandung nilai-nilai etis dan etos keagamaan itu sendiri. Inilah yang menjadi landasan bagi terciptanya suatu ummah (komunitas) yang diridai Tuhan. Dengan demikian, Nasr mengingatkan bahwa dari perspektif Islam, nilai suatu masyarakat di mata Tuhan terletak pada kualitas kebajikannya, ketinggian moralnya, dan bukan pada jumlah kekuasaannya.
Di tiga bab terakhir dari tujuh bab buku ini, Nasr menegaskan komitmen Islam terhadap nilai cinta, kedamaian, keadilan, dan tanggung jawab kemanusiaan.
Uraian dan refleksi Nasr yang begitu gamblang sepanjang buku ini bermakna penting karena Nasr mengajak kita untuk menemukan dan merengkuh kembali makna keberimanan dan keberislaman yang sejati dalam konteks sosial global saat ini. Yang khas dari Nasr adalah perspektif filosofis dan perennial yang begitu kental, sehingga paparannya tampak sebagai langkah introspeksi dan evaluasi diri terhadap berbagai segi ajaran mendasar agama untuk dikembalikan ke jantung maknanya yang hakiki. Langkah meneguhkan kembali nilai-nilai kebajikan dan kebijaksanaan dalam agama semacam inilah yang amat diperlukan saat ini menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan berat.
Tulisan ini dimuat di Harian Surya, 20 Juni 2004.
Sabtu, 24 April 2004
Membincang Kafâ’ah
Dalam konteks fikih, istilah kafâ’ah berarti keserasian atau kecocokan (mumâtsalah, suitability) antara pasangan suami-istri demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pernikahan. Faktor menciptakan persamaan sosial (musâwah fî umûr ijtimâ‘iyyah), merawat keberlangsungan dan kekukuhan ikatan pernikahan dan terciptanya kebahagiaan di antara sepasang suami-istri merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem hukum Islam dari konsep kafâ’ah ini.
Berbagai mazhab memasukkan unsur-unsur yang berbeda yang patut dipikirkan dalam mempertimbangkan soal kafâ’ah ini. Mayoritas ulama (jumhûr) menyebut unsur agama, nasab, status kemerdekaan, dan mata pencaharian sebagai hal yang harus diperhitungkan. Kelompok mazhab Maliki hanya menyebut dua hal: agama dan kondisi fisik (yang dimaksud kondisi fisik di sini bukannya soal kecantikan, tetapi cukup untuk memastikan apakah calon pasangannya tidak memiliki cacat tubuh tertentu yang dapat mengurungkan niatnya untuk mengawini orang tersebut). Mazhab Syafi’i menyebut lima hal: agama, status kemerdekaan, nasab, cacat fisik, dan mata pencaharian. Sementara ulama Hanbali dan Hanafi memasukkan unsur harta sebagai hal yang patut dipertimbangkan dalam soal kafâ’ah.
Para ulama berbeda pendapat dalam memosisikan kafâ’ah sebagai syarat dalam pernikahan, yang secara umum dibagi ke dalam dua pendapat. Yang pertama menyatakan bahwa kafâ’ah sama sekali bukan syarat pernikahan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat wajib. Termasuk dalam kelompok ini adalah Sufyân al-Tsawrî, Hasan al-Bashrî, dan al-Karakhî. Dalil mereka antara lain adalah hadis Nabi yang menyatakan bahwa “…manusia itu seperti gigi sisir; seseorang tidak memiliki kelebihan atas orang yang lain, kecuali dalam hal ketakwaannya” (Subulussalâm, 3: 129). Hadis ini dipandang menyuarakan egalitarianisme Islam secara mutlak sehingga kafâ’ah tidak diperlukan dalam kasus pernikahan. Kelompok ini juga berargumen dengan ayat al-Qur’an yang menyatakan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah dari sisi ketakwaannya (Q.S. al-Hujurât [49]: 13).
Terhadap dalil ini, kelompok kedua, yang mensyaratkan kafâ’ah dalam pernikahan, menyatakan bahwa teks-teks tersebut pada dasarnya menyatakan persamaan hak dan kewajiban manusia. Tetapi dalam konteks pergaulan kemasyarakatan sehari-hari, teks juga mengakui adanya kelebihan sesosok pribadi seseorang dibandingkan dengan yang lainnya, baik dalam hal kekayaan maupun kualitas keilmuan (lihat, Q.S. al-Nahl [16]: 71, dan Q.S. al-Mujâdalah [58]: 11). Ini berarti bahwa teks juga mengakui realitas sosial yang memperlihatkan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat sebagai suatu hal yang manusiawi.
Kelompok yang pertama ini menambahkan dengan argumen hadis Nabi yang mengisahkan sahabat Bilâl yang hendak melamar seorang perempuan dari kaum Anshâr dan didukung oleh Nabi, padahal kaum Anshâr sendiri menolak. Ada juga hadis lain yang menggambarkan kasus semacam ini. Namun demikian, hadis-hadis ini selanjutnya secara substansial banyak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang dijadikan dalil kelompok yang kedua.
Kelompok yang kedua terdiri dari empat mazhab yang terkemuka dalam fikih, yaitu Hanafi, Syafi’i, Hanbali, dan Maliki, yang merupakan pendapat kelompok mayoritas. Mereka menyodorkan beberapa hadis Nabi, yang di antaranya menyatakan bahwa perempuan itu harus dinikahkan dengan orang yang kufu’. Selain hadis yang begitu banyak dikutip sebagai landasannya, kelompok kedua ini berargumen dengan pendekatan rasional. Menurut mereka, kemaslahatan suami-istri tidak akan dicapai bila tidak ada keserasian (kafâ’ah). Perspektif kafâ’ah ini terutama dilihat dari sisi si perempuan. Artinya, jika di suami tidak kufu’ dengan si istri, maka ikatan pernikahan dapat bermasalah. Demikian juga, orang tua si perempuan (istri) akan menjadi rendah derajatnya secara sosial jika menantunya tidak kufu’, sehingga tujuan sosial pernikahan untuk mengukuhkan integritas sosial menjadi gagal.
Setelah mengulas argumentasi dua kelompok ini, secara menarik Wahbah al-Zuhaylî (al-Fiqh al-Islâmî, 7: 243) menyatakan bahwa ia pribadi cenderung sepakat dengan pendapat mazhab Maliki yang hanya memasukkan dua unsur dalam menimbang kafâ’ah, yaitu dalam hal agama dan kondisi fisik. Menurut Wahbah, hadis-hadis yang menjadi landasan mayoritas ulama (kelompok kedua) pada dasarnya lemah (dha‘îf) dan dalil yang menguatkan kelompok kedua ini hanyalah dari pendekatan rasionalnya saja, yang dalam membacanya—dan ini harus diberi garis bawah—berlandaskan pada ‘urf (kebiasaan). Karena itu, ketika pada era sekarang egalitarianisme (musâwah) menjadi landasan pergaulan sosial, dan ketika stratifikasi-sosial-yang-sepadan yang dipandang sebagai syarat terciptanya harmoni keluarga tidak lagi dinilai signifikan, maka dalil yang menjadi alasan kafâ’ah tidak perlu diperhitungkan lagi.
Mayoritas ulama dari keempat mazhab fikih sepakat bahwa kafâ’ah merupakan syarat wajib dan bukan syarat sah, sehingga jika seorang perempuan menikah dengan tidak kufu’, maka akad nikahnya itu sah, tetapi walinya memiliki hak untuk menentang dan menuntut pembatalan akad tersebut (faskh).
Kafâ’ah itu sendiri menurut mayoritas ulama merupakan suatu tuntutan dari sisi laki-laki untuk si perempuan, suatu hak yang bertujuan demi menjaga kebaikan si perempuan, sehingga disyaratkan si calon suami serasi (kufu’) dengan si calon istri. Sebaliknya, si perempuan tidak disyaratkan kufu’ terhadap si laki-laki, sehingga ketentuan fikih mengizinkan jika si perempuan secara kualitatif berada jauh di bawah si laki-laki, dengan alasan bahwa si laki-laki tidak akan menjadi tercoreng namanya dengan menikahi perempuan yang tidak kufu’ itu. Memang dalam beberapa kasus kafâ’ah juga harus dipertimbangkan untuk kepentingan si laki-laki, seperti dalam kasus pernikahan yang oleh pihak laki-laki diwakilkan kepada orang lain.
Kemudian, siapa yang memiliki hak dalam soal kafâ’ah ini? Para ulama sepakat bahwa baik si perempuan maupun walinya sama-sama memegang hak kafâ’ah ini. Karena itu, jika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu’, maka walinya berhak menuntut pembatalan (faskh) akad nikah tersebut. Demikian juga, jika seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan tidak kufu’, maka si perempuan berhak untuk menuntut pembatalan (faskh).
Ada sebuah hadis menarik yang berhubungan dengan kasus ini, yang mengisahkan bahwa suatu hari seorang gadis datang mengadu kepada Nabi perihal ayahnya yang memaksa kawin dengan seseorang lelaki yang tidak ia sukai. Rasulullah memutuskan mengembalikan urusan pernikahan itu kepada anak gadis tadi. Memang, ia akhirnya menerima pilihan orangtuanya, dengan berkata: “…yang penting (dari pengaduan saya ini) orang tahu bahwa dalam masalah pernikahan, seorang ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya” (HR Ibn Mâjah, Nasâ’î, dan Ahmad, Nayl al-Awthâr, 6: 127).
Terakhir, ada satu pendapat menarik dari kelompok mazhab Hanbali yang menyatakan bahwa bila ternyata si suami diketahui tidak kufu’ setelah akad nikah dilangsungkan, maka si istri memiliki hak untuk menuntut pembatalan akad tersebut (faskh), tetapi wali perempuan itu tidak. Ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama dari mazhab yang lain.
* * *
Setelah beberapa perspektif fikih klasik dipaparkan secara ringkas, menarik untuk mempertemukannya dengan praktik sosiologis pernikahan dalam masyarakat kita. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, konsep kafâ’ah sebagai elemen normatif yang menjadi salah satu pertimbangan dalam mengikat suatu tali pernikahan tidak jarang dijadikan rujukan pembenaran bagi pilihan tindakan sosial tertentu.
Dalam kasus semacam ini, ada beberapa hal yang bisa terbaca. Pertama, masih dominannya peranan wali (si perempuan) dalam memutuskan dengan siapa si perempuan itu akan menikah. Tidak jarang seorang wali akan menggunakan hak ijbâr atas anak perempuannya ketika ruang dialog tentang status kafâ’ah pasangan tersebut berakhir buntu. Bersamaan dengan itu pula, kafâ’ah kemudian menjadi suatu konsep yang relatif cukup subjektif sehingga menjadi semacam “pasal karet” yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu (dalam banyak kasus kepentingan wali/orangtua). Inilah salah satu problem dari konsep ini, karena dalam praktiknya ternyata rentan mengantarkan ketentuan fikih menjadi “otoriter”.
Dalam hal ini, mungkin menarik dibicarakan lebih jauh, di mana batas-batas ketentuan kafâ’ah ini bisa menjadi “otoriter” dan tidak. Menurut penulis, sejauh kedua belah pihak (wali dan si anak perempuan) bersedia tulus untuk membicarakan berbagai detail sisi-sisi kafâ’ah tersebut secara jujur dan terbuka, maka otoritarianisme dapat dihindari.
Kedua, konsep kafâ’ah memperlihatkan kepada kita betapa perempuan dalam konteks fikih betul-betul mendapat suatu sistem “perlindungan” yang ekstra ketat. Perempuan tidak dibiarkan mendapatkan jodoh yang bisa menghinakan dirinya dan keluarganya. Akan tetapi, pendekatan fikih yang bertujuan ingin melindungi kaum perempuan ini kemudian menjadi cukup problematis ketika dalam praktik sosial yang patriarkal kaum perempuan tidak cukup memiliki hak yang kuat untuk menyuarakan pendapatnya. Misalnya begini. Seorang perempuan dijodohkan dengan seorang laki-laki oleh walinya, dan telah melewati suatu proses pertimbangan dari sisi kafâ’ah oleh walinya secara matang.
Sampai pada titik ini terlihat perspektif perlindungan dari ketentuan fikih tersebut. Persoalannya, bagaimana jika perhitungan kafâ’ah si wali tidak sama dengan anak perempuannya. Artinya, si anak menemukan sisi-sisi yang membuat si calon suaminya tidak kufu’ dalam pandangan si anak. Sementara ketentuan fikih memberikan hak ijbâr untuk si ayah sehingga si anak berada dalam posisi yang relatif lemah, maka dengan demikian tujuan demi melindungi kemaslahatan si anak tadi berada di ujung tanduk hak ijbâr wali.
Perspektif kedua ini sebenarnya mengandung kemungkinan lain. Jangan-jangan fikih tidak terlalu memberikan penekanan pada sisi “perlindungan” terhadap perempuan, tetapi jangan-jangan ketentuan fikih ini secara keseluruhan memperlihatkan posisi perempuan yang lemah, dan, mungkin, kurang dihargai. Artinya, ada perspektif bias ketimpangan jender dalam kasus ini. Ketentuan hak ijbâr misalnya menurut penulis masih memperlihatkan bagaimana perempuan dianggap tidak cukup mampu untuk memilih calon suami yang tepat, sehingga ia dapat diveto.
Dalam soal ini, menarik untuk diteliti sejauh mana kaitan antara konsep hak ijbâr dalam fikih, kaitannya dengan tujuan “perlindungan” terhadap kaum perempuan, atau hubungannya dengan pandangan minor yang cukup populer—dan ini mendapatkan landasannya melalui hadis-hadis Nabi—bahwa perempuan itu sumber fitnah (lihat, Shahîh Bukhârî, Bab Nikah).
Ketiga, dalam suatu perbincangan pribadi dengan beberapa rekan, muncul pertanyaan nakal, mengapa para fukaha tidak memasukkan unsur kecocokan perasaan (perasaan saling mencintai) sebagai salah satu unsur kafâ’ah. Bukankah hubungan pernikahan yang harmonis akan lebih mudah tercapai bila ada unsur kasih sayang lebih dahulu. Analisis atas masalah ini tentu juga harus melibatkan disiplin psikologi yang kurang dieksplorasi secara mendalam oleh para fukaha. Secara normatif, masalah ini mungkin akan mengantarkan perbincangan pada tema tentang bagaimana semestinya pola pergaulan antara laki-laki dan perempuan.
Keempat, dalam praktik sosial yang mungkin cenderung feodal, ada segi-segi tertentu yang lebih dipertimbangkan di antara berbagai unsur kafâ’ah. Misalnya, ada seorang laki-laki yang kualifikasi keilmuan dan integritas pribadinya, misalnya, tidak cukup baik, tetapi karena status sosial keluarganya yang cukup terpandang, seperti dari segi kekayaan atau “keningratan”, dia dengan penuh percaya diri dia melamar seorang perempuan dengan kualitas keilmuan dan kedirian yang lebih baik, tetapi berasal dari kelas sosial menengah ke bawah. Unsur kafâ’ah yang lebih dilihat dalam kasus semacam ini kemudian adalah soal status sosial: bahwa si lelaki berasal dari keluarga kelas atas.
Dari kasus-kasus terakhir semacam ini terlihat betapa ternyata faktor normatif tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Nalar masyarakat, bahkan nalar orang-orang yang akrab dengan ilmu-ilmu keagamaan pun, rentan dirasuki oleh perspektif budaya yang bisa saja berperspektif “feodal”, dan kemudian menguasai cara berpikirnya.
Dalam hubungannya dengan feodalisme dan eksklusivisme kiai, penting untuk dicatat jangan-jangan feodalisme dan eksklusivisme di kalangan kiai ini sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan dimensi normatif kafâ’ah, tetapi dengan formasi sosial-budaya yang tidak terlalu merelakan seorang anggota keluarga (terutama perempuan) dinikahi oleh “orang lain” (dalam arti, orang yang tidak memiliki hubungan famili). Realitas pernikahan antarsepupu kenyataannya tidak hanya terjadi di kalangan kiai, tapi juga masyarakat umum. Jangan-jangan ada sebuah konstruksi sosial tertentu yang meneguhkan perspektif semacam ini, yang kemudian seperti mendapatkan pembenarannya dalam konsep kafâ’ah tersebut. Bila memang demikian, perlu dipikirkan, dari mana kita harus memulai membongkarnya?
Wallâhu a‘lam bishshawâb.
Tulisan ini disampaikan dalam acara diskusi mingguan warga Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Yogyakarta, 21 April 2004.
Label: Gender Issues, Religious Issues
Kamis, 01 April 2004
Pemilu 2004 dan Kembalinya Apatisme Politik
Ketika pemilu yang dalam orde reformasi ini untuk kedua kalinya akan segera diselenggarakan tidak lama lagi, muncul pertanyaan sederhana yang cukup menggelitik: Apa bedanya Pemilu 1999 dengan Pemilu 2004?
Sekilas pertanyaan ini tidak bermakna apa-apa dalam situasi sosial-politik sekarang ini. Akan tetapi, dalam pertanyaan singkat tersebut, juga tersimpan jawaban mendalam tentang langkah maju macam apa yang telah diraih setelah panji reformasi dikibarkan di mana-mana dengan gairah politik demokrasi yang begitu menggebu.
Pemilu diyakini dapat menjadi sebuah media politik yang paling tepat untuk menjadi jembatan emas bagi pemulihan negeri ini. Pemilu adalah jalan yang konstitusional, sehingga hasilnya nanti diharapkan akan lebih mudah diterima oleh semua kalangan. Akan tetapi, bila mengamati bagaimana Pemilu 2004 dipersiapkan, terbersit keraguan apakah harapan besar itu dapat tercapai. Di samping kekurangsigapan dalam langkah penyiapannya, menjelang pemilu yang sudah tidak lama lagi ini muncul sejumlah kecenderungan yang mengarah kepada dugaan kuat bahwa pola budaya politik reformasi saat ini menjadi cukup sulit dibedakan dengan pola budaya politik orde baru yang mengantarkan keterpurukan negeri ini.
Perilaku partai dan berbagai elemen di dalamnya (elit partai, calon legislatif, ataupun massa partai) seperti menjadi kabar buruk di tengah harapan yang meluap dari masyarakat. Berita di mana-mana tentang rebutan nomor jadi antarcaleg dan digunakannya ijazah palsu semakin menyingkap borok akut di tubuh partai yang selama ini sudah terendus. Dalam kasus semacam ini, yang terbaca dengan cukup mudah oleh masyarakat adalah raibnya ketulusan para elit partai dalam berpolitik. Menjadi calon legislatif saat ini cukup sulit dibedakan dengan zaman orde baru, ketika badan legislatif bukan lagi menjadi sebuah tempat untuk memperjuangkan nilai-nilai luhur, kebijaksanaan, idealisme, dan kepentingan rakyat, ketika legislatif hanya menjadi ajang permainan kekuasaan belaka dan dengan mudah mencampakkan nilai-nilai moral.
Di daerah, aksi saling sikut antarcaleg menjadi pemandangan yang begitu mudah disaksikan oleh masyarakat awam. Ironisnya, beberapa elit partai bahkan tidak punya cukup rasa malu ketika mempertontonkan hal semacam itu di depan tatapan polos masyarakat.
Pertunjukan politik menjelang Pemilu 2004 yang semestinya memercikkan harapan fajar perubahan yang benar-benar mencerahkan ini malah memunculkan kekhawatiran akan kembalinya apatisme politik masyarakat. Ketika politik tampak begitu sulit menjanjikan perbaikan, bisa saja masyarakat akan lari dan memilih tidak peduli apakah negeri ini akan diperintah dengan gaya diktator berkedok demokrasi atau apa, asalkan kehidupan sehari-hari mereka dapat cukup terjamin. Atau, dengan kata lain, jangan-jangan masyarakat akan merindukan kembalinya otoritarianisme orde baru yang memiliki harmoni semu itu.
Apatisme di sini memiliki substansi yang tidak jauh berbeda dengan politik massa mengambang ala orde baru, dengan memotong jalur-jalur partisipasi politik. Bedanya, politik massa mengambang orde baru diterapkan dengan dukungan politik intimidasi dan hegemoni penguasa, sedang saat ini politik massa mengambang didorong oleh berbagai kekuatan politik yang haus kekuasaan dengan membiarkan rakyat dalam cengkeraman ketidakdewasaan.
Menghadapi situasi semacam ini, ada dua hal yang bisa kita harapkan dapat membantu merawat semangat perubahan dan harapan masyarakat dalam konteks reformasi. Pertama, dengan semakin mendekatnya waktu pelaksanaan pemilu, termasuk juga kampanye, berbagai elemen partai politik pada khususnya diharapkan dapat bersikap lebih arif dalam memperlakukan masyarakat (pemilih). Parpol tidak boleh semata-mata melihat masyarakat sebagai objek yang bisa diperalat untuk memenuhi ambisi kekuasaan belaka. Parpol harus ikut mendukung setiap upaya untuk menjadikan Pemilu 2004 lebih berkualitas. Misalnya, dengan ikut menyosialisasikan mekanisme pemilihan yang lebih menekankan pada sosok person ketimbang pada nomor urut yang sudah ditetapkan parpol.
Dalam ajang kampanye, parpol juga diharapkan memperlihatkan perilaku yang lebih dewasa dengan tidak hanya mengumbar pesona massa, tetapi juga diimbangi dengan pendekatan rasional dan mendidik. Simpati rakyat harus didapat dengan cara-cara yang jujur dan dewasa, bukan dengan pembodohan. Intinya, rentang waktu yang tersisa ini harus bisa digunakan dengan sebaik-baiknya oleh berbagai kekuatan politik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atas peran yang dimainkan berbagai kekuatan politik itu, untuk terus mengawal proses perubahan dengan baik.
Kedua, berbagai elemen masyarakat, terutama kelompok-kelompok kritis dan strategis, harus terus dengan gencar mengawal proses pemilu ini agar dapat memberi hasil yang sesuai dengan harapan. Gerakan Anti-Politisi Busuk sebagai sebuah gerakan yang ingin menghindari hadirnya kembali sosok-sosok politisi yang miskin nurani sangat perlu didukung secara luas.
Lebih umum lagi, poin yang kedua ini sebenarnya ingin menitiktekankan bahwa agenda reformasi terpenting saat ini adalah bagaimana menjaga agar kultur politik orde baru tidak kembali berkuasa dan menyebar epidemi yang sulit diobati. Turunnya Soeharto dari kekuasaan orde baru dan bergantinya sosok penguasa tidak menjamin bahwa sistem dan pola orde baru yang terkutuk juga lenyap. Berbagai gerakan prodemokrasi saat ini masih harus berjuang keras melawan praktik korupsi yang semakin canggih dan menyusup ke mana-mana, menyingkap kebusukan nurani politik yang terbungkus dalam retorika menawan, dan terus menanamkan budaya kritis dan rasional kepada masyarakat.
Partisipasi politik yang semakin meluas dari berbagai elemen masyarakat dan iklim yang cukup memberi ruang bagi kebebasan berekspresi setelah tergulingnya rezim orde baru merupakan modal besar bagi upaya reformasi. Ini tidak boleh disia-siakan dan mesti dihargai. Kita harus memberinya makna dengan selayaknya, dengan mengerahkan segala usaha yang berlandaskan pada niat tulus demi masa depan bangsa yang lebih baik.
Tulisan ini dimuat di Harian Surya, 31 Maret 2004.
Rabu, 10 Maret 2004
Ruh Kemanusiaan dalam Aktivitas Berkesenian
Dalam beberapa tahun terakhir ini, ada sebuah perkembangan menarik dalam disiplin psikologi. Setelah sekian lama dicengkeram oleh paradigma positivistik yang membuat psikologi menjadi kering dan mengabaikan sisi-sisi mendalam dari sisi lain kemanusiaan, kini psikologi mulai bertegur sapa dan bahkan berangkulan dengan beragam dimensi spiritualitas keagamaan. Ini sebenarnya adalah jalan kembali psikologi ke rumah tinggalnya yang sejati. Psikologi mula-mula memang merupakan suatu cabang metafisika yang membahas jiwa manusia. Namun, segi jiwa ini menjadi ditinggalkan, bahkan kemudian tidak diakui, ketika paradigma psikologi eksprimental dan behaviorisme menjadi paham yang berjaya, beriringan dengan pemikiran August Comte (1798-1857) yang mensponsori lahirnya positivisme.
Comte menerangkan istilah “positif” dengan membuat suatu pembedaan antara ‘yang nyata’ (reel) dengan ‘yang khayal’ (chimerique), ‘yang pasti’ (certitude) dan ‘yang meragukan’ (indecision), ‘yang tepat’ (precis) dan ‘yang kabur’ (vague), ‘yang berguna’ (utile) dan ‘yang sia-sia’ (oiseux), dan ‘yang mengklaim memiliki kesahihan relatif’ (relative) dan ‘yang mengklaim memiliki kesahihan mutlak’ (absolut). Pemikiran yang dalam wilayah filsafat menggeser refleksi epistemologis menjadi prinsip metode ilmiah ini menjadikan beberapa segi kemanusiaan menjadi kurang diperhitungkan—untuk tidak mengatakan tidak dihargai.
Jalan pulang psikologi menjadi lapang dimulai ketika Daniel Goleman mempopulerkan istilah EQ (Emotional Quotient, Kecerdasan Emosional) dan kemudian diikuti dengan konsep SQ (Spiritual Quotient, Kecerdasan Spiritual) yang dikampanyekan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall. Berbeda dengan pemikiran yang sudah mapan sebelumnya, yang menempatkan IQ sebagai tolok ukur kecerdasan, berkembang suatu kesadaran baru akan adanya keragaman bentuk kecerdasan. Bahkan, SQ kemudian diakui sebagai the ultimate intelligence.
Ketika masyarakat kebanyakan mengidentikkan kecerdasan manusia dengan kecerdasan IQ semata, yang dihargai hanyalah orang yang cerdas di bidang matematika atau bahasa, sementara orang yang memiliki kemampuan lain kurang mendapat penghargaan yang layak. Padahal tidak jarang orang yang memiliki IQ rendah mempunyai bentuk kecerdasan yang lain (pandai bergaul, berkemampuan dalam bidang kesenian atau olah raga yang baik, dan sebagainya). Fakta ini amatlah merugikan, karena penghargaan terhadap potensi kecerdasan orang-orang semacam ini menjadi kurang.
Adalah kemudian Dr. Howard Gardner, profesor pendidikan di Universitas Harvard, yang menunjukkan fakta bahwa kita tidak hanya memiliki “satu” kecerdasan, tetapi setidaknya tujuh, atau mungkin delapan. Atau mungkin bahkan lebih. Setiap kecerdasan memiliki nilai yang sama penting dan berharga dalam konteks kehidupan kemanusiaan. Kedelapan kecerdasan itu adalah: kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis/logis, kecerdasan visual/spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan fisik, kecerdasan inter-personal, kecerdasan intra-personal, dan kecerdasan naturalis.
Kedelapan macam kecerdasan ini selanjutnya menegaskan bahwa sosok manusia itu menyimpan potensi dan kekuatan yang luar biasa, lebih dari sekadar kemampuan akal-rasionalnya.
* * *
Berbagai penemuan mutakhir di bidang psikologi yang disebutkan secara ringkas tersebut di atas tentu tidak boleh hanya dilihat sebagai suatu perkembangan suatu disiplin ilmu belaka, tetapi juga harus dicermati sebagai suatu fenomena yang lebih besar maknanya, suatu arah penemuan kesadaran kemanusiaan yang semakin menghargai berbagai dimensi manusia yang begitu kaya. Bila sebelumnya kekayaan potensi manusia itu dibekap dalam kerangkeng positivisme dan materialisme, kini langkah pembebasannya telah mulai dilakukan.
Jamak diakui bahwa positivisme dan materialisme telah banyak menjatuhkan korban, terutama korban-korban kemanusiaan. Positivisme telah menumpulkan sensitivitas kemanusiaan dan menenggelamkan kemampuan manusia untuk berempati dan merengkuh makna inti keberadaannya yang hakiki. Bahkan, positivisme yang beroperasi dengan nalar formalistik dan sistem birokrasi kemudian semakin melanjutkan kisah nestapa kemanusiaan tersebut. Namun demikian, perkembangan pemikiran dalam psikologi yang sebenarnya juga diikuti dengan pergeseran paradigmatik dalam bidang yang lain (termasuk sains dan filsafat) telah memberikan arah baru bagi dinamika hidup dan pemaknaan terhadap keberadaan manusia itu sendiri.
Yang penting dicatat dalam soal ini adalah bahwa arah pemikiran tersebut di atas pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu modal dan landasan epistemologis yang semakin mengukuhkan untuk menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk berkebudayaan. Dalam kebudayaan, manusia hadir penuh seluruh dengan segala kemampuan, pergulatan, dan sisi kebebasannya untuk terus berkreasi. Sebagai makhluk budaya, manusia menyimpan kekuatan tak terkira yang dapat menjelma menjadi mahakarya yang luar biasa, baik dengan olahan kekuatan nalar, imajinasi, atau juga intuisi.
Pada titik inilah, kegiatan berkesenian menemukan konteks maknanya yang berharga dalam kerangka aktivitas kebudayaan manusia. Kesenian, dengan beragam wujudnya, adalah salah satu bentuk konkret dari pijar-pijar potensi cipta, rasa, dan karya manusia yang memuat sejumlah nilai tertentu. Di situ, tumpah seluruh upaya manusia untuk mengungkapkan diri, menyingkapkan pengertian, mengkomunikasikan gagasan dan pengalaman (estetik), dan menyatukan kekayaan nuansa hidup dalam suatu wadah yang dapat mempertemukan horison rasa dan pikiran manusia yang berasal dari ruang waktu yang berbeda. Sebagaimana halnya suatu karya semisal buku atau risalah tertentu, sebuah karya kesenian berusaha merawat kedalaman suatu pengalaman perasaan dan gagasan agar dapat melintasi rentang zaman dan aneka ruang yang lebih banyak.
Untuk itulah, setiap karya kesenian, dan karya peradaban yang lainnya, selalu menyimpan sifat keterbukaan terhadap khazanah kebudayaan yang lain, termasuk juga peradaban Islam itu sendiri. Dalam wawancaranya dengan Majalah Horison di tahun 1984, Gus Dur menyebutkan bahwa peradaban Islam itu berwatak eklektik, mampu menyerap karya kebudayaan lain. Gus Dur memberi contoh karya fabel dari al-Zais, yang termaktub dalam karyanya yang berjudul Kitâb al-Hayawân, yang merupakan empat jilid tebal yang memuat fabel-fabel yang banyak diambil dari tradisi Yunani, Romawi, dan India. Atau tentang bagaimana Imam Abû Hanîfah (pendiri mazhab Hanafî) membuat sebuah karya lengkung gapura (arcade) yang diambil dari model di Asia Tengah ketika ia memborong pembangunan pagar kota Baghdad.
Eklektisisme ini, dalam konteks keindonesiaan, juga muncul dalam karya para sunan Walisongo yang menghasilkan khazanah kesenian yang cukup bernilai. Sunan Kalijaga, yang hidup di sekitar akhir abad ke-14 misalnya, dikenal sangat berjasa dalam perkembangan wayang kulit yang bercorak islami seperti sekarang ini. Bahkan, Sunan Kalijaga juga berjasa dalam perkembangan seni suara, seni ukir, seni busana, seni pahat, dan kesusastraan. Dalam sebuah sumber disebutkan bahwa banyak corak batik yang oleh Sunan Kalijaga diberi motif burung. Burung dalam bahasa Kawi disebut kukula, yang kemudian ditulis dalam bahasa Arab menjadi qû dan qîla yang berarti “jagalah ucapanmu”.
Nilai-nilai moral bukanlah sesuatu yang asing dalam karya-karya kesenian. Bahkan, tidak jarang nilai-nilai moral itu menjadi suatu keharusan yang dituntut dalam suatu karya (meski gagasan semacam ini juga ditampik oleh sebagian kalangan yang menghendaki seni independen dan hanya mengabdi untuk seni itu sendiri, tidak usah terlalu dibebani oleh imperatif moral itu menyampaikan nilai tertentu). Lebih jauh lagi, dalam dunia tasawuf kesenian terkadang menjadi media ekspresi untuk menyampaikan gagasan atau pesan-pesan moral, atau bahkan menjadi media untuk menumpahkan ekspresi kecintaan total kepada Tuhan. Hal semacam ini dapat dilihat dalam karya berupa syair-syair yang menggambarkan nuansa keagamaan yang kental, seperti dalam salah satu syair Abû Nuwâs yang terkenal itu (hidup di abad ke-8, pada masa Khalifah Hârûn al-Rasyîd).
Sayangnya, apresiasi kita pada umumnya terhadap khazanah kesenian Islam itu sendiri masih jauh dari cukup. Diduga kuat, ada semacam nuansa subversif yang ditakutkan yang dapat saja muncul dari khazanah kesenian tersebut. Mengambil contoh Abû Nuwâs misalnya, kita kebanyakan hanya mengenal syair karya Abû Nuwâs yang berbunyi Ilâhî lastu li al-firdaws ahlâ... saja. Padahal, ia juga dikenal sebagai penggubah puisi pertama yang mengangkat tema minuman keras atau khamar (khumrayyât). Bahkan, puisi mujuniyyât-nya (yang berisi lelucon dan senda gurau) kadang melampaui batas kesopanan dan merendahkan ajaran agama, sehingga ia juga dicap sebagai penyair fasik atau zindik.
Selain Abû Nuwâs, seorang tokoh sufi terkemuka pendiri Tarekat Mawlawiyyah, Jalaluddin Rumi (1207-1273), yang juga sangat dikenal dengan puisi-puisi cintanya yang memukau, juga pernah dihujat masyarakat karena bersama seorang sahabatnya, Syamsuddin al-Thabrizi, mengembangkan tarian sama’, sebuah tarian berputar yang diiringi dengan musik, sesuatu yang oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu hal yang bertentangan dengan ajaran agama.
Selain sebagai media ekspresi moralitas dan spiritualitas tertentu, kesenian dalam sejarah peradaban Islam juga telah menjadi media untuk merawat salah satu dimensi penting dalam agama Islam itu sendiri. Seni kaligrafi misalnya sering disebut sebagai “seninya seni Islam” (the art of Islamic), suatu kualifikasi dari penilaian yang menggambarkan kedalaman makna yang esensinya berasal dari keseluruhan nilai dan konsep keimanan. Kaligrafi bahkan diakui dengan lebih umum tidak disebut kaligrafi Arab, tetapi kaligrafi Islam, karena pertumbuhan kaligrafi itu berkait erat dengan proses penulisan Alquran dan hadis Nabi. Contoh lainnya adalah syair-syair yang berisi riwayat dan pujian atas Nabi Muhammad saw. yang biasa dilantunkan umat Islam, seperti Burdah yang digubah oleh Ka‘b bin Zuhayr bin Abi Salma.
* * *
Yang menjadi soal saat ini adalah bagaimana memberdayakan berbagai khazanah kesenian Islam yang berharga itu untuk kemudian dibumikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu hal ini pertama-tama mensyaratkan adanya atensi dan apresiasi yang cukup dari kita sendiri. Kita dituntut untuk terus menggali kembali kekayaan khazanah tersebut untuk kemudian dimaknakan dan dikontekstualisasikan dalam era kekinian. Penghargaan yang pantas terhadap karya-karya kesenian itu perlu dilakukan agar berbagai dimensi keilmuan sebagai sebuah karya peradaban Islam mendapat tempat yang layak.
Dari proses ini, kita akan dapat menemukan semangat eklektik, muatan nilai moral, dan kreativitas penciptaan, yang pada akhirnya dapat mengantarkan kita pada suatu pemahaman akan kekayaan karya kesenian sebagai bagian kerja kebudayaan manusia. Yang kemudian muncul dari situ adalah terasahnya sensitivitas kemanusiaan kita untuk menghargai, membaca pesan, dan menggali hikmah pengalaman dari berbagai peristiwa hidup yang berharga. Makna-makna luhur yang diikat, dan bahkan dilekatkan dalam-dalam, di dalam suatu karya kesenian, adalah bagian dari menara peradaban Islam yang mencita-citakan sosok manusia sempurna dan masyarakat utama.
Ini berarti bahwa sejatinya kegiatan berkesenian itu pada dasarnya adalah bagian dari upaya kita untuk melengkapi kualitas kemanusiaan kita, menjadi sosok manusia yang tidak hanya mampu bernalar dengan logika yang benar, tetapi juga menjadi sosok yang bisa menangkap kehalusan pesan kemanusiaan dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup. Sisi-sisi personal-eksistensial ditonjolkan, dipertemukan dengan normativitas dan historisitas setiap karya. Pada momen itulah, penyingkapan makna hakiki menjadi lebih memungkinkan.
Wallâhu a‘lam bishshawâb.
Label: Cultural Issues
Minggu, 29 Februari 2004
Bercermin pada Kisah Rumi
 Judul buku: The Way of Love: Jalan Cinta Rumi
Judul buku: The Way of Love: Jalan Cinta Rumi
Penulis: Nigel Watts
Penerjemah: Hodri Ariev
Penerbit: Gramedia, Jakarta
Cetakan: Pertama, 2003
Tebal: xvi + 237 halaman
Orang-orang ternama memang kerap menyimpan kisah perjalanan hidup yang menarik. Lika-liku kehidupan mereka penuh romantika, pasang-surut, dan menapaki tangga-tangga proses hidup yang tidak selalu mulus. Buku ini adalah sebuah sketsa biografis Jalaluddin Rumi (1207-1273), seorang sufi besar yang dikenal dengan puisi-puisi cintanya yang memukau. Model penyajiannya yang berbentuk novel menjadi daya tarik tersendiri dari buku ini, bagi peminat sufisme pada umumnya maupun pengagum Rumi pada khususnya.
Novel berjudul The Way of Love ini tidak menyajikan seluruh rentang perjalanan Rumi sepanjang hidupnya, tapi lebih menekankan pada romantika persahabatan Rumi dengan Syams dari Tabriz, seorang penyair sufi pengelana. Bisa dimengerti mengapa Nigel Watts, penulis novel ini, memilih untuk membidik segi kehidupan Rumi yang satu ini. Syams adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan spiritual Rumi, bahkan dialah yang mengubah haluan hidup Rumi untuk masuk ke kehidupan sufi.
Kisah novel ini dibuka dengan peristiwa meninggalnya Baha Walad, ayah sekaligus guru pertama Rumi yang sangat dicintai Rumi dan masyarakat kota Konya (sekarang di wilayah Turki), tempat mereka tinggal. Rumi sangat terpukul dengan kematian ayahnya itu. Setelah melewati masa berkabung, tibalah saatnya bagi Rumi untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai syeikh dan pembimbing masyarakat Konya. Rumi merasa tidak siap, sampai kemudian datang Sayyid Burhan, murid dan sahabat ayahnya, yang kemudian menemani Rumi belajar dan menempa diri.
Kehausan Rumi untuk mendalami pengetahuan agama mengantarkannya pada pengembaraan selama tujuh tahun, bersama istri dan anaknya, Burhan, dan Husam sahabatnya. Rombongan kecil ini berkelana mencari orang-orang saleh untuk menimba pengetahuan dan kebijaksanaan. Di akhir pengembaraan itu, Rumi sempat berjumpa Syams di pasar Damaskus yang muncul dengan pakaian compang-camping sebagai pengemis.
Tapi kehadiran Syams yang betul-betul menghujam dalam kehidupan Rumi dimulai ketika Syams datang menemui Rumi di Konya, setelah Syams diberi tahu oleh Ruknuddin Sanjabi, seorang saleh, bahwa putera Baha Walad di Konya akan menjadi sahabatnya mendalami rahasia-rahasia besar Allah.
Persahabatannya dengan seseorang semacam Syams memang begitu dirindukan Rumi. Dimulailah kemitraan mereka berdua menggapai jalan cinta menuju Tuhan. Rumi mabuk di jalan itu. Rumi, yang semula seorang fakih terkemuka dan menjadi guru masyarakat kota Konya, meninggalkan jubah keprofesorannya, menyelam ke kedalaman dunia sufi bersama Syams, Sang Matahari dari Tabriz. Rumi, yang saat itu hampir mendekati usia 40 tahun, mulai menuliskan puisi-puisi cinta sebagai ungkapan dari penemuan-penemuan mistiknya bersama Syams. Kelak, Rumi menulis sebuah buku berjudul Dîwân Syams-I Thabrîz untuk mengenang dan menghormati sahabatnya itu. Karya ini juga diakui menjadi buku pokok untuk memahami ajaran-ajaran sufi Rumi, selain Masnawî.
Namun demikian, kehadiran Syams dalam kehidupan Rumi bagi sebagian masyarakat Konya dianggap sebagai bencana. Syams dipandang menghancurkan kehidupan Rumi, bahkan menjerumuskannya ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Misalnya, bersama Syams, Rumi mengembangkan tarian sama’, sebuah gerakan berputar yang diiringi dengan musik yang kemudian menjadi bagian dari tradisi Tarekat Maulawiyah, yang oleh masyarakat Konya dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Kebencian masyarakat Konya terhadap Syams sempat membuat Syams pergi meninggalkan Rumi. Tapi Rumi mencari Syams dan akhirnya kembali ke Konya. Syams dan Rumi juga pernah diadili di Konya atas dasar tuntutan beberapa masyarakat yang mengeluh atas perilaku mereka.
Akhir yang mengenaskan adalah ketika ternyata Syams dibunuh oleh ‘Ala’uddin dan beberapa santrinya, putera kedua Rumi yang mengkhawatirkan keadaan ayahnya. Sultan Walad, putera sulung Rumi yang menuturkan semuanya. Tapi, rahasia akhirnya tersingkap. Dalam keterpukulan Rumi atas tragedi besar itu, tumbuhlah rasa tawakal dan kesadaran baru bahwa kematangan spiritual dirinya memang harus melewati ujian perpisahan dengan Syams tercinta.
Ini kemudian dirumuskan dalam teori Rumi tentang kefanaan, yang diungkapkan sebagai berikut: “Apakah arti ilmu tauhid? Hendaklah kau bakar dirimu di hadapan Yang Maha Esa. Seandainya kau ingini cemerlang bagai siang hari, bakarlah eksistensimu (yang gelap) seperti malam; dan luluhkan wujudmu dalam Wujud Pemelihara Wujud, seperti luluhnya tembaga dalam adonannya.”
Meski tidak memuat seluruh perjalanan hidup Rumi, buku ini menjadi sangat menarik dalam formatnya sebagai novel. Dengan gaya bertutur yang lincah dan menggugah, kisah hidup Rumi menjadi lebih tersaji dengan penuh kedalaman dan detail yang menyentuh. Sebagai sebuah buku biografi, tidak salah bila Nigel Watts memilih format novel, karena dengan begitu akan bisa menampung dimensi-dimensi emosional dan kedalaman perasaan yang juga lekat dalam ajaran-ajaran dan dunia sufisme. Pembaca akan lebih mudah terlibat dalam suasana hidup tokoh yang dikisahkan, masuk ke dalam kemelut perasaan dan pergolakan batinnya. Mutiara kebijaksanaan akan lebih mudah ditemukan dalam ungkapan-ungkapan yang menyapa hati, seperti dalam novel ini.
Pemilihan fokus cerita pun sangat tepat. Sosok Syams dari Tabriz yang begitu dicintai dan dihargai Rumi bisa menjadi isyarat betapa memang benar bahwa Syams telah mengubah hidupnya. Perjumpaan, persahabatan, ketulusan, dan perpisahan Rumi dengan Syams dapat menjadi cermin cemerlang yang memberi kemilau permata hikmah hidup yang fitri.
Tulisan ini dimuat di Harian Jawa Pos, 29 Februari 2004.
Senin, 16 Februari 2004
Merawat Khazanah Budaya Lokal
Setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, banyak yang berharap bahwa konsep otonomi daerah yang sudah diatur oleh UU No. 22/1999 terutama dalam bidang pendidikan akan dapat dibicarakan dengan lebih leluasa oleh putera-putera daerah sendiri.
Namun demikian, sejauh ini perbincangan soal pendidikan di daerah yang secara khusus ditangani oleh Dewan Pendidikan masih banyak terfokus pada masalah-masalah teknis seperti ketersediaan guru di sekolah terpencil, bantuan dana pendidikan, dan semacamnya. Mungkin saja ini adalah persoalan-persoalan yang memang mendesak di daerah, setelah sekian lama sentralisme politik Orde Baru memburatkan dampak yang mewujud dalam terlantarnya pengelolaan pendidikan terutama di daerah pelosok (baca: pemerataan pendidikan).
Tulisan singkat ini ingin membuka kembali perbincangan tentang salah satu segi dari otonomi pendidikan di daerah—yang salah satu wujudnya adalah dibentuknya Dewan Pendidikan—dalam hubungannya dengan pengelolaan khazanah lokal, khususnya di Kabupaten Sumenep. Perlu ditegaskan bahwa tulisan ini berpegang pada asumsi bahwa praktik pendidikan tidak dapat dilepaskan dari aktivitas pembudayaan. Pendidikan bukan hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi berupa penyediaan tenaga kerja. Usaha pendidikan bukan hanya dilakukan untuk menjadi pelayan bagi sistem ekonomi kapitalistik, karena bila demikian maka pendidikan hanya akan terjerat dalam jaringan sistem ketergantungan global yang menjadi ciri hubungan internasional saat ini (Abdurrahman Wahid, 1984, “Pembebasan Melalui Pendidikan: Punyakah Keabsahan?: Tinjauan Sepintas Atas Sebuah Pendekatan”, kata pengantar dalam buku Paulo Freire, Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan, PT Gramedia, Jakarta, hlm. xvi-xvii).
Bila pendidikan dilihat sebagai kerja kebudayaan, maka salah satu konsekuensinya dalam konteks otonomi daerah adalah perlunya penggalian khazanah kebudayaan lokal untuk dijadikan titik-tolak praktik pendidikan sekaligus dengan menjadikan pendidikan sebagai media sosialisasi khazanah kebudayaan lokal lintas-generasi. Ini tentu saja mengandaikan tersedianya bahan-bahan mentah yang nantinya akan diolah baik untuk kepentingan penanganan pendidikan di daerah.
Contoh konkret yang bisa diajukan dalam konteks Sumenep di sini adalah persoalan sejarah. Sumenep memiliki sejarah yang cukup panjang yang merentang berabad-abad hingga kini. Sejarah suatu masyarakat sebagai bagian dari wujud keberadaban manusia dapat menjadi bagian dari kesadaran warganya untuk bertindak dan mengelola tanah kelahirannya. Sejarah memuat nilai dan menghimpun berbagai kearifan. Persoalannya saat ini sejarah lokal mengalami himpitan luar biasa dari arus globalisasi untuk menemukan ruang sosialisasinya yang efektif. Berbagai fasilitas sosial yang dapat merujukkan pengalaman aktual para generasi baru kepada tatanan nilai para pendahulunya kurang mendapat tempat yang cukup diperhatikan. Museum-museum sudah terlalu kering dan hambar, pelajaran sejarah lokal di sekolah tidak ditemukan, dan kesenian-kesenian daerah kalah dengan musik-musik populer. Pun, tak ada lagi cerita sebelum tidur tentang legenda-legenda masyarakat daerah, karena para orang tua sudah digantikan perannya oleh sang kotak ajaib bernama televisi (M. Mushthafa, “Menghargai Sejarah”, Jawa Pos, 13 April 2003).
Sungguh menggembirakan ketika tersiar kabar melalui situs resmi Pemda Sumenep (www.sumenep.go.id, update berita tanggal 3 September 2003) bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan meluncurkan buku sejarah tentang Sumenep. Buku sejarah yang disusun melibatkan tokoh-tokoh budaya terkemuka seperti H. D. Zawawi Imron, Edi Setiawan, RB. Ahmad Rifa’i, dan sejarawan Edi Mukarram ini akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang cukup menemukan media memadai untuk menyelami sejarah masyarakatnya. Menurut penulis, buku sejarah semacam ini berfungsi tidak hanya “untuk meluruskan kebenaran sejarah Sumenep, karena dilihat dari beberapa sumber buku sejarah yang ada terjadi kesimpang siuran,” seperti dinyatakan oleh Kepala Dinas Pariwisaata dan Kebudayaan Sumenep, Iskandar Sulkarnain, tapi juga dapat menjadi pengaya wawasan dan sudut pandang sebagai suluh untuk membawa Sumenep ke masa depan yang lebih gemilang.
Berkaitan dengan hal ini, tidak ada salahnya bila kemudian dibuka kemungkinan dimanfaatkannya buku sejarah Sumenep tersebut untuk dijadikan sebagai bagian dari pelajaran formal di sekolah di Kabupaten Sumenep. Kemungkinan ini akan menarik dilanjutkan untuk didiskusikan bila menimbang beberapa hal (M. Mushthafa, “Pendidikan Nilai dan Khazanah Lokal”, Kompas, 24 April 2003). Pertama, dari segi kegunaan, dimasukkannya pelajaran sejarah lokal (Sumenep) di sekolah akan dapat menjadi bagian dari proses sosialisasi yang saat ini cukup sulit menemukan media yang berdaya guna. Khazanah sejarah yang juga bisa disebut tradisi ini pada titik tertentu dapat menjelma visi dan orientasi bersama yang dapat mengarahkan gerak maju masyarakat. Dalam ranah tersebut pula dimungkinkan terjadinya proses dialog-kreatif baik bersifat personal-eksistensial maupun sosial-kolektif antara kondisi konkret kekinian yang dihadapi masyarakat dan nilai-nilai keberadaban yang termuat dalam sejarah yang menjadi muasal akar hidup masyarakat itu sendiri. Kedua, saat ini juga telah tersedia sejumlah sumber tentang Madura pada umumnya selain buku sejarah Sumenep yang diterbitkan Pemda tersebut, seperti disertasi Prof. Kuntowijoyo berjudul Madura 1850-1940 yang diterbitkan oleh Penerbit Mata Bangsa Yogyakarta (ulasan tentang buku ini, lihat M. Mushthafa, “Determinasi Ekologi dalam Sejarah Madura”, Sinar Harapan, 13 September 2003), Carok karya Dr. A. Latief Wiyata yang diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta (ulasan tentang buku ini, lihat M. Mushthafa, “Carok, Ketika Malo Tada’ Ajina”, Gatra, 14 April 2002), Lebur yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia Jakarta, atau buku klasik Hubb de Jonge yang diterbitkan oleh Gramedia, Madura dalam Empat Zaman.
Belum lagi bila kemudian Pemerintah Daerah Sumenep memiliki political will untuk melibatkan kalangan muda, sebutlah misalnya kalangan mahasiswa, untuk bergabung dalam proses penggalian khazanah lokal ini. Wujudnya bisa dengan menginventarisasi karya-karya akademik atau penelitian semacam skripsi yang berhubungan dengan Sumenep untuk kemudian diolah dan dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah. Bila ini dilakukan, akan terjadi keberuntungan ganda (simbiosis-mutualisme) antara pemerintah dan kalangan muda Sumenep: para muda akan merasa dihargai dengan kerja budaya yang dilakukannya dan pemerintah dapat memetik manfaat langsung dari mereka dengan himpunan data dan sejumlah analisis dari beragam perspektif yang bisa saja menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan publik tertentu. Ini berarti,
* * *
Hal-hal yang sudah dipaparkan secara singkat dalam uraian di atas bertolak dari asumsi bahwa saat ini kita sudah memiliki seperangkat aturan, lembaga, maupun juga keleluasaan yang dapat mengakomodasi kekayaan khazanah lokal, terutama dalam bidang pendidikan. Tak ada salahnya bila kemudian perangkat-perangkat tersebut lebih dimaksimalkan fungsi dan kegunaannya, dan dijadikan momentum untuk memperluas
Pada saat kecanggihan teknologi informasi dan globalisasi menyedot
Tulisan ini dimuat di Harian Radar Madura, Minggu, 15 Februari 2004.